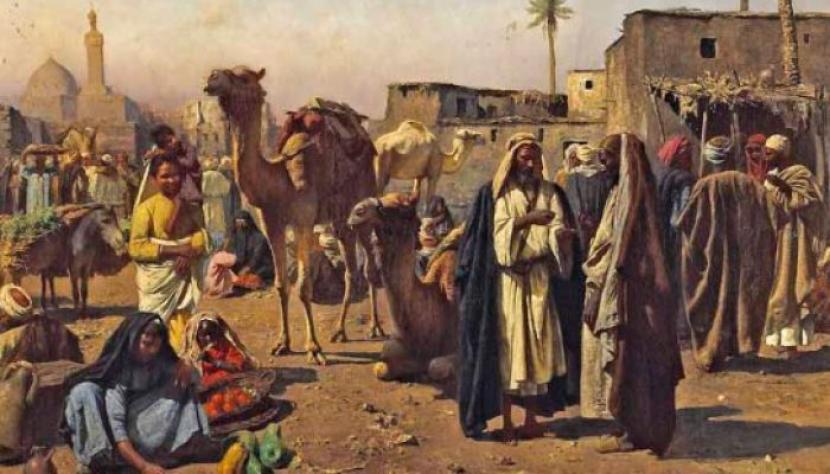REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dr Ahmad Choirul Rofiq, Dosen Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Ponorogo.
Al-Qur’anul Karim menegaskan secara jelas bahwa kemuliaan derajat ulama (QS. 58: 11) ditentukan oleh kedalaman ilmu, kualitas pribadi, dan keluhuran budi pekertinya. Dengan pengukuhan langsung dari Allah Swt tersebut, maka keberadaan ulama dipandang mulia bukan karena banyaknya limpahan harta yang ada padanya, kedudukan mentereng jabatan formal yang diembannya, maupun banyaknya penghargaan yang diterimanya dari pemerintah.
Sejarah telah merekam dengan lengkap kisah para ulama yang tetap ditinggikan derajatnya sepanjang zaman meskipun mengalami ujian berat disebabkan keteguhan sikap yang dipeganginya tatkala di depan penguasa politik.
Di dalam karyanya berjudul Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, KH Moenawar Chalil (1908-1961) dari Kendal, Jawa Tengah, menuturkan beratnya ujian yang dihadapi oleh Imam Hanafi atau al-Nu‘man ibn Tsabit Abu Hanifah (81-150H/700-767M), Imam Malik bin Anas (93-179H/712-798M), Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi’i (150-204H/767-820M), dan Imam Ahmad bin Hanbal (164-241H/780-855M).
Mereka inilah figur-figur ulama panutan yang berpendirian sangat kuat dan tidak gentar tatkala berhadapan dengan penguasa.
Dikisahkan bahwa Imam Hanafi pada tahun 130 H ditawari oleh Yazid bin ‘Amr, Gubernur Iraq, agar bersedia menjabat sebagai kepala urusan perbendaharaan negara (baitul mal), tetapi tawaran jabatan itu ditolaknya.
Akibatnya, beliau dihukum cambuk karena tidak menuruti perintah si penguasa. Kemudian pada tahun 136 H beliau dipanggil ke Baghdad, ibukota Kerajaan ‘Abbasiyyah, oleh Khalifah Abu Ja’far al-Manshur untuk menduduki jabatan hakim agung (qadhi).
Namun beliau bersikukuh untuk tidak mau menerima jabatan itu sehingga beliau dijatuhi hukuman berat sampai akhirnya beliau wafat di dalam penjara secara menyedihkan.
Keteguhan sikap ulama juga ditunjukkan oleh Imam Malik yang sempat merasakan kejamnya cambukan aparat penguasa ketika beliau tidak mau menuruti kehendak Gubernur Madinah supaya beliau mengubah keputusan fatwa fiqih yang diputuskannya untuk disesuaikan dengan keinginan pemerintah.
Selanjutnya beliau bahkan pernah menolak tawaran Khalifah al-Manshur dan Harun al-Rasyid agar berkenan meninggalkan Madinah dan pindah ke Baghdad untuk menduduki jabatan keagamaan sebagai hakim negara.
Adapun ujian yang dialami Imam al-Syafi’i adalah sewaktu beliau ditangkap aparat pemerintah karena dituduh oleh orang-orang yang dengki padanya bahwa beliau bergabung dengan gerakan Syi’ah di Yaman dalam melawan pemerintahan ‘Abbasiyyah. Akibatnya, beliau dibawa ke hadapan Khalifah Harun al-Rasyid dalam keadaan terbelenggu.
Setelah melalui penyelidikan seksama, Harun al-Rasyid kemudian membebaskan Imam al-Syafi’i dari segala tuduhan negatif dan menghadiahkan 2.000 dinar kepadanya yang seketika itu langsung ditolaknya. Tidak hanya itu, beliau pun menolak keputusan khalifah yang mengangkatnya sebagai pejabat kehakiman di Yaman.
Beliau selanjutnya memilih untuk berpindah ke Mesir sampai akhir hayatnya di sana sebagai ulama besar yang disegani.
Penolakan jabatan formal keagamaan ternyata juga dilakukan oleh Imam Ahmad yang tidak berkenan diangkat sebagai hakim oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Kemudian pada masa pemerintahan Khalifah al-Ma’mun terjadilah peristiwa tragis yang menimpa Imam Ahmad, yakni inquisisi (mihnah) terhadap keyakinan teologis.
Saat itu kelompok Mu’tazilah sedang mendapatkan dukungan besar dari khalifah, termasuk pandangan teologis Mu’tazilah yang menyatakan bahwa al-Qur’an itu makhluk. Aparat pemerintah secara gencar melakukan intimidasi kepada siapa saja yang tidak menerima doktrin tersebut.
Di antara ulama yang berseberangan dengan penguasa yaitu Imam Ahmad (yang berfatwa bahwa al-Qur’an itu bukan makhluk karena ia merupakan Kalam Allah Swt) sehingga beliau dimasukkan ke penjara dan merasakan pedihnya hukuman selama bertahun-tahun.
Penderitaan beliau yang telah berusia lanjut itu terus berlanjut sampai pemerintahan al-Mu’tashim dan al-Watsiq. Kebebasan beliau diperolehnya setelah Khalifah al-Mutawakkil naik tahta dan menetapkan Ahlus Sunnah wal Jama’ah sebagai mazhab resmi negara (sebagai ganti Mu’tazilah).
Demikianlah, kita menyaksikan keteladanan kemandirian ulama dan kekokohan sikap mereka dalam berpendirian yang tidak menjadikan kemuliaan derajatnya berkurang sedikitpun.
Seorang ulama hakiki memang semestinya memegang erat idealisme dan senantiasa memperjuangkan prinsip ideal itu, meski di hadapan pemangku kekuasaan sekalipun.