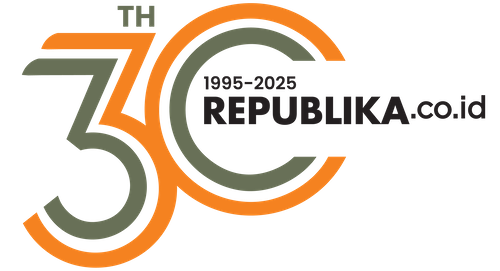REPUBLIKA.CO.ID,
Oleh: Denny JA
Di era Google dan Hak Asasi Manusia (HAM), untuk hidup yang harmoni serta mendalam, pertanyaannya bukan lagi apa agamamu? Juga bukan lagi apakah kau tidak beragama? Tapi bagaimana kamu menafsirkan agama atau paham (ideologi) yang kamu yakini?
Ini era di semua agama tersedia spektrum. Ada tafsir yang pro hak asasi yang membangun peradaban. Dan ada tafsir yang otoritarian, yang membajak agama itu menuju kekerasan. Itulah sebabnya di semua penganut agama tercatat konflik berdarah, perang bahkan terorisme.
Itu respons cepat saya melihat riset mengenai agama di zaman now. Kini terdaftar lebih dari 4.200 agama. Satu agama bahkan terpecah pula kepada banyak aliran (Schism).
Namun siapapun tak bisa menolak fenomena yang dahsyat dari agama besar. Agama seperti Kristen, Islam, Buddha, Hindu sudah hadir lebih dari 1.500 tahun. Agama itu juga diyakini ratusan juta manusia hingga di atas satu miliar populasi.
Bahkan ideologi modern seperti Komunisme, Fasisme, dan lain lain, hanya bertahan kurang dari seratus tahun saja. Setelah itu ideologi itu layu.
Hanya dengan melihat fenomena itu, bahkan bagi mereka yang semata mata ingin memahami agama secara ilmiah, dan membuang sisi wahyu ilahiah, tetap terpesona. Ada sesuatu dalam agama besar itu yang membuatnya bertahan ribuan tahun. Ada yang sentral dalam agama besar itu yang menyentuh kedalaman manusia, yang membuatnya selalu disegarkan kembali.
Riset yang dibuat lembaga terkemuka berpusat di Amerika Serikat, Pew Research Center (PRC), 2015, bahkan menyebutkan angka. Di masa depan agama ini tidak menghilang, namun justru bertambah.
Bahkan penganut paham yang atheis, agnostik dan non-religius akan berkurang. Pendukung paham non-agama ini, akan menurun dari 16,4 persen di 2010 menjadi hanya 13,2 persen saja di tahun 2050.
Ini yang juga penting! Di tahun 2070, menurut PRC, Islam akan menjadi agama yang penganutnya terbesar di dunia. Jumlah penganut Islam akan melampaui jumlah penganut agama Kristen dan juga pendukung paham yang atheis, agnostik dan non-religius.
Di usia 55 tahun, prinsip hidup dan zikir /La Ilaha Illallah/ begitu menggetarkan saya. Mendalam saya merenung. Apa arti dan signifikansi /La Ilaha Illallah/ di ruang publik, dalam era Google dan Hak Asasi Manusia?
Pertama kali yang saya ingat adalah Eric Fromm. Ia seorang ahli psikologi dalam tradisi psikoanalisis. Pandangannya banyak dipengaruhi oleh Sigmun Freud. Namun Fromm tumbuh berbeda karena ia juga menjadi filsuf dan sosiolog. Fromm hidup di tahun 1900-1980.
Ujar Fromm, psikologi manusia tak bisa menghindari dari Tuhan dan agama. Apapun manusia akan meyakini Tuhan dan memeluk agama. Manusia bisa saja menolak konsep Tuhan dan agama versi lama. Tapi kebutuhan psikologinya membuat manusia menciptakan konsep Tuhan dan konsep agama baru.
Fromm mengartikan Tuhan sebagai pusat orientasi hidup. Secara psikologis, manusia memerlukan pusat orientasi. Ia jadikan pusat orientasi itu hal utama.
Agama besar mengajarkan pusat orientasi itu adalah Yahwe, atau Allah, atau Tuhan, atau Budha, atau dewa. Ideologi modern mungkin saja meruntuhkan pusat orientasi itu. Namun pasti akan ada pusat orientasi baru entah itu negara, kapital, partai, atau tokoh. Itulah aneka “Tuhan” yang baru.
Hal yang sama dengan agama. Fromm mengartikan agama sebagi sistem nilai yang memberikan panduan pada manusia menuju pusat orientasi itu. Lahirkah sistem nilai Hindu, Buddha, Judaisme, Kristen, Islam dan sebagainya.
Sekali lagi, pemikir modern bisa saja meruntuhkan sistem nilai bahkan agama. Namun pasti, psikologi manusia membutuhkan sistem nilai pengganti. Itulah “agama” baru baik bernama ideologi, paham ataupun filsafat hidup.
Pentingnya La Ilaha Illallah, prinsip tauhid dalam Islam, justru terasa dalam kerangka Eric Fromm. Prinsip tauhid: tiada tuhan selain Allah, justru menegasi tuhan-tuhan kecil atau palsu.
La ilaha Illallah menjadi konsep pembebasan jiwa manusia yang sangat mendasar. Konsep itu menolak menjadikan manusia berorientasi pada tuhan kecil (harta, negara, partai, tokoh, guru suci, dan sebagainya). Kodrat manusia lebih tinggi untuk sekedar menjadi budak dan penghamba tuhan kecil itu.
Dengan La Ilaha Illallah, prinsip ini menjadikan Allah semata sebagai pusat orientasi. Tapi apakah Allah itu? Itu adalah kesempurnaan paling jauh yang bisa diimajinasikan manusia. Yang terbatas (manusia) mustahil bisa memahami seluruhnya yang tak terbatas (Allah). Tapi untuk kepentingan praktis, Allah dapat didekati dengan proksi atau permisalan saja.
Dengan menjadikan Allah semata sebagai pusat orientasi, maka manusia diletakkan dalam makom paling tinggi, dibebaskan dari orientasi hidup yang mendangkalkan. Apalagi Allah itu dipahami secara proksi sebagi segala yang maha baik (maha mampu, maha adil, maha kasih, maha tahu, dll)
Dengan berorientasi pada Allah (yang maha adil, maha tahu, maha kasih, maha suci, dll), manusia pun memulai perjalanan hidup menuju pencapaian itu hingga ajal menjemput. Manusia terus dibuat mencari, belajar dan melatih diri untuk tahu (karena Allah maha tahu), untuk adil (karena Allah maha adil), untuk mampu (karena Allah maha mampu), untuk kasih dan penuh cinta (karena Allah maha kasih). Dan sebagainya.
Inilah implikasi psikologis dari La Ilaha Illallah. Sebuah implikasi sikap hidup yang sangat mendasar, penting dan mendalam.
Namun apa arti La Ilaha Illallah itu di era Hak Asasi Manusia dan Google? Dalam sejarah konsep itu bisa ditafsir secara otoriter yang justru membawa pada kekerasan. Namun bisa juga ia ditafsir secara berbeda yang membawa pada kedamaian, harmoni, dan hidup positif.