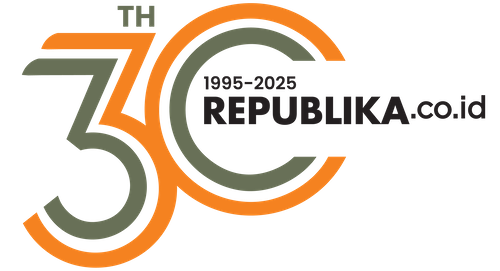REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Azyumardi Azra
Ramadhan 1433 Hijriah. Kedamaian ibadah puasa belum juga terwujud di Suriah. Sebaliknya, perang di antara pasukan pemerintah Bashar al-Assad melawan rakyatnya sendiri justru terus kian meningkat dan seolah memasuki fase sangat menentukan.
Korban terus berjatuhan. Berbagai lembaga humaniter internasional memperkirakan lebih 20 ribu warga Suriah tewas dalam gejolak kekerasan yang berkecamuk di negara ini menyusul berlangsungnya demonstrasi besar ala "Arab Spring" pada 15 Maret 2011. Dan, hampir dua juta warga Suriah menjadi pengungsi di wilayah perbatasan Turki dan Yordania.
Melihat berlanjutnya kekerasan di Suriah, mendorong munculnya pertanyaan tentang efektivitas hu -kum humaniter internasional (HHI) dan juga hukum humaniter internasional Islam (HHII) dalam melindungi warga nonkombatan, khususnya orang-orang lanjut usia, kaum perempuan, dan anak-anak.
Mengapa HHI dan HHII tidak diindahkan para penguasa negara Muslim semacam Suriah? Pertanyaan selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan negara-negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas Muslim dan masyarakat internasional lainnya? Dalam kaitan pertanyaan- pertanyaan tersebut, menarik melihat kembali pemikiran dan konsep Islam yang dalam masa kontemporer disebut sebagai HHII.
Dengan menggunakan istilah HHII terlihat bahwa kalangan negara, ulama, dan pemikir Islam, khususnya di dunia Arab, melihat adanya perbedaan dan distingsi antara paradigma humaniter Islam dan hukum humaniter internasional. Sedangkan, di Indonesia, yang berpenduduk mayoritas Muslim, terlihat absennya pembicaraan tentang HHII di kalangan para ulama dan pemikir Islam. Dengan begitu, baik negara Indonesia maupun kalangan pemuka, ulama, dan pemikir Islam negeri ini secara praktis menerima paradigma dan konsep HHI.
Apa sesungguhnya paradigma dan konsep HHII tersebut? Tidak banyak literatur bahasa Indonesia yang tersedia tentang subjek ini. Karena itu, pemahaman kita tentang HHII sangat terbantu dengan penerbitan buku Islam dan Hukum Humaniter Internasional (Bandung: ICRC dan Mizan, 2012). Karya yang merupakan terjemahan dari Maqalat fi al-Qanun al-Duwali al-Insan wa al-Islam (ICRC, 2012) ini memberikan perspektif cukup komprehensif tentang HHI dan HHII.
Dalam pemikiran klasik Islam, hukum humaniter merupakan genre tersendiri yang cukup kaya, dihasilkan para ulama fikih siyasah semacam Abu Umar 'Abd al-Rahman al-Awza'i (lahir 77H/707), Abu Yusuf (113-182H/731-798M), dan Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani (132- 189H/748-804M), dan juga Imam al Syafii (150- 204H/767-820M).
Genre yang mereka hasilkan umumnya dikenal sebagai siyar, yang sebenarnya menyangkut tidak hanya hukum humaniter terkait konflik dan perang baik di suatu negara tertentu maupun di antara beberapa negara, tetapi juga berbagai konsep tentang tata relasi antara penguasa dengan rakyatnya di dalam sebuah negara Muslim dan hubungan internasional dan dalam segi tertentu juga diplomasi.
Paradigma dan konsep klasik siyar tentang hukum humaniter umumnya berangkat dari pandangan Islam tentang kemuliaan harkat manusia yang jasmani dan ruhaninya harus dipelihara dan dilindungi dalam keadaan apa pun, khususnya perang.
Terdapat ketentuan-ketentuan tentang keharusan perlakuan manusiawi terhadap kombatan yang menjadi tawanan perang dan juga tentang kewajiban melindungi warga sipil, objek sipil, harta benda, dan rumah ibadah. Sebagian besar paradigma dan konsep siyar sangat relevan dengan HHI yang diadopsi menjadi Konvensi Jenewa 1949 yang mencakup Konvensi Jenewa I tentang perbaikan kondisi anggota angkatan perang yang sakit dan terluka; Konvensi Jenewa II perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang terluka dan sakit serta anggota angkatan laut yang kapalnya tenggelam di perairan; Konvensi Jenewa III tentang perlakuan terhadap tawanan perang; dan Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan warga sipil dalam perang.
Dalam perkembangannya, Konvensi Jenewa ini pada 1977 dilengkapi dengan Protokol Tambahan I dan II. Kedua Protokol ini kembali menegaskan tentang kewajiban untuk memperlakukan tawanan perang secara manusiawi dan adil tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, agama dan kepercayaan, ideologi politik, jenis kelamin, kebangsaan, dan status sosial.
Dalam banyak segi, HHI dan HHII tumpang tindih; dan HHII memberikan perspektif spiritualisme ke dalam humanitarianisme universal. Karena itu, perbedaan pokok di antara keduanya hanyalah bahwa jika HHI lebih banyak berdasarkan pada pandangan falsafi tentang humanisme universal. Sebaliknya, HHII berangkat dari pandangan keagamaan Islam tentang kemanusiaan sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT dengan sebaik-baik penciptaan.
Dari perspektif terakhir ini, umat dan negara Muslim sepatutnya menjadi contoh aktualisasi humani - tarisme dalam situasi konflik, kekerasan, dan perang. Sayangnya, hingga kini masih banyak negara Muslim--khususnya yang terakhir rezim Suriah Bashar Assad--gagal mewujudkan ketentuan fikih siyasah tentang siyar dan juga sekaligus HHI, semata-mata hanya karena ingin mempertahankan status quo kekuasaannya.