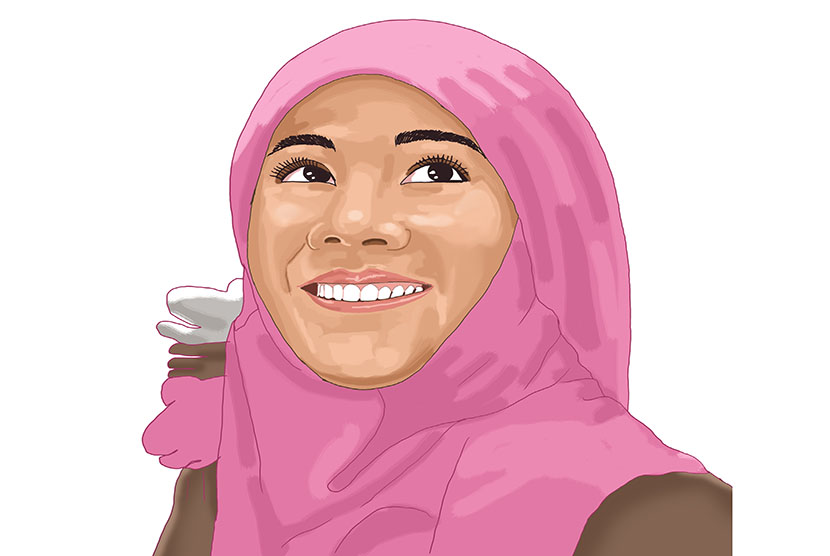REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Asma Nadia
Saya tercengang. Jantung berdetak lebih cepat sementara kaki terasa lemas. Kedua mata terpaku pada potret sebuah bangunan yang diselimuti asap hitam pekat nan membubung tinggi. Foto yang dikirimkan seorang karyawan Toko Asma Nadia melalui whats app. Pada bagian bawah dibubuhi teks singkat: Kebakaran pagi ini di sekitar kantor Asma Nadia.
Lokasi yang disebutkan, jaraknya tak sampai setengah kilometer.
Dari berita yang belakangan merebak, kabarnya kebakaran hebat itu bermula dari ulah entah siapa yang membakar ban. Percikan karet yang terjilat api meluas cepat, melahap bagian yang lain, lalu dengan cepat tak terbendung, merembet ke mana-mana.
Bahkan, sekadar melihat foto, benak siapa pun akan mencerna dan dengan cepat berempati. Seketika terproyeksi betapa pilu derita yang ditanggung keluarga korban. Terbayang anak yang tidak bisa bersekolah karena orang tuanya kehilangan semua harta benda dan sumber penghasilan.
Bisnis yang bertahun-tahun dibangun dari tetes keringat, kerja keras, dan sejumlah dana, barangkali pun pinjaman yang masih harus dikembalikan, perjuangan sekian lama musnah hanya dalam hitungan detik. Belum kemungkinan timbulnya korban jiwa.
Saat itu saya dan suami berpandangan dan ternyata dalam waktu yang sama mengetik kalimat senada di grup whats app.
"Apakah ada yang bisa membantu ke sana?"
Saya meminta staf meninggalkan kantor dan ikut membawa ember, air, atau apa saja untuk urun tangan meredakan amukan sang jago merah. Suami bahkan berniat membawa alat pemadam kebakaran di rumah berjaga-jaga barangkali diperlukan dan bisa membantu.
Syukurlah, tidak berapa lama kemudian kami mendapat kabar bahwa api yang mengganas sudah berhasil dijinakkan. Tidak urung, sedikitnya lima rumah atau tempat usaha rata dengan tanah dan menjadi arang setelah petugas pemadam kebakaran berhasil menguasai medan.
Kebakaran, jelas sebuah tragedi yang menyisakan catatan derita, korban yang harus diringankan. Paling tidak agar mereka bisa shalat dan punya pakaian layak pakai, juga sesuatu untuk dimakan.
Namun, ternyata sekelumit cerita lain menanti dan terasa lebih miris. Bukan, bukan karena jatuhnya korban jiwa, sebab syukurlah tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Bukan juga terkait kerugian materi.
Seorang karyawan yang sempat datang untuk melihat kemungkinan membantu, bercerita betapa dia terperangah saat berada di dekat lokasi kebakaran demi melihat keramaian ratusan orang yang menonton kejadian tersebut.
Uniknya mereka bukan sibuk membantu, atau berlari ke sana kemari mencari air, atau berusaha menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan milik keluarga yang kemalangan. Di antara keramaian tersebut tampak sang pemilik toko berusaha meredakan lidah api dengan sisa tenaga hingga akhirnya terduduk pasrah sebab kehabisan tenaga dan tidak memiliki air yang tersisa.
Keramaian ratusan orang, batin saya. Harusnya kabar baik, pasti ada di antara mereka yang membantu si pemilik toko. Namun, karyawan saya membantah.
Menurut dia, bisa dihitung yang berupaya membantu karena sebagian besar kerumunan tampak sibuk. Ya, semua sibuk dengan telepon genggam mereka.
Ada yang sekadar memotret kejadian lalu mengunggahnya ke media sosial. Mungkin untuk menginfokan ke masyarakat luas, siapa tahu ada di antara yang tersapa, punya keluarga di lokasi kejadian. Saya masih berprasangka baik.
Namun, emoticon sedih di grup whats app, membuat saya tidak mengerti.
“Kebanyakan pada foto-foto selfie bunda.”
Apa? Sempat-sempatnya melakukan swafoto dengan latar gedung yang sedang terbakar?
“Ada juga yang live insta story, bun,” lanjut karyawan kami yang lain menambahkan. “Mending serius, ini sambil cengar-cengir dan merapikan belahan rambut.”
Inna lillahi.
Atmosfer penderitaan dan kesengsaraan sedemikian pekat, bagaimana mungkin masih ada yang bisa menemukan ruang untuk menjadikannya alat meng-upgrade eksistensi di medsos?
Tidakkah seharusnya musibah hebat yang terjadi justru menjadi sarana bagi masyarakat untuk menghidupkan kembali iklim gotong royong. Inilah saat tepat untuk bahu-membahu mengangkat ember secara estafet untuk meredakan api bersama-sama. Seharusnya demikian yang terjadi. Kenyataannya tidak.
Pada tangan-tangan sebagian besar masyarakat yang berkerumun, tidak ada ember berisi air atau benda-benda milik korban yang diselamatkan, tetapi erat tergenggam ponsel yang dilengkapi kamera.
Mendadak saya merasa begitu berjarak pada masa lalu.
Saya lupa kapan terakhir mendengar bunyi kentongan yang diketuk bertalu-talu, sebagai isyarat agar warga sekitar bergerak untuk meredakan api. Teriakan kepanikan yang semestinya terdengar bukan saja dari lisan mereka yang ditimpa musibah, melainkan dari khalayak yang juga bergerak cepat untuk membantu.
Sebagai ganti saya bayangkan suara klik shutter kamera pada ponsel yang ditekan untuk mengabadikan bukan peristiwa lagi, melainkan diri dengan latar peristiwa yang terbilang jarang.
Ah, ke mana perginya nurani?
Sejak kapan dia tak lagi menetap di dalam diri?
Ke mana menguapnya kepedulian? Kepekaan?
Inikah dunia yang kita tempati sekarang?
Benar zaman sudah berubah, tapi bukan berarti semua perubahan harus diterima. Setiap perubahan sejatinya membawa kepada sebuah kebaikan, sekalipun di sisi lain tak jarang diiringi berbagai efek negatif.
Tugas manusia untuk mengambil sisi positif, manfaat dari sebuah perubahan dan kemajuan dengan sebaik mungkin. Sebaliknya, tugas kita pula untuk memastikan meminimalisasi atau malah menghindari efek negatif dari laju perubahan.
Sebuah potret zaman yang memprihatinkan, terbentang di depan mata. Ancaman besar.
Dan tanpa introspeksi, lalu upaya keluarga untuk memastikan diri dan anak-anak kita menggenggam empati dan kepedulian, juga agama lebih erat dari kemajuan zaman dan teknologi, maka tidak terbayangkan betapa miskinnya hati dan nurani yang dimiliki generasi penerus kelak.
Sudah banyak yang mengingatkan, bagaimana media sosial sebagai bagian dari gerak teknologi telah mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Kita sibuk berinteraksi dengan orang yang tak tampak, sedangkan orang tua, kakak, dan adik yang bersisian atau teman yang duduk satu meja, malah terabaikan. Semoga tidak!