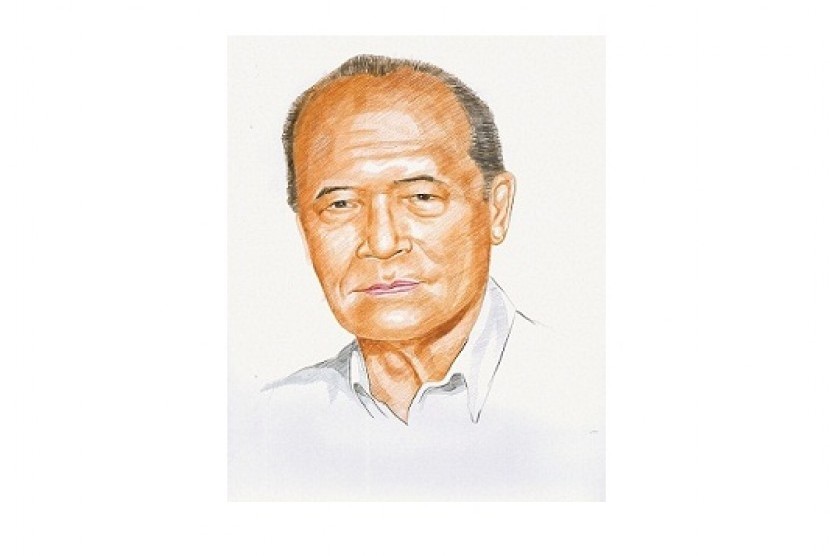REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Ahmad Syafii Maarif
Kasus Aceh dan Papua sesungguhnya dapat dicari akar utamanya karena pengingkaran sila ini dan sila kelima berupa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Begitu rapuhnya penghayatan kita terhadap sila kedua ini, ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI)/ tenaga kerja wanita (TKW) yang tertindas sewaktu akan berangkat, di tempat bekerja, dan setelah pulang ke Tanah Air seperti tidak mendapat perlindungan yang memadai, khususnya dari instansi yang terkait.
Padahal, tenaga kerja ini telah memasukkan triliunan rupiah ke devisa negara saban tahun. Penderitaan mereka yang tidak berujung ini telah menjadi pengetahuan kita semua, tetapi nasib mereka tetap saja tak tertolong.
Sila ketiga adalah “Persatuan Indonesia”. Ini menyangkut masalah integrasi nasional yang telah diupayakan sejak awal abad ke-20. Adalah sebuah pandangan yang ahistoris jika kita menganggap bahwa persatuan bangsa sebagai sesuatu yang given dan final dengan adanya Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945.
Dua tonggak sejarah ini hanyalah modal utama untuk melangkah selanjutnya dalam upaya mengisi kemerdekaan. Masalah integrasi nasional yang terganggu akhir-akhir ini disebabkan oleh sikap salah pandang itu. Kita lupa bahwa masalah persatuan bangsa adalah sebuah proses yang tidak pernah selesai. Karena dia bergerak terus, maka kelalaian kita selama ini dalam memelihara dan merawatnya telah memicu munculnya gejala disintegrasi yang sangat berbahaya bagi hari depan Indonesia.
Lagi-lagi, di sini masalah keadilan yang telantar sekian lama menjadi faktor pokok mengapa kekuatan disintegratif mendapat peluang untuk memperjuangkan kemerdekaan daerahnya, lepas dari bingkai Republik Indonesia yang sudah kita bangun dengan susah payah. Pendekatan militer semata untuk mencegah gerakan separatis ini tidak akan pernah efektif selama inti persoalannya berupa keadilan tetap saja tidak dihiraukan.
Sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan” sebagai sila keempat merupakan sumber primer bagi sistem demokrasi yang ingin ditegakkan di Indonesia. Tetapi, karena pengaruh subkultur semifeodal atau sikap kebaratbaratan di kalangan sementara elite bangsa, kita sampai hari ini belum lagi mampu menciptakan sebuah sistem politik demokrasi yang kuat dan sehat sesuai dengan kondisi Indonesia.
Dalam sistem Demokrasi Liberal (1950-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966), dan Demokrasi Pancasila (1966-1998), mereka yang mengaku sebagai pendukung demokrasi lebih banyak dalam teori, sementara dalam realitas politik mereka tidak toleran, sempit dada, dan mau menang sendiri. Akibatnya jelas, demokrasi tidak semakin mendekatkan bangsa kepada tujuan kemerdekaan: terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Demokrasi tanpa rasa tanggung jawab terhadap kepentingan yang lebih besar dan budaya lapang dada bukan penyelesaian bagi hari depan Indonesia. Sementara, sistem otoritarian telah membunuh kekuatan-kekuatan kreatif yang pernah dimiliki bangsa ini.
Sila kelima adalah “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sebuah sila yang manis sekali, tetapi telah kita sia-siakan sejak Proklamasi. Sedikit sekali perilaku kita yang dibimbing oleh sila ini dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keretakan antara kata dan laku semakin menganga dari hari ke hari, dari sistem politik yang satu ke sistem yang lain. Kelatahan kita dalam menghayati dan melaksanakan sila ini sesungguhnya adalah faktor yang paling krusial mengapa masalah integrasi nasional belum semakin mantap dari waktu ke waktu, tetapi kita tidak juga mau belajar dari keteledoran ini.
Pada era Demokrasi Liberal dengan kekuasaan partai yang begitu besar, kabinet jarang sekali yang berumur panjang. Jika berlaku perbedaan pandang antara pemimpin partai yang belum tentu mengenai masalah mendasar, langsung kabinet dijatuhkan untuk diganti oleh kabinet yang baru dengan nakhoda yang lain. Kejadian ini berlangsung berkali-kali sehingga kabinet tidak pernah berusia sampai lima tahun. Ganti kabinet, ganti kebijakan dan program. Pemborosan energi politik terjadi berulang-ulang, tanpa rasa dosa terhadap bangsa dan negara.
Di era Demokrasi Terpimpin, kabinet dapat bertahan sampai enam tahun, tetapi demokrasi itu sendiri harus takluk ke bawah sistem otoritarian dengan subkultur semifeodal yang ada di belakang. Partai-partai yang tidak sejalan dengan penguasa disingkirkan untuk kemudian dibubarkan. Di bawah sistem ini, demokrasi tinggal nama dan Pancasila hanyalah dipakai untuk pembenaran terhadap libido kekuasaan tanpa kontrol.
Politik menjadi panglima, aspek kenegaraan yang lain harus tunduk kepada kehendak panglima. Sistem ini kemudian berantakan dan berguguran ibarat rumah yang terbuat dari kartu (untuk meminjam Bung Hatta) melalui tragedi berdarah dalam bentuk G30S/PKI. Entah berapa puluh ribu nyawa anak bangsa yang tertumpah sebagai biaya dari konflik politik dengan skala nasional. Tragedi ini berlaku enam tahun setelah Dekrit 5 Juli 1959 dengan mengukuhkan Pancasila dan UUD 1945, tetapi dengan mengorbankan Majelis Konstituante yang dinilai gagal menjalankan tugas konstitusionalnya.