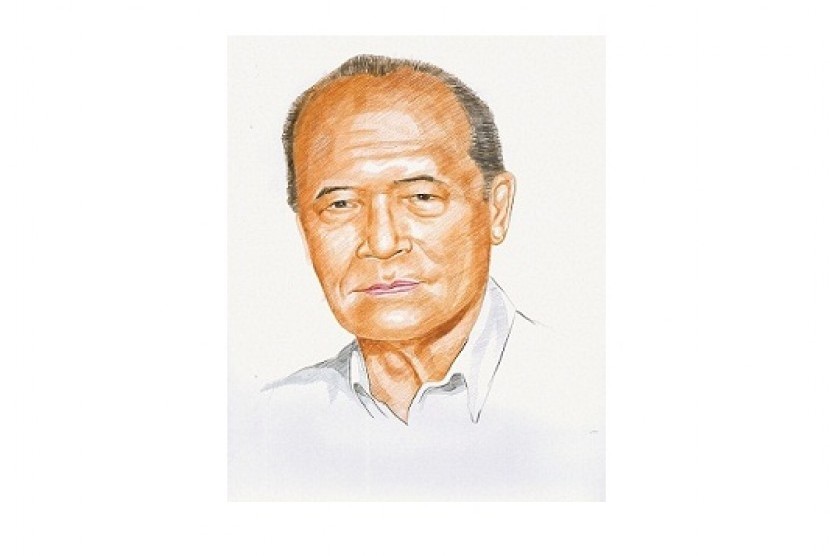REPUBLIKA.CO.ID, Saya tidak tahu apakah penggunaan ungkapan buih sebagai simbol kebatilan dan air sebagai lambang kebenaran cukup tepat untuk membaca situasi terkini di Indonesia yang telah membelah publik menjadi dua. Mana yang mewakili buih dan mana pula yang mewakili air, saya tidak bisa memastikannya karena masing-masing pihak merasa sama-sama berada di jalan kebenaran. Baik yang mengatakan bahwa seseorang telah menghina Alquran atau pun pihak yang mengatakan bahwa penghinaan tidak terbukti. Pihak pertama telah menggelar dua gelombang demo yang kabarnya akan diikuti oleh gelombang ketiga. Pihak kedua lebih banyak berkomunikasi secara intensif melalui berbagai media untuk saling menguatkan pendirian yang telah dipilih.
Untuk memberikan landasan teologis terhadap masalah krusial ini, saya mencoba berkonsultasi dengan Alquran ayat 17 surat al- Ra’d/guruh/petir (13) yang maknanya: “Dia telah menurunkan air dari langit, maka lembah-lembah menjadi banjir menurut ukurannya. Lalu air banjir itu mengandung buih yang mengapung. Dan dari apa [logam] yang mereka bakar dalam api untuk membuat perhiasan atau perkakas, ada pula buih semisal itu. Demikianlah Allah meragakan kebenaran dan kebatilan. Maka adapun buih itu akan sirna dengan sia-sia; dan adapun apa yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia akan tetap di bumi; demikianlah Allah menerangkan beberapa perumpamaan.”
Dalam kutipan makna ayat di atas, kepada manusia dijelaskan tentang buih yang tidak punya hakekat, dan dipertentangkan dengan air yang melambangkan hakekat kebenaran. Buih itu terlihat di saat banjir atau ketika pandai besi sedang membuat perhiasan atau perkakas yang dibakar di atas api. Air sebagai lambang kebenaran untuk sementara bisa saja tertutup oleh buih, tetapi hanya sementara untuk kemudian buih menghilang tanpa bekas. Begitu halnya logam murni ketika dipanaskan bisa saja ditutupi oleh buih, tetapi juga hanya buat sementara, dan buih pasti menghilang karena tidak ada manfaatnya.
Sekali lagi, saya tidak bisa mengatakan mana pendapat yang mewakili buih dan mana pula pendapat yang mewakili air. Kebenaran mutlak hanyak milik Allah, milik manusia siapa pun mereka adalah kebenaran relatif. Di ranah yang serba relatif inilah kita beradu argumen sejujur mungkin, setulus mungkin, dengan menggunakan otak yang sehat dan hati yang bening. Kita harus bersama-sama berusaha sebagai pencari kebenaran dengan membuang jauh-jauh rasa benci, rasa sayang, dan rasa marah terhadap seseorang yang dapat mendorong kita kepada sikap yang tidak adil.
Lalu ujungnya di mana? Berdasarkan pemahaman saya terhadap ayat di atas, kita harus sabar menunggu sampai banjir itu usai, sehingga air terlihat jelas karena buih yang menutupi telah sirna. Dalam suasana banjir perdebatan dan silang pendapat yang saling mengklaim kebenaran dengan tensi yang tinggi, akan sulit kita berfikir tenang, jernih, dengan dada yang lapang. Selama musim banjir ini, teriakan bernada hujatan, cacian, tudukan, dan hinaan kita hentikan sekali dan untuk selama-lamanya, karena cara-cara semacam itu tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh makhluk beradab. Siapa tahu, di ujung lorong sana akan terlihat titik cahaya kebenaran, entah milik siapa, kita belum bisa memastikan. Biarlah waktu yang akan memberi tahu.
Bagi seorang beriman, Alquran pasti benar secara mutlak, tetapi tafsiran manusia terhadap ayat-ayat Kitab Suci ini tidak pernah mencapai posisi serba mutlak itu. Dengan demikian, pihak-pihak yang mencoba memonopoli kebenaran, sama artinya dengan mengambilalih peran Tuhan sebagai sumber kebenaran tertinggi dan sejati. Dan sikap semacam ini sungguh berbahaya dan menyesatkan, seperti yang terlihat dalam teologi ISIS dan Boko Haram yang menghukum siapa pun yang berbeda dengan pandangan mereka darahnya menjadi halal.
Teologi semacam ini muncul ke permukaan pada saat orang merasa berada dalam posisi tak berdaya. Karena tidak berdaya, akhirnya menjadi kalap dalam suasana mental yang sangat labil dan memilukan. Sebagian dunia Muslim sedang berkubang dalam suasana mentalitas kalah ini. Buih disangka air. Amat memprihatinkan, memang. Jalan ke luar yang benar hanyalah tunggal: mengucapkan selamat tinggal kepada suasana mentalitas yang serba tak berdaya ini dengan cara bersedia mengoreksi kesalahan fundamental kita selama ini dengan menjadikan Alquran sebagai al-Furqân (kriterium pembeda antara yang benar dan yang salah). Jalan lain, pasti akan menggiring kepada kebuntuan peradaban.
Bagi saya, inti ajaran Islam qur’ani dan Islam kenabian tersimpul dalam ungkapan singkat dan padu ini: “Dan tidaklah Kami mengutus engkau [Muhammad] kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta.” (Lih. Alquran surat al-Anbiyâ’ ayat 107). Maka, praktik “Islam” yang berada di luar payung teologis yang maha benar ini haruslah ditolak dengan keras karena pasti akan menghancurkan peradaban dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Islam datang adalah membangun peradaban yang adil, asri, dan menawan.