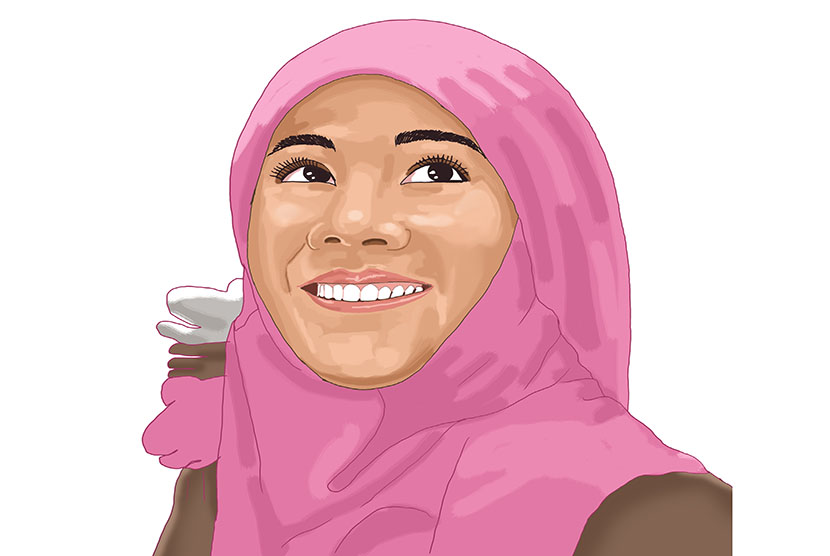REPUBLIKA.CO.ID, Dalam ilmu ekonomi, terdapat teori supply dan demand. Jika permintaan banyak, sedangkan penawaran atau persediaan sedikit, maka harga naik. Jika permintaan sedikit dan persediaan banyak, maka harga turun.
Akan tetapi, terkait ibadah haji, teori tersebut tidak sepenuhnya bisa diterapkan. Demand atau permintaan ibadah haji sangat tinggi. Setiap tahun jumlah orang yang ingin pergi haji meningkat, Namun, supply relatif tetap, bahkan kadang berkurang.
Jika teori ekonomi murni diterapkan, tentu saja biaya haji melesat naik setiap tahun dan hanya yang mampu membayar tinggi yang berangkat. Kenyataannya, patokan biaya haji tidak bisa dinaikkan sewenang-wenang karena ia berupa ibadah, bukan bisnis murni. Akibatnya terjadi antrean panjang. Calon jamaah haji harus menunggu sepuluh, bahkan dua puluh tahun lamanya.
Harus ada solusi yang lebih cerdas dari pendekatan biasa. Terlebih, ibadah haji menyangkut jutaan orang yang berkumpul dalam waktu singkat, melakukan aktivitas yang cukup berat.
Pemerintah Arab Saudi selalu berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik dari tahun ke tahun, termasuk di antaranya membangun jalur kereta cepat, menambah area tawaf, membuat terowongan, dan pembangunan lainnya.
Akan tetapi, renovasi membuat Pemerintah Saudi mengurangi jatah jamaah haji buat Indonesia, dari 200 ribuan menjadi 150 ribuan. Meski setelah renovasi selesai, jumlah tersebut kembali ke 200 ribuan.
Logika sederhananya, usai renovasi seharusnya kapasitas bukan sekadar kembali ke awal, melainkan meningkat banyak sehingga menyusul jatah yang sempat dihilangkan. Saat ini, hal tersebut belum seperti yang diharapkan. Semoga pada tahun mendatang kuota segera bertambah.
Ketimpangan lain yang muncul adalah kebijakan kuota yang tidak mengacu pada jumlah Muslim di satu negara, tapi pada jumlah penduduk. Misalnya, Australia yang mendapat kuota 30 ribu jamaah karena berpenduduk 30 juta jiwa, padahal yang berangkat haji hanya ribuan saking memang masyarakat Muslimnya sedikit.
Sebaliknya, Indonesia yang mayoritas Muslim dan angka jamaah yang ingin pergi mencapai jutaan, hanya mendapat jatah 200 ribu merujuk pada jumlah penduduk yang 200 jutaan.
Akibat kebijakan ini, akhirnya banyak jamaah yang berusaha pergi haji melalui negara lain dan dianggap ilegal. Jika pihak Arab Saudi memperhatikan kondisi ini, barangkali tenggang masa menunggu jemaah haji di Indonesia tidak perlu sampai puluhan tahun.
Tahun 2007 ketika menunaikan ibadah haji bersama suami, saya bertemu seorang bapak berusia 70 tahun yang dilarang meneruskan ibadah haji karena diketahui datang secara ilegal. Ia dari pelosok Indonesia dan masih belum banyak mengerti. Setelah puluhan tahun menabung, berhasil tiba di Arafah, tapi dilarang melanjutkan aktivitas ibadah. Buat saya sungguh dilema, karena ia datang memenuhi panggilan Allah secara susah payah, dengan penghasilan halal. Apakah di mata Allah, panitia berhak melarangnya menggenapkan ibadah haji?
Masalah lain yang kini jadi berita, persoalan dana antrean haji yang mencapai triliunan diwacanakan untuk pembuatan jalan tol. Logika sederhananya, sayang uang menganggur dan bisnis jalan tol toh jarang merugi.
Tapi, bagaimana jika ada gempa yang membuat jalan tol patah-patah dan tidak bisa dipakai selama beberapa tahun? Atau terjadi korupsi yang mengakibatkan jalan retak hingga tidak bisa dipakai lama? Siapa yang akan memikul tanggung jawab?
Apakah bijak, jika sejumlah jamaah tidak jadi berangkat karena tabungannya yang mengendap puluhan tahun tiba-tiba hilang akibat investasi yang salah?
Lain halnya jika dana tersebut menjadi pinjaman pemerintah, yang terlepas proyek jalan tol nanti merugi ataupun untung. Dana haji yang terpakai akan tetap dibayar pemerintah sebagai pinjaman yang dikembalikan. Kebijakan ini harus dipikir matang-matang karena menyangkut uang amanah yang penggunaannya jelas untuk haji. Akan berbeda pula jika ketika membayar uang pangkal haji, jamaah menandatangani persetujuan pengelolaan dana haji dan persetujuan tersebut tidak dipaksakan, dan berupa pilihan.
Sebenarnya mungkin ada solusi lain untuk mengatasi jumlah jamaah yang mengantre, yaitu dengan mengurangi pembimbing haji. Dari 200 ribu jatah haji Indonesia, ribuan di antaranya dialokasikan bagi pembimbing haji, meski di sana juga biasanya didampingi muthowif, ustaz muda yang tinggal di sana. Benar pembimbing tetap diperlukan, tapi jika kita imbangi dengan mengedukasi jamaah--apalagi misalnya terdapat calon haji yang juga ustaz dan ustazah, paham syarat dan rukun haji--dibimbing lagi secara intensif selama bertahun-tahun sebelum berangkat sambil menunggu antrean, bisa jadi akan terdapat calon jamaah yang cukup baik membantu menjadi asisten pembimbing haji hingga mengurangi jatah pembimbing yang biasa pergi haji berkali-kali.
Aturan tegas untuk tidak mengulang haji juga harus ditegakkan agar prinsip keadilan terwujud, memprioritaskan mereka yang baru pertama kali ke Tanah Suci.
Terakhir tentang media sosial. Sempat diberitakan jamaah telantar akibat stroke. Ketika diusut, ternyata tidak demikian kejadiannya. Sang jamaah hanya minta pulang ke hotel supaya nyaman beristirahat.
Kontrol penyelenggaraan haji lewat media sosial bagus, tetapi jangan sampai menambah kerepotan pihak penyelenggara dengan isu-isu yang tidak mampu dipertanggungjawabkan.
Sama-sama berharap, semoga penyelenggaraan haji semakin baik dari tahun ke tahun, dan mereka yang berangkat menjadi haji yang mabrur. Labbaik allahuma labbaik.