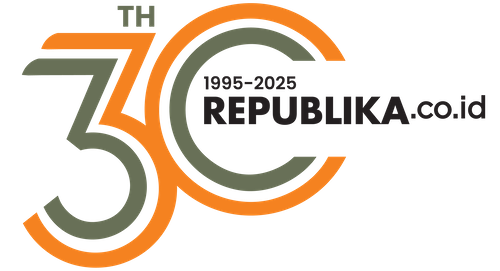Oleh: DR Margarito Kamis, Pakar Hukum Tata Negara
RUU KPK Perubahan telah disetujui bersama DPR dan Presiden menjadi UU pada tanggal 17 September yang lalu. Pada tanggal 17 Oktober ini RUU yang telah disetujui bersama menjadi UU ini genap berusia 30 hari.
Menurut pasal 20 ayat (5) UUD 1945 RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden menjadi UU, tetapi tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari, RUU itu sah berlaku menjadi UU dan wajib diundangkan.
Gerak melingkar politik mengakibatkan tidak tersedia kabar terkonfirmasi tentang penyebab lambannya RUU itu dikirimkan ke Presiden untuk disahkan. Ketika diserahkan ke Presiden, terdapat satu kesalahan ketik “kecil” sekali. Kabarnya kesalahan itu berkisar pada kekeliruan menuliskan huruf atas angka 50.
Seharusnya angka 50 ini ditulis dengan huruf “lima puluh.” Dalam kenyataanya malah ditulis, kalau tidak salah “empat puluh.” Apa ini, 50 ko ditulis 40. Menyebut dan membaca frasa lima puluh kan tidak memiliki kemiripan lafal empat puluh. Konsekuensinya Presiden harus mengembalikan RUU itu ke DPR untuk diperbaiki.
Kenyataannya? Roda politik membawa DPR hingga waktu dua hari menjelang batas waktu maksimum 30 hari barulah DPR mengirimkan kembali RUU itu ke presiden. Putaran politik sampai dengan pengiriman kembali RUU itu, menunjukan Presiden, terlihat tak mendesak, setidaknya meminta dalam gaya politisi agar DPR secepatnya mengirimkan kembali.
Tak Terluka
Apakah kenyataan itu menandai DPR dan Presiden berada dalam satu gelombang politik? Sulit menyodorkan pernyataan kongklusif. Yang bisa dikatakan adalah bila DPR segera menyerahkan RUU kepada Presiden, dan Presiden segera menandatangani dan mengundangkannya, maka datanglah satu peluang. Peluang itu boleh jadi, saya menduga, tak disukai keduanya.
Peluang itu, saya duga, mengerasnya penilaian mahasiswa bahwa Presiden dan DPR sama-sama tidak responsif. Presiden dan DPR satu gelombang dalam urusan ini. Sama-sama hendak memastikan RUU itu diperlukan dan harus diberlakukan. Bila penilaian ini mengeras, memompa hasrat sebagai intelektual muda yang bergelora menuntaskan reformasi, terlepas apapun defenisi mereka tentang itu, maka kebutuhan terhadap ekspresi eksistensial mereka bisa memanjang.
Bila memanjang menyentuh hari-hari persiapan pelantikan dan pelantikan presiden, maka pekerjaan pemerintah bertambah. Selain harus mengelola mahasiswa agar ekspresi rasa mereka dalam bentuk unjuk rasa berlangsung meriah, juga harus memastikan suasana hari pengambilan sumpah presiden untuk periode kedua, sama meriahnya.
Satu gelombang dalam membaca konstitusi, boleh jadi, itulah sekali lagi terlihat dilintasi bersama DPR dan Presiden dalam kasus ini. Bagaimana nalarnya? DPR tahu bahwa begitu sampai 30 hari, RUU ini sah menjadi UU, dan harus diundangkan. Presiden pun tahu juga. Karena sama-sama tahu, mengerti dan memahami konsekuensi-konsekuensi konstitusional, maka biarkan saja konstitusi bekerja membawa RUU itu menjadi UU tanpa harus ditandangani dan diundangkan Presiden sebelum tenggat waktu 30 hari itu. Toh sah secara hukum.
DPR di satu sayap terlihat tak disudutkan, apalagi tertampar. Presiden pun sama, disayap yang lain juga tak terdesak, untuk tak mengatakan disudutkan oleh DPR. Praktis keduanya aman dalam putaran roda politik. Mereka tidak memanggil, apalagi berkreasi menggunakan kewenangan-kewenangan konstitusional yang tersedia, yang bisa memanaskan bola non hukum. Bola politik.
Presiden dan DPR sama; tidak main kasar, dengan cara menggerakan senjata konstitusi yang tersedia. Mereka tidak normatif dalam game konstitusi ini. Mundur dan maju bersama sampai bertemu pada titik toleransi konstitusi yang tersedia bagi kedua pihak. Bermain dengan waktu hingga batas yang ditentukan konstitusi, tanpa ada yang merasa terluka.
Bisa Fatal
Siapa yang dapat memastikan bahwa pada tangal 17 Oktober ini, atau sehari setelahnya RUU yang telah disahkan menjadi UU itu benar-benar diundangkan? Apakah Presiden memiliki keberanian untuk menjatuhkan pilihan tak mengundangkan RUU yang telah disetujui menjadi UU itu? Menurut saya ini bukan pilihan konstitusional. Konstitusi tidak menyediakan pilihan itu. Itu pilihan politik yang merepotkan.
Sudahlah mari melupakan soal itu. Mari mengenal gelombang baru yang dibawa UU KPK Perubahan, entah nomor berapa ini. Komisioner KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik dan penuntut umum. Apa yang mematikan dengan ketentuan hukum ini? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Komisioner KPK tetap saja berstatus sebagai pimpinan KPK. Semua kewenangan mereka sebagai pimpinan KPK tidak dihapuskan.
Sejauh yang diketahui, Komisioner tak pernah memeriksa saksi dan tersangka. Mereka, sekali lagi, sejauh yang diketahui tidak ikut melakukan penyitaan dan penggeledahan. Tidak juga bersidang di sidang pengadilan sebagai penuntut umum. Praktis mereka tidak pernah menggunakan statusnya sebagai penyidik dan penuntut umum.
Sampai dengan titik itu, praktis gelombang baru yang dibawa ketentuan yang menghapuskan status Komisioner KPK sebagai penyidik dan penuntut umum, tidak mematikan. Sama sekali tidak. Komisioner KPK, sebagai konsekuensinya tetap memegang tanggung jawab dan kendali atas pelaksanaan semua wewenang pencegahan dan penindakan korupsi di KPK.
Berbeda dengan gelombang itu, gelombang kedua cukup fatal. Mematikan. Gelombang kedua ini menggambarkan dengan jelas betapa buruknya imajinasi dan kreasi, bahkan ketidaktahuan Presiden dan DPR terhadap modus utama korupsi di negeri ini. Sejauh yang terberitakan, semoga tidak benar, “penggunaan kewenangan penyadapan” dibatasi, bukan dihapus.
Cara membatasinya adalah penyadapan harus terlebih dahulu memperoleh otorisasi, izin dewan pengawas. Penyidik tak bisa menyadap bila tak mendapat izin dewan pengawas. Kapan izin itu diperlukan? Ini soalnya. Apakah pada saat penyelidikan atau penyidikan? Bila dilakukan setelah perkara berada pada penyidikan, berapa lama bisa dilakukan?
Bila UU ini memungkinkan penyadapan dilakukan hanya pada tingkat penyidikan, ditambah lagi dengan menyatakan telah ada tersangka, apakah KPK tidak lumpuh? Tiidak. Sama sekali tidak. Tetapi KPK tidak dapat memulai sebuah kasus dengan penyadapan. Itu jelas. Konsekuensinya KPK harus berjibaku, memeriksa tumpukan fakta yang tersebar dan berceceran di dalam ratusan lembar kertas dan keterangan saksi serta ahli.
KPK dalam konteks itu, praktis tidak bisa menemukan kasus korupsi seperti yang diduga dilakukan Bupati Lampung Utara, Walikota Medan, dan kepala-kepala daerah lainnya yang telah ditangkap berkat penyadapan. Kelak penyadapan hanya dilakukan dalam kerangka pengembangan atau membuat terang sebuah kasus, bukan mengawalinya.
Pembatasan penyadapan model UU KPK baru ini, mungkin berlebihan, sama dengan memanggil, bahkan mengucapkan selamat “menggelorakan suap-menyuap.” Inilah duri kecil itu. Bisa fatal.
Dititik inilah, suka atau tidak, terlihat kedangkalan imajinasi, skenario pertempuran melawan korupsi. Bahkan lebih jauh cara ini menandakan ketidaktahuan pemerintah dan DPR tentang modus utama korupsi, sejauh ini. Padahal modus itulah yang harus dipukul telak, diperangi.
Bila penyadapan itu telah terlihat Presiden dan DPR sebagai singa betina lapar yang selalu siaga menerkam, memandang bahwa tindakan itu tidak efektif, maka tersedia banyak pilihan untuk mengefektifkannya. Ubah saja skema atau jenis sanksinya, bukan malah membatasi atau tidak memungkinkan penyadapan pada level penyelidikan.
Pembatasan ini bisa, sekali lagi, fatal. Tetapi mau apa? Disepanjang jalan fatal itu, harus diakui juga bahwa ketentuan ini sah sebagai sebuah kebijakan hukum dalam perspektif konstitusi.