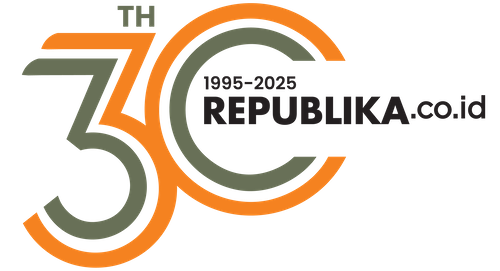REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Nasihin Masha
Namanya Hanibal Wijayanta. Sebagai wartawan, ia dibesarkan dalam tradisi investigasi dan bobot kritisisme yang kuat. Khas Karni Ilyas, guru jurnalistiknya di majalah Forum Keadilan. Kini ia menjadi wartawan televisi. Namun kebiasaannya menulis tak bisa ia hentikan. Ia sadar kekuatan tulisan tak bisa digantikan sepenuhnya oleh kekuatan gambar. Karena itu ia tetap rajin menulis di media sosial.
Melalui SMS, pekan lalu ia meminta saya untuk membaca tulisannya tentang terorisme. Ia mencatat ada data yang berbeda antara yang dikemukakan satu petinggi Polri dengan petinggi lain. Ia juga mencatat pengakuan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyad Mbay bahwa salah satu korban meninggal di lokasi kejadian adalah intelijen lembaganya yang disusupkan ke jaringan teroris. Ia menilai ada nuansa persaingan antar-petinggi Polri dalam pemberantasan terorisme, misalnya untuk karier pribadi mereka. Ia juga mencatat pernyataan khas petinggi Polri, misalnya sindiran terhadap Din Syamsudin.
Tulisan Hanibal dipicu oleh penangkapan sejumlah orang yang diduga teroris di Mustikajaya, Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat 15 Maret 2013. Namun tulisannya sama sekali tak menyinggung soal ledakan di Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa 12 Maret 2013. Namun ia merangkainya dengan ledakan bom di Beji, Depok, pada Sabtu 8 September 2012. Ia juga mengaitkan dengan dua perampokan. Perampokan toko emas di Tambora, Jakarta, pada Ahad 10 Maret 2013 dan perampokan Bank CIMB Niaga di Medan pada Rabu 18 Agustus 2010. Adapun ledakan di Cipete hanya 12 hari setelah Din dan sejumlah ulama menemui Kapolri, 28 Februari 2013. Para ulama menyerahkan rekaman video penyiksaan yang di akhiri kematian orang yang diduga pelaku terorisme yang diduga dilakukan Densus 88. Mereka meminta Kapolri untuk membubarkan detasemen tersebut dan digantikan dengan lembaga lain.
Kecuali Komnas HAM, tak banyak yang merespons dan mendukung sikap para ulama tersebut. Hal ini sudah menjadi sikap umum, sebagaimana kritik-kritik sebelumnya terhadap kinerja Densus 88. Publik seolah mengabaikannya. Bisa jadi ini karena mereka marah terhadap teroris.
Indonesia tiba-tiba menjadi lahan petualangan biadab para teroris sejak ledakan bom di depan Kedubes Malaysia pada 2000. Hingga kini, sudah lebih dari 30 ledakan bom terjadi dengan korban tewas lebih dari 300 orang. Sudah sekitar 800 orang yang ditangkap, sebagian ditembak mati dan sebagian divonis mati. Ada pula yang kemudian menjadi informan, yaitu Ali Imron (pelaku bom Bali I) dan Nasir Abbas (warga Malaysia). Di antara yang ditahan ada yang sudah bebas lagi. Walau dibatasi regulasi yang ketat, kinerja Densus 88 banyak dipuji masyarakat internasional. Data-data tadi menjadi buktinya. Namun di balik kisah sukses itu, muncul kritik-kritik keras terhadap lembaga khusus tersebut. Mereka dituduh banyak melanggar prinsip kemanusiaan, menjadi agen asing, dan dibiayai asing.
Namun Polri membantah semua tuduhan itu. Tuntutan audit khusus terhadap Densus tak kunjung dipenuhi. Walau bagaimana pun kisah detasemen ini memiliki ragam versi. Seorang wanita yang bisa disebut agen intelijen asing pernah bercerita bahwa riwayat pembentukan detasemen tersebut salah satunya datang dari dirinya. Dia pula yang ikut merangkai akses dan dukungan internasional. Sehingga detasemen ini bisa mendapat bantuan peralatan, pelatihan, dan juga informasi dari lembaga-lembaga sejenis di negara-negara lain. Bahkan ia mengaku ikut membantu memberi nama Densus 88. Semua itu ia lakukan karena ia cinta Indonesia. Indonesia tak berdaya menghadapi teror bom. Sejak ledakan di Kedubes Malaysia, Indonesia bak medan tempur. Darderdor bom di mana-mana: Atrium Senen, Kedubes Filipina, Gedung BEJ, bom natal, dan puncaknya bom Bali pada 2002.
Kita semua tersentak. Marah. Menangis. Setelah itu lahirlah Densus 88. Lembaga ini berhasil mengungkap jaringan teroris di balik semua bom itu. Mata rantai dana dari Alqaidah berhasil diputus. Namun terorisme tak kunjung habis. Mereka berhasil berevolusi dan berbiak. Pelaku yang sudah ditahan dan bebas lagi menjadi sel yang aktif lagi. Kadang kita menyaksikan keganjilan. Misalnya, jika presiden berkunjung ke suatu negara penting, selalu didahului kisah penangkapan atau penembakan teroris. Tak lama setelah Din dan para ulama menyoal Densus 88 terjadi ledakan di Cipete dan penangkapan di Bekasi. Bisa saja itu kebetulan. Kebetulan yang berkali-kali.
Kita ini terbiasa membenarkan suatu kesalahan atas kesalahan. Kita tutup buku pembantaian dan pengusiran Madura oleh Dayak, kita tutup buku pengusiran warga pendatang di Maluku. Kita juga sering tak berdaya terhadap amuk massa seperti tawuran kampung, kisruh pilkada, dan seterusnya. Tak ada yang ditangkap, tak ada yang dihukum. Seolah semua itu benar belaka. Satu kesalahan dipertukarkan dengan kesalahan yang lain. Kita biarkan cara kerja Densus 88 yang diduga melanggar kemanusiaan dan hukum karena kita marah pada terorisme.
Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Berkali-kali negeri ini menghukum prajuritnya yang melanggar hukum di Guantanamo, Afghanistan, ataupun di Irak. Mereka tak membenarkan kesalahan atas kesalahan. Mereka bisa memisahkan antara yang hak dan yang batil. Ada kejujuran dan kerendahhatian. Mereka tetap bisa menanamkan moralitas di tengah kemarahan. Membangun negeri tak cukup hanya bermodal pelor dan kuasa.