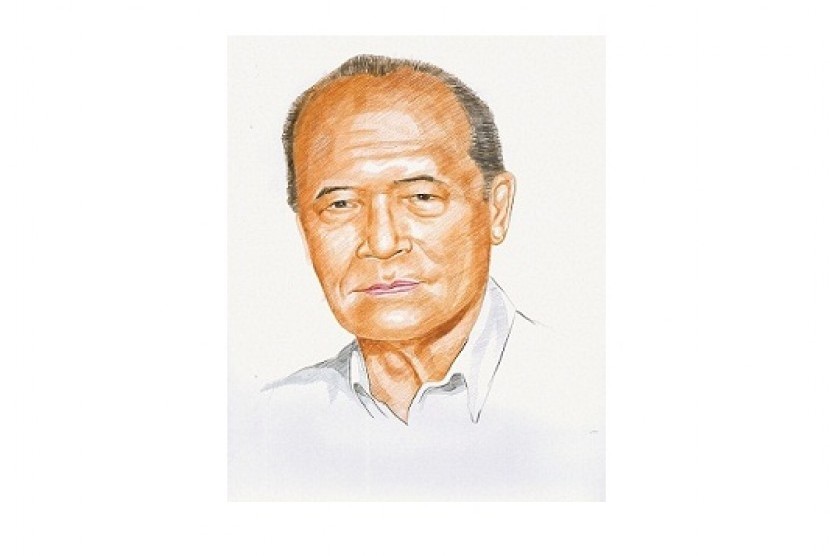REPUBLIKA.CO.ID,Oleh: Ahmad Syafii Maarif
Sekiranya tidak meledak perang mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia atau juga yang dikenal sebagai revolusi kemerdekaan, tahun 1945-1949, pemilu pertama akan diadakan bulan Jan. 1946. Demikian tingginya semangat rakyat Indonesia untuk memberi makna kepada sistem demokrasi melalui pemilu agar pemerintah yang dibentuk benar-benar memiliki legitimasi konstitusional yang kuat. Tetapi Belanda sebagai mantan penjajah belum rela melihat Indonesia masuk ke peta dunia sebagai sebuah negara merdeka. Bahkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sama sekali tidak diakuinya, padahal Balanda bulan Maret 1942 telah diusir Jepang dengan penuh kehinaan. Telah dihina, belum juga kapok untuk meneruskan petualangan imperialisme dan kolonialismenya. Inilah watak kaum imperialis yang tidak tahu diri, tidak punya kepekaan tentang konstelasi politik dunia telah berubah secara dramatis sebagai akibat PD (Perang Dunia) II.
Indonesia bergerak cepat dalam mengkonsolidasi kemerdekaannya pascarevolusi untuk menyiapkan pemilu. Maka dengan UU Pemilu No. 7 Tahun 1953 di bawah kabinet Ali Sastroamidjojo I, pemilu pertama sedang dalam proses persiapan. KPU (Komisi Pemilihan Umum) segera dibentuk, diketuai oleh Hadikusumo dari PNI (Partai Nasional Indonesia). Tetapi karena terjadi krisis kabinet, maka Pemilu diselenggarakan oleh kabinet Burhanuddin Harahap dari partai Masyumi pada 29 September untuk DPR dan 15 Desember 1955 untuk Majelis Konstituante (semacam MPR). Inilah pemilu yang fenomenal dalam makna luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia), demokratis, aman, damai, dan tanpa politik uang, di tengah-tengah pertentangan ideologi politik yang sangat tajam.
Pada tahun 1955 usia kemerdekaan Indonesia baru 10 tahun, sangat muda, tetapi telah mencapai tingkat kedewasaan politik yang luar biasa. Pertentangan antar partai memang keras, tetapi tidak ada kerusakan fisik, tidak ada darah yang tertumpah, padahal gaungan perbelahan partai itu telah menyusup sampai ke pelosok Nusantara yang paling tersuruk. Siapa yang tidak terharu dan tidak bangga dengan pesta demokrasi pertama ini? Sampai hari ini Pemilu 1955 ini masih menjadi buah mulut, sering dijadikan acuan sebagai pemilu yang ideal yang pernah dikenal dalam sejarah Indonesia modern.
Secara teknis Pemilu 1955 ini pasti ada kekurangannya. Jumlah pemilih sebesar 43,104, 464, tetapi yang sah hanya 37,785,299. Partisipasi mencapai 91.41%. Gejala golput belum dikenal saat itu, baru muncul 1971, tahun pemilu pertama di era Orde Baru, sebuah pemilu yang pemenangnya sudah direkayasa sebelum bertarung. Ada 28 partai yang ikut Pemilu 1955 dan satu perorangan, sehingga berjumlah 29 peserta.
Pemilu 1955 menghasilkan empat partai besar dalam DPR dengan jumlah kursi masing-masing: PNI (57), Masyumi (57), NU (45), dan PKI (39). Kursi yang diperebutkan ada 260. Kursi dalam Majelis Konstituante yang diperbutkan menjadi dua kali lipat=520, tetapi raihan masing-masing partai besar dalam majelis tidak selalu bersifat matematis. Partai yang ketika itu dianggap paling intelektual di Indonesia adalah PSI (Partai Sosialis Indonesia) pimpinan Sutan Sjahrir, tetapi partai inilah yang menderita kalah telak dengan hanya meraih lima kursi di DPR, sekalipun masih ada partai-partai gurem dengan satu kursi.
Amat disayangkan Pemilu 1955 yang demikian dipuji itu tidak diikuti oleh perkembangan politik nasional yang sehat dan rasional. Perpecahan antara Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta diikuti pula oleh pertentangan partai-partai, pergolakan daerah yang berdarah-darah, merapatnya PKI kepada Presiden Soekarno, adalah di antara masalah besar bangsa yang rumit dan berakibat jauh. Sekiranya Soekarno dan Hatta mampu meredam pertentangan pendapatnya dan tetap bersatu 10 tahun kemudian, maka fondasi kultur politik Indonesia akan jauh lebih kuat, stabil, dan negara ini tidak akan sempoyongan kemudian.
Kultur politik kita yang belum juga stabil sampai sekarang, akarnya bisa ditelusuri pada kejadian tahun 1950-an itu. Ibarat mobil, Soekarno adalah gas, Hatta rem. Mundurnya Hatta sebagai wakil presiden akhir tahun 1956, secara bertahap mobil Soekarno semakin melaju tanpa rem. Bangsa dan negara dengan semangat tinggi kemerdekaan tidak dikelola dengan baik dan seksama. Itulah pelajaran moral yang mesti dipetik agar
tidak diulang lagi. Perpecahan pemimpin puncak pasti mengalir sampai ke
desa yang paling jauh.