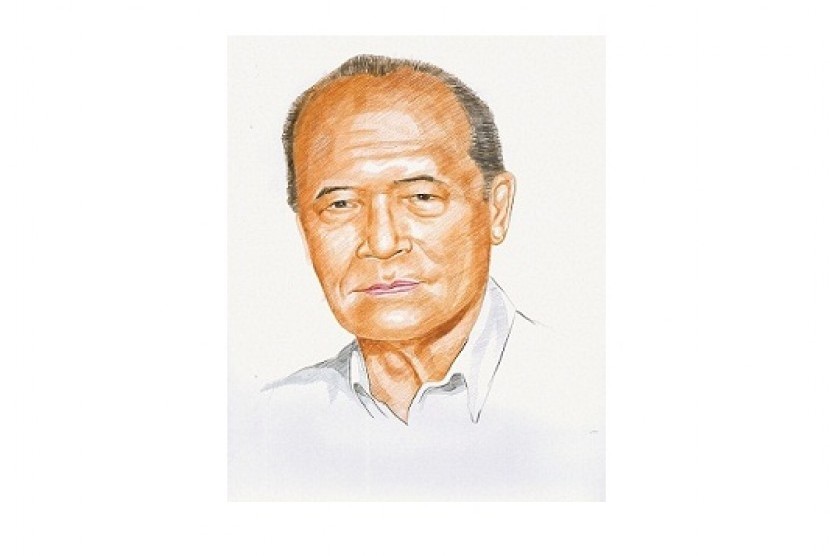REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif
Kabinet JKW-JK baru saja diresyafel sebelum berusia satu tahun. Ada pergantian menteri, ada pula yang digeser posisinya. Tidak tertutup kemungkinan akan ada lagi resyafel jilid dua, karena perimbangan di DPR telah berubah dengan beralihnya dukungan sebuah parpol menjadi partner pemerintah yang sebelumnya berseberangan. Perpindahan parpol mendapat sedikit kritik, tetapi tidak menimbulkan heboh. Catatan saya tentang perubahan sikap politik ini adalah agar orang janganlah terbiasa bersikap serba ekstrem dalam mendukung atau menentang. Dalam politik sikap-sikap seperti itu tidak mendidik, sebab jika kemudian melunak akan ditafsirkan secara liar dan negatif oleh sementara orang.
Di tengah melemahnya posisi rupiah dan kesulitan hidup rakyat yang semakin menghimpit, semestinya kabinet ini terhindar dari segala macam kegaduhan. Jika berlaku perbedaan pendapat di antara anggota kabinet, bicarakan masalah itu dalam rapat tertutup, jangan cari forum di luar untuk mendapatkan dukungan. Patuhilah etika bernegara, agar publik tidak jadi bingung dan bahkan marah, mengapa telah terjadi semacam persaingan dalam pemerintahan. Mengenai kemungkinan adanya perasaan kecewa dengan seseorang di masa lampau jangan dibawa lagi dalam kabinet yang sekarang. Indonesia yang sedang oleng ini sungguh memerlukan sebuah pemerintahan yang kompak dan saling melengkapi. Titik!
Sekiranya ada kritik yang harus disampaikan kepada seseorang dalam kabinet dan dinilai perlu diketahui publik, pakailah tangan lain di luar pemerintahan. Dengan cara ini, kesan positif publik terhadap pemerintahan tetap terpelihara, sekalipun kabinet JKW-JK ini belum melakukan sesuatu yang fundamental untuk perbaikan sistem politik dan sistem ekonomi bangsa yang terkesan masih sangat liberal. Trisakti Bung Karno yang sering diucapkan itu barulah melayang pada tingkat wacana, praktik riil di lapangan belum banyak berubah sejak rezim Orba yang lalu. Gerakan Reformasi yang bertekad merubuhkan benteng KKN (Korupsi-Kolusi-Nepotisme) selama 17 tahun berjalan, benteng itu bahkan tetap saja bertahan dan dinikmati oleh elite politik kita.
Apa maknanya semuanya ini? Jawabannya sederhana saja: kita tidak sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan mendasar dalam cara kita mengurus negara. Dulu semua kita sepakat bahwa musuh revolusi Indonesia ada dua: penjajahan dan feodalisme. Keduanya wajib ditumbangkan oleh sebuah bangsa merdeka. Penjajahan asing secara resmi memang telah diusir, tetapi sikap-sikap penjajah oleh bangsa sendiri masih saja berlangsung sampai hari ini. Rakyat banyak masih saja diberlakukan sebagai komoditas dalam pemilu, sedangkan keadilan yang mereka tuntut sejak zaman nenek moyangnya dulu masih saja diabaikan. Jika prilaku elite semacam ini tetap saja bertahan, maka demokrasi Indonesia tidak akan pernah mencapai tujuan utamanya berupa tegaknya keadilan buat semua.
Adapun feodalisme yang sudah berusia puluhan abad dalam kultur bangsa ini, ada yang tebal ada pula yang tipis, memang tidak mudah menghalaunya. Revolusi Indonesia yang hanya berlangsung sekitar empat tahun jangankan berhasil melumpuhkan feodalisme yang sudah mengakar itu, sebagian elite bangsa malah merasa nyaman hidup dengan feodalisme itu. Itulah sebabnya mengapa untuk menegakkan sistem demokrasi yang sehat dan kuat di negeri ini menjadi sangat-sangat sukar karena mereka yang menyebut dirinya demokrat, kelakuan hariannya tidak ada bedanya dengan kelakuan kaum feodal dengan tingkah serba bos. Slogan asal bapak senang memang nyata dan disenangi. Apalagi sebagian rakyat kita memang terbiasa menjadi pelayan, tidak faham apa makna kemerdekaan dan prinsip egalitarian bagi manusia.
Tetapi sikap merdeka dan egalitarian dalam politik haruslah dipagar dengan etika berkualitas tinggi, demi kekompakan dalam suasana saling memahami. Maka kagaduhan yang terasa dalam Kabinet JKW-JK tidak lain karena prinsip kemerdekaan dan egalitarianisme itu menjadi agak liar, lepas kendali, karena tidak dipagar dengan etika kolektif dalam mengurus sebuah pemerintahan.