
KAKI BUKIT – Tahun 2008, Ubaidillah Nugraha seorang bankir, penulis buku pasar modal dan kolumnis sepak bola pernah menulis buku berjudul “Republik Gila Bola.” Menurutnya, Republik Indonesia adalah Republik Gila Bola. Republik yang disebut zamrud khatulistiwa ini layak dikatakan surga sepak bola dengan beberapa alasan.
Pertama, siapa saja akan menemukan kesempatan untuk menikmati berbagai tayangan sepakbola di televisi yang tidak akan ditemukan di banyak negara lainnya. Bayangkan 103 jam perminggunya kita bisa menghabiskan waktu di depan televisi menonton pertandingan sepak bola. Semuanya gratis.
Kedua, ketika mendatangi berbagai kesempatan pertandingan sepak bola liga lokal maupun ketika tim nasional bermain. Antusiasme masyarakat Indonesia untuk hadir ke stadion, menonton ataupun sekedar bertemu suporter, benar-bernar membuat bulu roma berdiri. Kapasitas stadion yang hanya 30.000 misalnya, bisa dihadiri lebih dari 50.000 orang.
Apa yang terjadi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober 2022 sepertinya serupa dengan yang ditulis Ubaidillah Nugraha dalam bukunya setebal lebih dari 214 halaman?
Pada pertandingan kompetisi Liga 1 Indonesia 2022 yang mempertemukan tuan rumah Arema FC melawan tim tamu Persebaya, dengan kemenangan untuk tim berjuluk “Bajul Ijo.” Penonton dan pendukung Arema yang disebut Aremania kecewa dengan hasil tersebut, lalu terjadi tragedi yang mengakibatkan lebih dari 100 orang meninggal dunia.
Menurut Kepala Polda Jawa Timur (Kapolda Jatim) Irjen Nico Afinta, insiden ini bermula dari kekecewaan sekelompok suporter Arema. Usai wasit meniup peluit panjang suporter dari tribun mengungkapkan kekecewaan kepada pemain dan pelatih kemudian ada penonton yang masuk ke lapangan dan diikuti penonton lainnya. “Ada sekitar tiga ribu suporter yang masuk ke lapangan,” kata Kapolda Nico Afinta.
Polisi berusaha melakukan upaya preventif untuk mencegah aksi suporter semakin meluas. Namun yang terjadi situasi tak bisa lagi dikendalikan aparat keamanan yang berjaga lalu melepaskan tembakan gas air mata ke tribun.

Akibat insiden tersebut menurut Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta pada Ahad (2/10) ada 127 orang korban meninggal, 125 orang suporter dan dua orang anggota Polri. Korban berjatuhan selain orang dewasa ada anak-anak, mereka panik setelah terkena tembakan gas air mata dan berusaha berlari keluar stadion dengan saling berdesak-desakan sehingga menimbulkan korban jiwa.
Kemudian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Efendi yang meninjau langsung stadion Kanjuruhan dan para korban menyatakan bahwa korban meninggal dunia akibat tragedi tersebut sebanyak 130 orang.
Sementara itu menurut Menkopolhukam Mahfud MD, sejak sebelum pertandingan, pihak aparat sudah mengantisipasi terjadinya kericuhan melalui berbagai cara. Misalnya mengusulkan kepada panitia, pertandingan dilaksanakan sore, bukan malam hari, jumlah penonton agar disesuaikan dengan kapasitas stadion, yakni 38.000 orang.
“Tapi usul-usul itu tidak dilakukan oleh panitia yang tampak sangat bersemangat. Pertandingan tetap dilangsungkan malam, dan tiket yang dicetak jumlahnya 42.000,” kata Mahfud dalam keterangan pers di Jakarta.
Keterangan Menko Mahfud menjadi pembenar dari alasan kedua yang ditulis Ubaidillah Nugraha dalam buku “Republik Gila Bola.”
Tragedi Heysel
Lalu media massa khususnya media online serentak membuat pemeringkatan daftar sejarah tragedi dalam sepak bola yang terjadi di seluruh dunia, dari korban yang tewas terbanyak sampai yang sedikit. Peringkat pertama adalah tragedi yang terjadi di stadion Estadio Nacional, Lima, Peru pada 24 Mei 1964 dengan jumlah korban meninggal dunia 328 orang pada pertandingan antara tuan rumah Peru melawan Brazil.
Dan peringkat kedua adalah stadion Kanjuruhan, Malang dengan korban 130 orang meninggal dunia. Lalu disusul tragedi di Ghana yang menewaskan 126 orang. Dari berbagai tragedi sepak bola yang mengakibatkan para pendukungnya tewas, yang menyita perhatian dunia adalah tragedi yang terjadi di Benua Eropa mengingat penyelenggara kompetisi negara benua biru tersebut lebih maju dan moderen dibandingkan kompetisi dari belahan dunia lainnya.
Di negara dengan kompetisi sepak bola yang maju masih terjadi tragedi yang menewaskan penontonnya. Tragedi yang kerap disebut dan diingat adalah “Tragedi Heysel” yang terjadi 29 Mei 1985. Tragedi terjadi pada pertandingan final Piala Champions (sekarang Liga Champions) di Stadion Heysel, Bruseel, Belgia yang mempertemukan dua klub sepak bola raksasa, Liverpool dari Inggris dan Juventus dari Italia. Dua klub tersebut dihuni pemain top dunia pada masanya, diantaranya Michel Platini kapten tim nasional Prancis di Juventus dan Kenny Dalglish di Liverpool.
Sebelum laga final berlangsung Direktur Liverpool Peter Robinson dan Presiden Juventus Giampiero Boniperti sudah menyampaikan keluhan tentang kondisi stadion Heysel yang waktu itu sudah berusia 55 tahun kepada Asosiasi Sepakbola Eropa (UEFA) dan mendesak tempat pertandingan dipindahkan ke stadion lain. Namun UEFA tidak menanggapi keluhan itu.
Pertandingan final Piala Champions 1985 tetap berlangsung di stadion Heysel. Menjelang pertandingan, suporter dari dua negara asal klub tersebut mulai berdatangan termasuk penonton dari warga negara Belgia. Yang terjadi ratusan suporter tanpa tiket menerobos memaksa masuk stadion dengan cara menjebol tembok stadion yang menggunakan cinder block atau sejenis batako ringan yang terbuat dari beton campuran batu bara dengan abu. Tembok yang ringkih itu pun jebol.
Di dalam stadion, tempat penonton pendukung Liverpool dan Juventus ditempat pada tribun yang berbeda. Satu jam sebelum kick off mulai terjadi insiden, suporter Liverpool yang berada di sektor Y mulai menyebrang mendatangi suporter Juventus di sektor Z. Lalu mulai terjadi saling lempar batu yang berasal dari runtuhan dinding stadion yang jebol.
Sebagian suporter Juventus berusaha menyelamatkan diri ke tempat yang dirasa aman dari lemparan batu. Mereka memadati sisi tersebut dengan jumlah ratusan orang. Akibat tekanan jumlah orang yang banyak tersebut, membuat bagian bawah tembok stadion runtuh dan menimpa penonton yang berlindung tersebut. Akibatnya 39 orang penonton meninggal, 24 orang diantaranya warga Italia dan 450 penonton lain mengalami luka-luka. Walau tragedi terjadi, pertandingan tetap berlangsung dengan kemenangan Juventus 1-0 dari tendangan pinalti Michel Platini.
Bentrok antara suporter dari dua negara tersebut tidak terlepas dari dendam suporter Liverpool yang pada tahun sebelumnya menjadi juara Piala Champions menang dari AS Roma. Selama dan sebelum dan setelah pertandingan suporter Liverpool diserang oleh suporter AS Roma. Pada final 1985 Liverpool dipertemukan kembali melawan klub dari Italia yaitu Juventus. Namun dendam itu masih membara dalam dada suporter Liverpool.
Usai tragedi tersebut, 2 Juni 1985 Perdana Menteri Inggris saat itu Margareth Thatcher mendesak UEFA agar klub-klub dari Inggris dilarang berlaga di Eropa dan larangan bertanding tersebut berlaku bagi seluruh klub Inggris dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.
Lalu FIFA empat hari berselang mengeluarkan hukuman, menambah hukuman larangan bertanding bagi tim-tim asal Inggris di seluruh dunia, kecuali laga persahabatan. Melarang semua klub sepak bola asal Inggris berkompetisi di ajang Piala Champions selama lima tahun. Liverpool dihukum secara khusus, yaitu enam tahun tidak boleh berkompetisi di Piala Champions. Juga ada 14 orang suporter Liverpool dihukum selama tiga tahun karena terlibat tragedi Heysel.
Menurut Thatcher waktu, hooliganisme di Inggris seperti penyakit menular yang harus dikarantina. Larangan bagi klub asal Inggris berkompetisi di Eropa berbuah hasil yang baik. Terjadi transformasi pada wajah sepakbola Inggris. Polisi Inggris sangat aktif dalam memantau pergerakan suporter dengan mengantisipasi sejak dini potensi kekerasan dan kerusuhan. Sistem pengamanan stadion lebih diperketat. Perdana Menteri Inggris itu meminta aparat kepolisian memiliki satuan khusus untuk menangani suporter.
Akibat dari peraturan tersebut Margareth Thatcher dianggap sebagai sosok yang anti sepak bola di Inggris. Ia tegas mengatakan, “Kita harus membersihkan olahraga ini dari aksi kekerasan di rumah kita sendiri kemudian mungkin kita bisa kembali melanglang buana seperti sedia kala.”
Dampak dari hukuman UEFA dan FIFA tersebut dan dukungan Margareth Thatcher melakukan lockdown klub-klub asal Inggris membuat perubahan terjadi pada kompetisi sepak bola di negera yang disebut asal sepak bola tersebut. Klub-klub mulai berbenah dengan memperhatikan suporternya. Berbagai atura diberlakukan kepada para suporter klub. Bahkan Menteri Olahraga Inggris Colin Moynihan menggagas kartu pengenal sebagai suporter yang mulai pada beberapa klub.
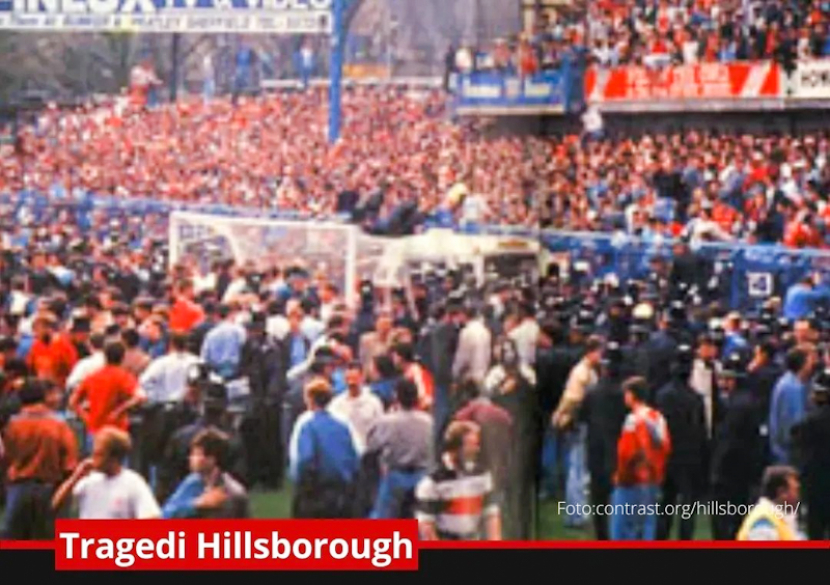
Tahun 1990 dan 1991 sanksi terhadap klub-klub Inggris dicabut. Pada 2005 suporter Liverpool dan Juventus bertemu kembali di Stadion Anfield, Inggris pada babak perempat final Liga Champions. Sebelum pertandingan dimulai, suporter Liverpool membuat koreografi terbaca “Amicizia” yang berarti pertemanan. Ini membuat suporter Juventus yang datang di Anfield tak kuasa menahan haru. Mereka memberikan tepuk tangan yang meriah.
Pada masa itu Thatcher juga menegaskan ada faktor lain yang tidak kalah besar andilnya pada Tragedi Heysel, yaitu panitia penyelenggara yang tidak kompeten dan UEFA. Andai saja saat itu UEFA mau mendengar masukan kedua belah klub untuk berpindah stadion tragedi itu mungkin tidak terjadi.
Di tengah sanksi yang diterima Inggris tersebut di dalam negeri sendiri kompetesi masih berlangsung. Empat tahun kemudian kembali terjadi tragedi, kali ini terjadi di Inggris tepatnya di stadion Hillsborough.
Pada 15 April 1989 yang menjadi kandang klub Sheffield Wednesday akan berlangsung pertandingan babak semi final Piala FA yang mempertemukan Liverpool dengan Nottingham Forest. FA atau federasi sepak bola Inggris memilih tempat pertandingan netral yaitu stadion Hillsborough. Stadion ini dari Liverpool berjarak 2 – 3 jam untuk menjangkaunya dengan kendaraan umum.
Tiket pertandingan sudah terjual habis. Ribuan suporter dari kedua klub telah bergerak menuju kota Sheffield. Panitia telah membagi tribun untuk pendukung kedua tim. Suporter Nottingham Forest ditempatkan di sisi Spions Kop, sebelah sisi utara dan timur. Kemudian suporter Liverpool ditempatkan di tribun selatan (Leppings Lane) dan barat. Leppings Lane adalah tribun tempat suporter berdiri (standing terrace) yang bertingkat dengan kapasitas 10.100 orang.
Menjelang pertandingan ternyata, jumlah suporter Liverpool yang datang melebih dari tampung tribun yang disediakan. Stadion telah penuh oleh penonton, di luar stadion masih ada ribun suporter berusaha masuk ke dalam stadion yang telah sesak penonton. Kemudian polisi membuka pintu keluar yang menghubungan tribun 3 dan 4, lalu pendukung Liverpool yang masih berada di luar stadion terus memaksa masuk ke dalam tribun yang sudah penuh sesak. Penonton yang telah lebih dulu masuk stadion tergencet dan tertekan untuk makin ke depan mendekat ke pagar penghalang ke arah lapangan.
Pada saat pertandingan baru memasuki menit ke-5 tragedi itu terjadi tiang atau pagar penghalang di area 3 jebol dan mengakibatkan aliran penonton semakin terdorong ke depan, para suporter Liverpool berjuang menyelamatkan dirinya masing- masing dari gencetan dan injakan. Mereka yang berada di posisi depan tergencet, tertindih, dan terinjak oleh pendukung lainnya. Suporter bergerak sampai ke sisi pinggir lapangan.
Pasca kejadian itu tercatat ada 96 orang meninggal dunia dan 766 orang menderita luka-luka. Korban termuda berusia 10 tahun dan tertua 67 tahun. Salah satu dari korban meninggal adalah Jon-Paul Gilhooley yang berusia 10 tahun sepupu dari Steven Gerrard.
Tragedi Port Said
Tragedi sepak bola yang menewaskan suporter dan pendukung klub tidak hanya terjadi di Eropa, Amerika dan Asia. Di benua Afrika juga terjadi tragedi mengenaskan yang terjadi di Mesir dan Kongo. Yang sangat mengenaskan dengan jumlah korban yang besar terjadi di stadion Port Said, Mesir pada saat pertandingan lanjutan kompetisi Liga Utama mesir pada 1 Februari 2012. Port Said berjarak sekitar 200 km dari ibu kota Mesir, Kairo.

Pada hari itu pertandingan mempertemukan klub tuan rumah Al-Masry menjamu tamunya Al-Ahly. Pada pertandingan tersebut tim tuan rumah menang dengan skor 3 – 1. Pertandingan pun berakhir wasit pun meniup peluitnya. Pada saat yang bersamaan ribuan supertor ultras Al-Masry menyerbu ke lapangan mereka memburu para suporter Al-Ahly, melemparnya dengan bat dan memukul dengan berbagai benda yang bisa digunakan, tiang gawang dirobohkan dan kursi tribun dibakar. Mereka melakukan barbarisme.
Dari kerusuhan tersebut 79 orang tewas sebagian besar suporter Al-Ahly. 1.000 orang lainnya menderita luka-luka. Polisi menangkap 47 orang suporter yang diduga sebagai dalang kerusuhan. 21 Orang diantara mereka yang ditangkap dijatuhi hukuman mati. Ada yang janggal dalam peristiwa ini, walau tuan rumah Al-Masry meraih kemenangan, justru pada pendukungnya yang beringas.
Dari berbagai liputan media massa internasional seperti Reuter dan The New York Times kemarahan pendukung Al-Masry dipicu oleh spanduk yang dibentangkan suporter ultras Al-Ahly yang menghina Port Said. Selain itu ada sentimen ideologi dan politik antara kedua klub tersebut.
Suporter ultras Al-Ahly dikenal sebagai suporter garis keras di Mesir, perilaku mereka sangat ekstrim dan kerap memancing keributan dengan suporter klub lain. Suporter Al-Ahly pada berbagai pertandingan selalu beringas dan kerap menyerang polisi. Al-Ahly sendiri adalah klub sepak bola tertua di Mesir berdiri tahun 1907.
Suporter ultras Al-Ahly juga disebut sebagai bagian dari “pasukan” penentang pemerintahan militer Mesir yang dituding terlibat dalam kerusuhan di Tahrir Square saat terjadi revolusi menumbang rezim Presiden Hosni Mubarak. Sebaliknya, suporter ultras Al-Masry adalah lawan politik yang menjadi pendukung Mubarak yang tumbang pada tahun 2011. Atas perseteruan dan tragedi di stadion Port Said, Perdana Menteri Mesir saat itu Kamal Al Ganzouri membubarkan EFA (Egyptian Football Association) atau asosiasi sepak bola Mesir.
Tragedi pada sepak bola di Mesir bukan hanya terjadi stadion Port Said. Di Kairo pada 9 Februari 2015 sebanyak 22 orang suporter tewas setelah bentrok dengan polisi Mesir di luar stadion. Bentrok terjadi pada pertandingan Liga Primer Mesir antara Zamalek dan ENPPI.
Bentrok yang menewaskan suporter Zamalek yang berjuluk “Kesatria Putih” setelah mereka berusaha memaksa masuk ke stadion meskipun tidak memiliki tiket sehingga terjadi kerusuhan. Polisi berusaha membubarka pada pendukung Zamalek dengan menggunakan gas air mata. Menurut para saksi mata, sebagian suporter tersebut tewas karena terinjak-injak saat polisi mengeluarkan gas air mata.
Dari berbagai kerusuhan suporter sepak bola tersebut, menurut Geetho TW dalam buku “Total Football For Life,” (2014), “Kerusuhan bisa terjadi dalam sepak bola atau pagelaran yang bersifat mengumpulkan massa. Berkumpulnya ratusan, ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu massa dalam satu stadion selalu berpotensi menciptakkan kerusuhan jika tidak ditangani secara strategis.” (maspril aries}


