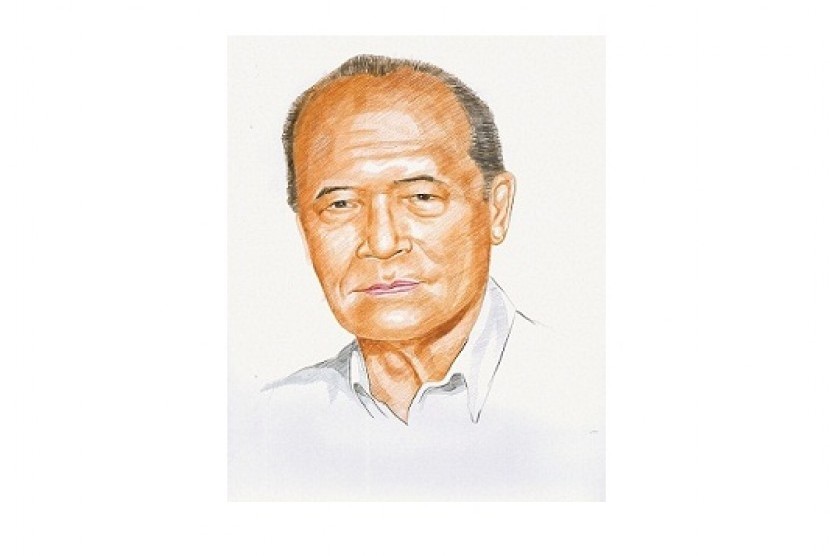REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Ahmad Syafii Maarif
Bulan depan, tanggal 17 Agustus 2013, genaplah usia kemerdekaan kita 68 tahun, sesuatu yang patut kita syukuri dengan segala plus-minusnya perjalanan bangsa dan negara ini. Di samping sisi-sisi positif dan konstruktif, kita tidak boleh menutupi sisi-sisi gelap bila kita tempatkan di bawah nilai-nilai luhur Pancasila.
Dengan diberi bobot dan nuansa baru di sana-sini, Resonansi ini didasarkan kepada makalah yang disampaikan di depan Forum Purnawirawan Perwira TNI dan undangan lainnya, bertempat di Gedung Cawang Kencana, Jakarta, pada 27 April 2006, dihadiri oleh sektar 300 peserta. Setelah berjalan tujuh tahun, keadaan bangsa dan negara belum juga ada perubahan fundamental. Pancasila tetap saja tidak dipedomani secara nyata dalam cara kita mengurus bangsa dan negara, suatu kelengahan konstitusional yang sangat menyakitkan, jika bukan telah dan sedang berlakunya pengkhianatan kolektif. Keadilan sosial masih jauh dari kenyataan sebagian besar rakyat Indonesia.
Setiap pergantian sistem kekuasaan selama kurang-lebih 68 tahun Indonesia merdeka, selalu saja ada harapan untuk kebangkitan dan perubahan mendasar agar lebih adil dan lebih baik. Tetapi, setelah sistem baru berjalan dengan 1.000 janji, kekecewaan dan rasa tidak nyaman di kalangan rakyat luas mencuat lagi dan lagi. Dengan demikian, kebangkitan sejati belum pernah terjadi selama sekian dasawarsa di era kemerdekaan.
Mula-mula kekecewaan itu dirasakan oleh kelompok kecil, kemudian radiusnya semakin meluas sehingga negara tidak mampu mengontrolnya lagi. Sistem Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dan Demokrasi Pancasila (1966-1998) telah roboh secara dramatis, pertumpahan darah sesama anak bangsa sukar sekali dihindarkan. Ajaibnya adalah, Pancasila secara formal konstitusional tetap berada pada posisi puncak, sedangkan nilai-nilai luhurnya tidak pernah dijadikan pedoman dan acuan secara sungguh-sungguh dalam cara kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Era Reformasi sejak 1998 sampai sekarang dengan slogan anti-KKN, otonomi daerah, dan demokratisasi, ternyata telah berjalan tersendat-sendat, sementara tingkat pengangguran tidak semakin berkurang, berbarengan dengan munculnya orang kaya baru yang diuntungkan. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan, Gerakan Reformasi telah mati suri.
Pertanyaannya adalah, mengapa bangsa ini tidak becus mengurus dirinya? Di mana letak kelemahan kita dalam berbangsa dan bernegara selama ini? Uraian berikut akan mencoba memberikan jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan semacam itu dan pertanyaan lain yang relevan.
Di sekitar era proklamasi 1945 dan tahun 1950-an, kita memang terganggu oleh masalah pertarungan Pancasila versus Islam sebagai dasar negara. Tetapi, dengan dikukuhkannya Pancasila sebagai dasar filosofi negara di era 1980-an dan diterima kemudian oleh kalangan masyarakat luas, sebenarnya masalah fundamental ini telah selesai. Sekarang hampir tidak ada lagi kekuatan politik yang berarti yang mampu melawan kenyataan ini. Sekalipun masih ada beberapa kelompok masyarakat yang mencoba menghidupkan kembali kesetiaan primordialnya, pasti tidak mendapat pasaran yang berarti dalam proses kenegaraan kita.
Adapun sekarang Pancasila sudah jarang disebut sejak 15 tahun terakhir, jangan diartikan bahwa filosofi ini ingin diganti dengan yang lain. Sama sekali tidak. Yang terjadi di bawah permukaan adalah kekecewaan berat masyarakat karena nilai-nilai luhur Pancasila itu lebih banyak dijadikan retorika politik, sedangkan dalam perbuatan nilai-nilai itu malah dikhianati tanpa rasa malu. Jadi, yang berlaku adalah pengkhianatan terhadap Pancasila dalam praktik.
Mari kita cermati dalam kehidupan kolektif kita bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila tidak lagi hidup dalam menuntun perilaku kita sebagai bangsa. Sila pertama adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Semestinya, sila ini dijadikan payung moral oleh semua kita. Benar, masjid, gereja, wihara, pura, klenteng, dan lain-lain tempat ibadat masih banyak pengunjungnya. Tetapi, apakah kehadiran orang di tempat-tempat ibadah itu ada pengaruhnya dalam memperbaiki perilaku kita sebagai individu atau secara kolektif? Saya sangat meragukan.
Dalam pantauan saya, sebegitu jauh proses internalisasi nilai-nilai luhur Pancasila belum terjadi secara efektif, terutama di kalangan pejabat tinggi, apalagi di kalangan politisi. Kenyataan ini sungguh sangat memprihatinkan. Tempat-tempat ibadah yang terus bertambah seperti tidak ada korelasi positif dengan perubahan perilaku ke arah kebaikan dan kejujuran. Ini suatu yang sangat serius yang sedang melingkungi kita, sebuah pertunjukan kemunafikan sosio-kultural yang masih menerpa bangsa ini secara keseluruhan.
Sila kedua adalah “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Rumusannya sangat padat dan padu, memberi arah yang jelas ke mana bangsa ini semestinya bergerak. Tetapi, kenyataan pada masa-masa tertentu dan di daerah tertentu, sejak beberapa tahun belakangan, yang berlaku adalah proses penindasan kemanusiaan dengan cara yang zalim dan biadab. Tidak jarang dilakukan dengan alasan politik, ekonomi, dan bahkan agama. Kita telah kehilangan perspektif moral dalam berhubungan sesama anak bangsa.
Sistem politik sentralistis selama puluhan tahun telah menginjak-injak sila ini dengan membunuh rasa keadilan dengan cara yang tidak beradab. Di era reformasi, keliaran politik dan ekonomi semakin tidak dapat dibendung dan dikendalikan. Akibatnya, partisipasi dalam pemilu telah merosot secara dramatis. Demokrasi dijadikan ajang pertarungan berebut rezeki dan kekuasaan, sementara sebagian besar politisi masih saja merasa benar di jalan dusta tunanurani.