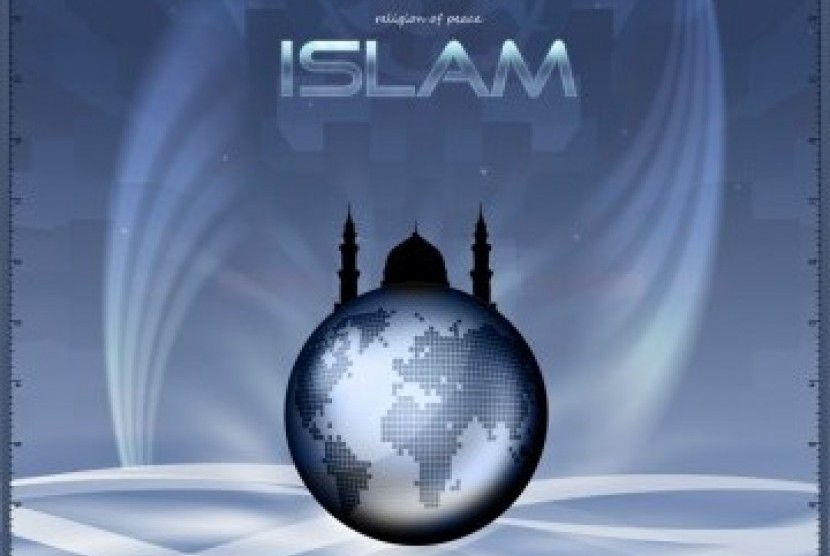REPUBLIKA.CO.ID, STOCKHOLM – Helena besar dalam lingkungan Kristen. Namun, ia tidak pernah melihat orang berdoa atau menyebut nama Allah.
"Kami merayakan Natal, Paskah dan hari besar lain. Tapi aku tak pernah tahu mengapa harus merayakannya," kata dia.
Sebagai penganut Kristen, lanjutnya, tentu harus mengetahui seluk beluk tentang agama tersebut. Tidak seperti kondisinya saat ini, di mana pengetahuan Kristen begitu minim.
Sebabnya, Helena berulang kali ambil bagian dalam kegiatan gereja untuk belajar tentang agamanya. "Begitu besar harapanku saat mengikuti kamp musim panas ala gereja. Nyatanya, aku tidak mendapat pengetahuan sedikit pun," ujarnya.
Dari pengalaman itu, Helena secara perlahan mulai berpikir untuk tidak lagi memandang penting sebuah agama. Yang terlintas di pikirannya saat itu, bagaimana melanjutkan hidup guna merajut masa depan. "
Semenjak sekolah, aku selalu mendapatkan nilai terbaik. Tidak terlintas sedikit pun dalam pikiranku untuk mendalami agama," kata dia. "Tanpa agama, aku merasa baik-baik saja."
Helena sebenarnya sadar manusia membutuhkan pegangan hidup. Sebuah pedoman untuk membentengi diri dari rasa sakit atau depresi saat menjalani kehidupan. Tapi sulit bagi dia untuk menerima agama begitu saja. "Aku mengalami perang batin, meski berulang kali aku patahkan dengan keinginan kuat untuk tidak bergantung pada Tuhan," tuturnya.
Semenjak itu, Helena memandang Tuhan tak lebih dari seorang yang tua berambut putih yang tidak bisa menciptakan dan mengatur alam semesta. "Aku semakin tidak percaya saat dicekoki teori Darwin. Teori itu seolah fakta," ujarnya.
Seiring berjalannya waktu, Helena tidak lagi sanggup untuk menutupi kekurangannya itu. Ia mulai mencoba untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Ia dengan perlahan mulai membuka kran untuk menerima Tuhan. "Aku semakin tertekan. Aku merasa hidup seperti dalam penjara," ungkapnya.