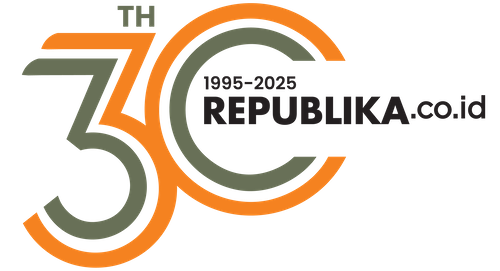REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Fitriyan Zamzami, wartawan Republika
Panggung di depan Pondok Pesantren Alquran Buaran, sudah rapi berdiri pada Senin, 24 Maret 1997. Panji-panji kuning mulai dikibarkan di salah satu titik kumpul di Kota Pekalongan, Jawa Tengah tersebut. Rencananya, panggung dan lapangan tersebut akan jadi lokasi perayaan haul Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang terbit pada 1966. Surat perintah Presiden Sukarno pada Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto yang jamak jadi penanda dimulainya rezim Orde Baru.
Sekira pukul 13.15 WIB, jauh sebelum acara dimulai dua hari mendatang, ratusan orang datang ke lokasi. Sebagian membawa batu dan bom molotov. Tenda-tenda lalu dirobohkan dan dibakar, api segera merambat ke bendera-bendera di sekitarnya. Karena tiupan angin yang kencang, api segera menjilat ruangan panggung utama yang terbuat dari kayu dan kain terpal. Kepulan asap berwarna hitam membumbung tinggi ke angkasa. Massa kemudian bergerak menghancurkan dan merusak semua fasilitas yang akan dipakai pengajian.
Aparat keamanan tak segera melansir alasan pembakaran tersebut. Acara yang intinya berupa pengajian itu tetap bakal dilaksanakan pada Rabu, 26 Maret 1997. Tak ayal, aksi massa kembali meledak keesokan harinya. Ribuan massa mengamuk dan merusak toko, kantor, dan fasilitas umum lainnya.
Kerusuhan ini terjadi setelah berlangsung acara pengajian rutin di tiga tempat yaitu Sampangan, Buaran, dan Kebulen. Mereka bergerak sejak Gang Apotek Buaran Kampung Banyuurip Ageng. Massa menutup jalan sepanjang Medono hingga Kertijayan.
Pertokoan di sepanjang jalan itu dirusak, sejumlah gardu telepon menjadi sasaran. Kantor BRI dan kontainer sampah juga rusak. Massa mengeluarkan barang-barang yang ada di toko lalu dibakar. Tercatat empat sepeda motor dibakar. Siang hari massa semakin beringas. Jalan menuju Pondok Pesantren Alquran --tempat berlangsungnya pengajian tadi-- diblokade dengan pembakaran ban-ban bekas, kayu, serta sampah.
Toko obat bahan batik di Jalan Kertijayan, menjadi sasaran amukan massa, obat-obatan bahan batik disiramkan ke jalan dan dibakar, sehingga menyebabkan kepulan asap di mana-mana. Jalan Kertijayan dan sekitarnya diblokir oleh petugas. Masyarakat banyak yang bergerombol di sepanjang mulut gang.
Sepanjang jalan Medono-Kertijayan yang semula marak dengan bendera warna kuning, berubah menjadi warna hijau. Tercatat sebanyak tujuh orang mengalami luka-luka, dua di antaranya petugas keamanan. Mereka mengalami luka akibat terkena lemparan batu dari massa.
Rabu, 26 Maret 1997, pukul 00.15 massa kembali melakukan aksi. Mereka berniat membakar dan merusak kembali panggung yang terletak di halaman pesantren. Beberapa massa yang sempat 'menyandera' wartawan Republika di lokasi mengatakan, mereka kesal karena penyanyi dangdut kesayangan mereka, Rhoma Irama serta dai sejuta umat Zaenuddin MZ (alm) bakal ikut serta dalam acara peringatan Supersemar. Peta politik Pekalongan yang memiliki banyak massa pendukung PPP, organisasi peserta pemilu (OPP) yang sebelumnya menaungi Rhoma Irama, ikut jadi pemicu.

Rhoma Irama
Mengapa orang-orang marah bahwa Rhoma Irama mengikuti acar yang jelas-jelas disponsori golongan beringin? Ada sejarah di balik itu. Sejarah yang menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru, dangdut yang dianggap sebagian orang sebagai musik kampungan adalah juga sarana perlawanan terhadap rezim.
Wartawan senior Republika Alwi Shahab pernah menuturkan sebuah kisah terkait hal itu. Ia mengenang, menjelang Pemilu 1977 pulang agak larut dari kantor. Ketika itu, Abah Alwi, sapaan akrabnya, masih bekerja di LKBN Antara dan hendak pulang menuju rumah di Depok, Jawa Barat, pada pukul 02.00 pagi.
Ketika melewati perempatan Pancoran, Jakarta Selatan, ia melihat ada sosok yang tak asing di tepi jalan. Ia bersama beberapa pemuda lainnya tengah berupaya memasang spanduk bergambar ka'bah.
Ia cermati, ternyata pria tersebut ikon musik dangdut saat itu, Rhoma Irama. Pemuda-pemuda yang menemani adalah rekan-rekannya dari Soneta, grup dagdut yang ia dirikan. Abah Alwi angkat tangan, kemudian menyapa sekilas, dan Rhoma membalas singkat.
Pemilu 1977 tentu bukan kisah tentang Rhoma semata. Tapi, kisah Rhoma saat itu bisa menggambarkan bagaimana suasana yang menyelimuti perhelatan tersebut. Pada Pemilu 1977, untuk pertama kalinya penyederhanaan partai digagas pemerintah. Partai-partai yang bertarung pada Pemilu 1971 dilebur menjadi dua kubu.
Partai Nahdlatul Ulama (NU); Partai Muslimin Indonesia (Parmusi); Partai Serikat Islam Indonesia (PSII); dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sisanya, bergabung di Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Hanya Golongan Karya (Golkar) yang saat itu menolak disebut partai, tetap berdiri sendiri.
Nah, menghadapi penyederhanaan partai tersebut, Golkar yang merupakan mesin politik Orde Baru semakin mati-matian berupaya memenangkan pemilu. Pada Pemilu 1971, Golkar sudah memenangkan pemilu, tapi pada Pemilu 1977 targetnya adalah kemenangan mutlak. Ujung-ujungnya, berbagai cara digunakan untuk mengarahkan suara masyarakat kepada Golkar. Rhoma adalah korban dari penggunaan “berbagai cara” tersebut.