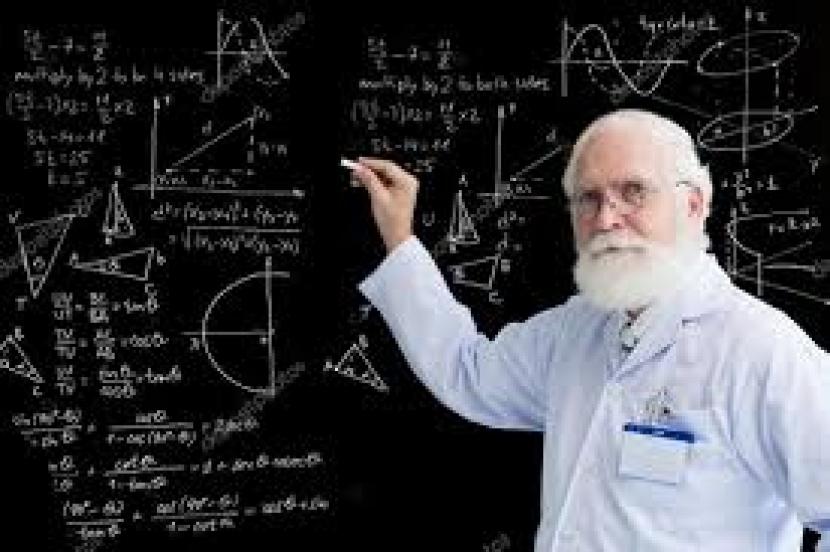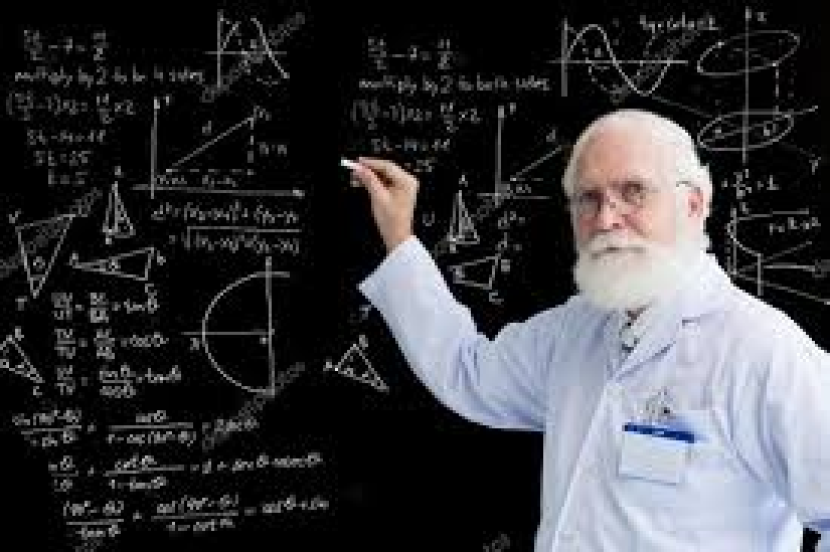
Oleh; Prof Dr Deddy Mulyana, Guru Besar Unpad dan pakar komunikasi.
*Pelanggaran etis mengenai pengangkatan _pejabat publik dan pesohor_ menjadi profesor yang menghebohkan di Tanah Air belakangan ini hanya puncak dari gunung es permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia. Jika saja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) no. 92 tahun 2014 pasal 10 ayat 1 secara tegas bahwa seorang calon profesor harus mengajar minimal 10 tahun, memiliki gelar akademis doktor, minimal 3 tahun setelah perolehan ijazah doktor, dan minimal 2 tahun menduduki jabatan lektor kepala, sangat sulit bagi pejabat publik dan pesohor untuk menjadi profesor.*
*Memangnya menjadi profesor itu kerja sambilan? Apalagi calon guru besar dituntut menerbitkan artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama dan berpengalaman sebagai pembimbing utama (promotor) mahasiswa S3.*
*Mengajar minimal 10 tahun itu seyogianya diterjemahkan sebagai durasi tanpa jeda atau tanpa dicicil. Calon profesor harus mengajar penuh waktu, bukan paruh waktu, apalagi sebagai dosen tamu yang mengajar 1-2 kali per semester, meski namanya tertera di program studi..Sulit dibayangkan, seorang profesor tidak memiliki home base tempat ia bekerja. Tanpa itu, ia tidak berhak memperoleh jabatan akademik profesor, seperti disebutkan Pasal 23 Undang-Undang no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan.*
Kebeletnya pejabat publik dan pesohor menjadi profesor menunjukkan rasa tidak percaya diri mereka.
Meminjam istilah (almarhum) Dr. Sudjoko yang dulu menjadi dosen ITB, mereka menderita krocojiwa.
Seolah ada relung hampa dalam mentalitas mereka yang harus mereka isi.
Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka juga cerdas seperti profesor yang berkarier sebagai akademisi. Mereka berilusi bahwa mereka bisa bergaul dengan lingkungan intelektual elite dan ekslusif yang dapat melambungkan citra dan wibawa mereka. Sebutan profesor memang istimewa di Indonesia karena digunakan penyandangnya dan diperlakukan orang lain sebagai profesor tidak hanya di dunia akademik seperti di Barat, tetapi pada semua pertemuan dan setiap waktu, termasuk saat resepsi pernikahan dan rapat RT.
Dengan menjadi profesor, pejabat publik dan pesohor merasa bisa disejajarkan dengan orang-orang kredibel yang menduduki puncak piramida pendidikan atau peradaban yang lebih universal ketimbang menjadi pejabat tinggi, politisi, dan pesohor tingkat institusional atau nasional.
Bukankah kecerdasan lebih bergengsi daripada jabatan atau kekayaan? Bukankah pendidikan tinggi formal sangat dihargai di negara mana pun? Mereka tidak sadar bahwa jabatan akademik profesor itu sarat dengan tanggung jawab dan menuntut dedikasi tinggi secara akademik.
Secara berkala seorang profesor sejatinya harus menunjukkan kapasitas intelektual mereka dengan mempublikasikan hasil pemikiran dan penelitian mereka melalui karya ilmiah berupa buku, artikel ilmiah di jurnal nasional dan jurnal internasional. Mereka dituntut untuk menyampaikan hasil pemikiran dan penelitian mereka dalam pertemuan ilmiah di tingkat nasional dan bahkan internasional, tanpa meninggalkan kewajiban rutin mereka sebagai pengajar di kelas untuk memotivasi mahasiswa, memberikan inspirasi dan pengetahuan kepada mereka. Kewajiban dan kualitas mengajar yang mumpuni ini tidak boleh diremehkan.
Snobisme ala pejabat publik dan pesohor di Indonesia ini langka kita temukan di negara- negara Barat demokratis seperti Amerika, bahkan di negara-negara berkembang di Asia, termasuk Malaysia. Barack Obama, Colin Powell, Steve Jobs, dan Elon Musk lebih bangga menjadi diri mereka sendiri dan dihormati khalayak karena karier mereka yang cemerlang dengan dedikasi mereka yang tinggi, meski mereka bukan profesor.
Namun di Indonesia, mengapa mereka yang sudah menjadi orang nomor satu atau eksekutif top di lembaga tinggi negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), petinggi partai politik, pemimpin bank sentral, jenderal polisi, dan jenderal militer, tidak puas dengan jabatan mereka dan masih menginginkan jabatan akademik profesor yang tidak linier dengan karier mereka? Dalam ungkapan Arief Anshory Yusuf yang Ketua Dewan Profesor Unpad dan Efa Laela Fakhriah yang salah satu ketua Komisi Senat Akademik Unpad, mereka serakah karena mereka mengambil yang bukan hak mereka. Ada benarnya pandangan Arief dan Efa.
Sementara pejabat publik dan pesohor dapat menyandang status profesor, profesor beneran tidak dapat menyandang status mereka. Jenderal bisa menjadi profesor, tetapi profesor tidak bisa menjadi jenderal.
Mengapa pejabat publik dan pesohor ini tidak bekerja sepenuh jiwa dalam bidang pekerjaan mereka untuk memperoleh kharisma dambaan mereka? Apakah mereka kurang kerjaan dan kelebihan waktu dalam karier mereka sehingga mereka bisa nyambi sebagai profesor?
Ketidakfokusan mereka pada karier mereka boleh jadi dipengaruhi konsep waktu polikronik (yang diasumsikan bersifat melingkar, jamak dan menyebar) yang dianut masyarakat tradisional Indonesia sehingga mereka dapat melakukan beberapa pekerjaan pada saat yang sama. Contoh nyata adalah seorang menteri yang juga menjadi pemimpin sebuah organisasi olahraga tingkat nasional.
Konsep waktu yang dianut pejabat publik dan pesohor yang kebelet jadi profesor itu kontras dengan konsep waktu monokronik bersifat tunggal seperti garis lurus yang dianut masyarakat Barat yang menuntut satu pekerjaan pada satu periode waktu. Ini bukan masalah perbedaan, atau mana yang lebih baik, antara konsep waktu Timur dan konsep waktu Barat.
Namun, berdasarkan nalar sehat, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses dan kredibel, kita harus fokus pada satu pekerjaan, apalagi pekerjaan besar demi kepentingan bangsa. Menurut teori sistem, kredibilitas itu sekadar pemberian dari khalayak. Khalayak akan sukarela memberikannya kepada kita, selama kita layak menerimanya. Sebaliknya, khalayak akan mengambil kredibilitas kita kembali jika kita tidak layak menerimanya.
Fakta bahwa banyak pejabat publik dan pesohor (ingin) menjadi profesor juga menunjukkan bahwa mereka masih menganut feodalisme. Dengan kata lain, mereka cenderung menghargai orang lain berdasarkan status bersifat bawaan alih-alih status karena prestasinya.
Gelar bangsawan seperti Raden di kalangan suku Jawa dan Sunda, Lalu (untuk laki-laki) dan Baiq (untuk perempuan) di kalangan suku Sasak, Andi (untuk Sulawesi Selatan) atau Laode (untuk laki-laki) dan Waode (untuk Perempuan) pada suku Buton memang sudah kedaluwarsa.
Mereka tidak tertarik pada gelar-gelar bangsawan yang mereka anggap kurang seksi, kalaupun mereka berhak. Namun, mereka ingin mendapatkan “gelar pengganti” seperti doktor kehormatan (Dr. HC), profesor, dan profesor kehormatan yang mereka pikir dapat mendongkrak harga diri mereka.
Tak heran segala acara yang tidak etis dan manipulatif dilakukan untuk memperolehnya. Dengan sebutan profesor yang mereka pikir mentereng, mereka petenteng-petenteng di depan khalayak, tetapi sebagian khalayak boleh jadi menertawakan mereka di belakang punggung mereka.
Seperti diungkapkan wartawan senior Bre Redana, menulis itu suatu tradisi.
Maka sulit dipahami bagaimana seorang pejabat publik atau pesohor ujug-ujug mampu menulis artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi tanpa melewati proses pembiasaan dan jatuh bangun dalam karier menulis. Menulis dalam bahasa Indonesia saja susah, apalagi dalam bahasa Inggris. Kecenderungan feodal dan kecenderungan lebih mementingkan hasil daripada proses itu pernah disinggung Mochtar Lubis sebagai ciri-ciri manusia Indonesia dalam pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki Jakarta tahun 1977 dan kemudian dibukukan dengan judul Manusia Indonesia (1978), dan kini masih relevan.
Pada akhirnya, permasalahan yang kita bahas ini hanya bisa dituntaskan jika pemerintah memiliki tekad politik. Kemenpenbudristek harus membuat regulasi yang transparan, sejalan dengan regulasi kementerian terkait lainnya dan regulasi perguruan tinggi di bawahnya. Sementara itu, perguruan tinggi pun harus berani melawan tekanan politik untuk melanggar aturan yang ada. Penganugerahan jabatan akademik profesor kepada orang yang tidak berhak menyandangnya hanya meruntuhkan martabat perguruan tinggi bersangkutan.Jika kita tetap abai membuat seperangkat regulasi yang solid berlandaskan meritokrasi, jangan-jangan para profesor kita hanya akan menjadi olok-olok bangsa lain.
--------
Deddy Mulyana (lahir 28 Januari 1958) Profesor Deddy Mulyana adalah Guru Besar dan Dekan ke-9 (2008-2012, 2012-2016) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Di fakultasnya, ia pernah menjadi Ketua Jurusan Jurnalistik (1996-1999) dan Koordinator Program Magister (2004-2008).