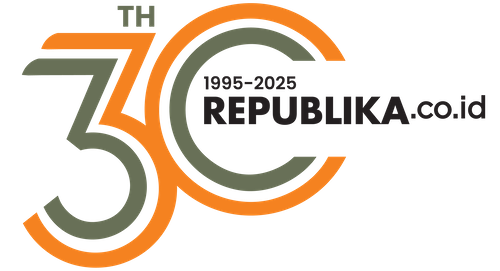REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Nasihin Masha
Ada tiga arus kuat dalam penolakan terhadap pembahasan RUU HIP. Pertama, kecurigaan bahwa di balik hadirnya RUU ini adalah orang-orang yang bersimpati atau bahkan pendukung komunisme atau PKI. Kedua, lahirnya RUU ini justru merupakan pengerdilan, mendegradasi, menyimpang, melemahkan, mendistorsi, dan mempersempit ruang tafsir Pancasila, dan bahkan menghilangkan roh Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Ketiga, hadirnya RUU ini dicurigai sebagai bagian dari upaya anti-demokrasi, yang sedang menjadi kecenderungan politik akhir-akhir ini. Ini merupakan trauma sejarah di era Demokrasi Terpimpin maupun di era Orde Baru.
Pada bagian ini, hanya akan mengulas poin pertama saja: kecurigaan terhadap kelompok-kelompok yang bersimpati atau bahkan bagian dari komunisme atau PKI. Dasarnya sederhana saja: tiadanya Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 sebagai bagian dari konsideran menimbang. Hal ini ditambah dengan upaya memasukkan Trisila dan Ekasila menjadi bagian dari tafsir resmi terhadap Pancasila. Dalam Trisila sila Ketuhanan Yang Maha Esa berubah menjadi Ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Sedangkan dalam Ekasila tidak ada lagi sila Ketuhanan. Apakah kecurigaan itu mengada-ada?
Pancasila dan Agama
Dalam berbagai pidatonya, Sukarno selalu menekankan tentang pentingnya Tuhan dan agama dalam kehidupan bernegara. Pidato 1 Juni 1945, yang menjadi hari lahir Pancasila, merupakan monumen terpenting dari gagasan Sukarno tentang itu. “Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan,” katanya. Menurutnya, bukan hanya penduduknya, warga negaranya, yang ber-Tuhan, tapi juga negaranya. Maksudnya, negara mengakui agama dan Tuhan. Inilah yang membuat Indonesia bukan negara sekular, tapi negara yang religius. Negara tak berlepas tangan dalam masalah ini. Karena itu, prinsip Ketuhanan ini diterima secara bulat sebagai salah satu sila dari lima sila, bahkan ditempatkan di nomor urut pertama.
Para pengamat Barat mengidentifikasi bahwa perjalanan ide kebangsaan di negara-negara di Asia berbeda dengan kebangkitan ide kebangsaan di Eropa. Di benua biru itu, ide kebangsaan muncul sebagai koreksi terhadap teokrasi. Ide kebangsaan di Eropa merupakan buah dari gerakan sekularisasi. Sedangkan di Asia, termasuk Indonesia, gerakan kebangsaan bahu membahu bersama dengan gerakan keagamaan untuk mencapai kemerdekaan untuk membentuk negara kebangsaan. “Inilah arti nasional bagi saya. Tidak berisi paham anti agama, tidak berisi paham anti lain-lain hal,” kata Sukarno saat berpidato berjudul Negara Nasional dan Cita-cita Islam di hadapan civitas academica UI pada 7 Mei 1953. Pidato ini merupakan penjelasan atas kontroversi pidatonya sebelumnya di Amuntai, Kalimantan, pada 27 Januari 1953. Dengan penjelasan itu, Sukarno tidak mempertentangkan negara nasional dan cita-cita Islam, atau secara umum tidak mempertentangkan negara nasional dengan agama.
Namun saat memberikan kursus tentang Pancasila, ada enam seri ceramah oleh Bung Karno, pada seri kedua menguraikan tentang sila pertama, pada 16 Juni 1958. Seri pertama berisi pendahuluan. Dalam penjelasan tentang Ketuhanan ini Sukarno menggunakan pendekatan evolusi darwinisme, pendekatan sosiologis tentang pertumbuhan masyarakat dan kesadaran tentang Ketuhanan. Menurutnya, masyarakat Indonesia masa lalu itu, sebelum kedatangan agama-agama dan paham luar, sudah mengenal ide tentang Ketuhanan. “Bangsa Indonesia itu hidup dalam alam Ketuhanan,” katanya.
Penjelasan Sukarno dimulai dengan tahap-tahap perkembangan masyarakat: masyarakat berburu, masyarakat beternak, masyarakat bercocok tanam, masyarakat pengrajin, dan akhirnya masyarakat industri. Inilah corak umum masyarakat manusia di manapun. Dan, katanya, “Cara hidup manusia memengaruhi alam pikirannya. Juga memengaruhi alam persembahannya, kalau boleh saya pakai perkataan ini.” Di fase pertama, ketika masyarakat manusia masih tahap berburu, maka manusia menyembah alam: petir, batu, gunung, pohon, sungai, laut, bulan, bintang, matahari, dan sebagainya. Pada fase beternak, manusia menyembah binatang: sapi, burung, dan sebagainya. Di fase pertanian, manusia menyembah dewi-dewi kesuburan seperti Dewi Sri, Dewi Laksmi. Di fase keempat, pada masyarakat pengrajin, ide tentang Tuhan mulai ghaib, tak bisa dilihat dan diraba. Ini karena kerajinan berpangkal pada ide-ide akal kreatif. Karena itu Tuhan menjadi abstrak, ada di pikiran. Di fase industri, katanya, “Manusia merasa dirinya atau sebagian daripada manusia merasa dirinya Tuhan”. Ini karena di masa industri, manusia merasa bisa membuat apapun. “Aku bisa, aku kuasa! Tuhan, persetan, tidak ada Tuhan itu. Lucunya di situ! Sebagian daripada manusia berkata: Tuhan tidak ada,” kata Sukarno.
Masyarakat Indonesia, kata Sukarno, “Terutama sekali masih di dalam alam perpindahan keempat, tiga ke empat, dan empat ke lima, sebagian besar masih agraris […] Sebagian hidup di dalam alam kerajinan […] Sebagian kecil yang telah hidup di dalam alam industrialisme itu.” Berdasarkan kenyataan itu maka rakyat Indonesia mempunyai kepercayaan terhadap adanya Tuhan. “Kalau Saudara tanya kepada saya persoonlijk, apakah Bung Karno percaya kepada Tuhan? Ya, saya ini percaya dan tadi sudah berkata saya ini orang Islam. Bahkan saya betul-betul percaya kepada agama Islam. Saya percaya dengan adanya Tuhan,” kata Sukarno menutup keraguan yang mungkin timbul. Penegasan ini perlu ia kemukakan karena pemikiran Sukarno sangat antroposentris dan darwinis. Hal ini tentu sangat menarik. Apakah jika masyarakat Indonesia sudah benar-benar pada fase industri, fase kelima, maka sila Ketuhanan tak diperlukan lagi? Atau premisnya dibalik, jika perkembangan masyarakat mengikuti garis linier model darwinisme, maka tahap industri merupakan tahap paling maju, dengan demikian maka masyarakat yang percaya pada Tuhan adalah masyarakat terbelakang dan ide Ketuhanan bagian dari keterbelakangan itu.
Demokrasi Terpimpin dan PKI
Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa puncak kejayaan PKI di Indonesia. Di masa sebelumnya, walau PKI meraih suara terbanyak keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU, namun PKI tak pernah ikut berkuasa. Koalisi pemerintahan selalu tak menyertakan PKI. Hal ini juga dikeluhkan oleh Sukarno. Namun setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, PKI mulai unjuk gigi. Apalagi setelah bangunan sistem Demokrasi Terpimpin mulai terbentuk. Sukarno membubarkan DPR, lalu ia membentuk DPR yang baru dan MPR yang baru, yang anggota-anggotanya diangkat Presiden. Masyumi dan PSI dibubarkan. Pada tahap inilah, perwujudan pelaksanaan Pancasila mulai diwujudkan sesuai tafsir pemerintah saat itu. Misalnya soal Nasakom, golongan fungsional, presiden seumur hidup, hadirnya front nasional, musyawarah mufakat, dan lain-lain.
Tentang musyawarah mufakat, kita bisa melihat Tap MPRS No VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip-prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga-lembaga Permusyawaratan Perwakilan. Tap ini ditetapkan pada 16 April 1965. Tap ini dibagi dalam lima bab: Pendahuluan, Demokrasi Terpimpin, Prinsip Musyawarah untuk Mufakat, Pentrapan dan Pedoman Pelaksanaan Musyawarah untuk Mufakat, dan Ketentuan Penutup. Pada intinya, Tap ini mencoba menjabarkan sila keempat Pancasila yang ditafsirkan sebagai Demokrasi Terpimpin dengan inti musyawarah mufakat. Pada Bab II angka 1 (1) tertulis: “Demokrasi Terpimpin ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner berporoskan Nasakom.” Prinsip gotong royong inilah yang menjadi sumber nilainya, yang menjadi Ekasila.
Bab musyawarah mufakat ini juga kemudian masuk dalam Doktrin Tri Ubaya Sakti, doktrin dasar tentara yang dihasilkan dari Seminar TNI Angkatan Darat I di Seskoad, Bandung. Seminar diadakan pada 2-9 April 1965. Namun satu tahun kemudian, Doktrin ini mengalami perubahan setelah Sukarno jatuh dan diganti melalui Seminar TNI Angkatan Darat II pada 25-31 Agustus 1966. Tap MPRS No VIII/MPRS/1965 juga kemudian dicabut melalui Tap MPRS No XXXVII/MPRS/1968.
Dalam RUU HIP, seperti ditulis pada tulisan saya seri #1, pemerintah pusat adalah presiden itu sendiri dan presiden sebagai pemegang kekuasaan pembinaan haluan ideologi Pancasila. Dengan demikian, presiden memiliki posisi sangat kuat. Pada saat bersamaan RUU HIP juga mengatur tentang pengutamaan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
Tap MPRS No VIII/MPRS/1965 maupun Doktrin Tri Ubaya Sakti versi 1965 tak hanya berbicara tentang musyawarah mufakat tapi juga frasa-frasa dan diksi-diksi yang menjadi ciri khas gerakan komunisme di mana pun di dunia. Namun tentu saja pada Tap MPRS dan Doktrin tersebut menjadikan Pancasila sebagai rujukan, sebagaimana RUU HIP.
Baca Tulisan Sebelumnya:
Karena itu, kecurigaan terhadap komunisme dalam masalah RUU HIP tersebut memiliki relevansi dengan pengalaman sejarah. Dalam sidang-sidang Konstituante maupun dalam kampanye Pemilu 1955 serta dalam berbagai tulisan dan pidato tokoh-tokoh komunis saat itu selalu berbicara tentang pembelaan terhadap Pancasila. Namun seperti dicatat sejumlah penulis, pada awal Mei 1964, Ketua CC PKI DN Aidit membuat pernyataan: “Pancasila mungkin untuk sementara dapat mencapai tujuannya sebagai faktor penunjang dalam menempa kesatuan dan kekuatan Nasakom. Akan tetapi begitu Nasakom menjadi realitas, maka Pancasila dengan sendirinya tak akan ada lagi.”
Hal ini menimbulkan kemarahan pada Sukarno. Sehingga pada 1964, Sukarno membuat peringatan hari lahir Pancasila secara resmi dengan ketuanya Subandrio. Panitia menerbitkan ulang materi pidato-pidato Sukarno tentang Pancasila. Tak hanya pidato 1 Juni 1945 tapi juga materi kursus Pancasila. Reaksi Bung Karno yang seperti itu, membuat Aidit melakukan klarifikasi. Aidit membuat tulisan berjudul Aidit Membela Pancasila dan juga ada wawancara khusus dengan Solichin Salam yang dimuat majalah Pembina pada 12 Agustus 1964.
Dalam wawancara itu Aidit menegaskan bahwa “PKI menerima Pancasila sebagai keseluruhan. Hanya dengan menerima Pancasila sebagai keseluruhan, Pancasila dapat berfungsi sebagai alat pemersatu. PKI menentang pemretelan terhadap Pancasila”. Sebagai contoh tidak ada pemretelan ia menerangkan soal sila Ketuhanan dan sila Kedaulatan Rakyat yang berkonsekuensi “tidak boleh ada propaganda anti-agama, tetapi juga tidak boleh ada paksaan beragama”, maksudnya adalah kebebasan untuk tak beragama. Aidit juga menerangkan bahwa saat itu Indonesia pada tahap pertama revolusi, yaitu tahap nasional-demokratis. Saat itu belum masuk tahap kedua yang ia sebut sebagai tahap sosialis. “Apakah berbeda atau tidak pembangunan masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila dengan yang berdasarkan Marxisme-Leninisme, hal ini akan kita ketahui kalau kita sudah sampai pada tahap kedua nanti,” kata Aidit. Penjelasan ini mencerminkan pandangannya tentang Pancasila dan Marxisme-Leninisme. Pancasila hanya sebagai alat pemersatu di fase Nasakom dan tetap konsisten pada pandangannya seperti pernyataan sebelumnya pada awal Mei 1964.
“Mereka sama sekali tidak memperdulikan bahwa inti daripada Pancasila ialah Ekasila atau Gotong Royong,” kata Aidit dalam pidato Berani, Berani, Sekali Lagi Berani, yang disampaikan dalam Sidang Pleno CC PKI pada 10 Februari 1963. Hal itu ia kemukakan saat membahas sila Ketuhanan yang ia sebut dipreteli karena menolak komunisme yang tak mengakui Tuhan.
Ada satu sinyal menarik dari pernyataan PBNU yang menyebutkan upaya menjadikan Pancasila sebagai “ideologi kerja”. Frasa ini sangat jelas tertuju ke mana dan apa arahnya.