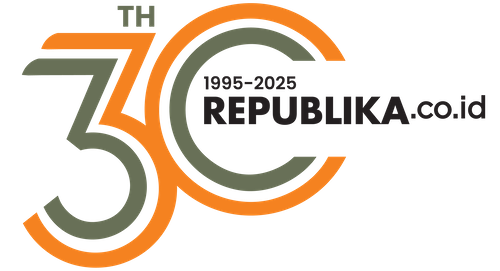REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Alex Yungan, S.Hut*
Sejak tahun 2003, pemerintah telah berusaha menyusun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh. Namun, usaha tersebut sempat terhenti ketika Aceh dilanda musibah tsunami pada 2004. Pascatsunami, upaya penyusunan RTRW Aceh kembali dilakukan pemerintah Aceh, sekitar 2006 hingga 2009.
Pada periode tersebut, pemerintah Aceh menginginkan penambahan jumlah hutan pada tiap kabupaten. Penambahan luas hutan yang direncanakan nantinya akan menjadi ± 4.047.897 hektare (ha) dari luas hutan semula ± 3.248.892 ha. Dengan kata lain akan terjadi penambahan luas hutan sebesar ± 799.005 ha di wilayah Aceh.
Namun kenyataannya, kebijakan tersebut mendapat penolakan dari tiap kabupaten/kota. Alasannya adalah kebijakan tersebut akan mengurangi kawasan budidaya masyarakat. Ketakutan ini menjadi beralasan, ketika pemukiman masyarakat yang telah ada sejak lama ternyata masuk dalam usulan penambahan hutan. Akibat penolakan tersebut, akhirnya membuat pemerintah pusat tidak menyetujui kebijakan pemerintah provinsi kala itu. Hingga akhir 2012, RTRW Aceh tidak kunjung disahkan.
Polemik RTRW Aceh tidak berhenti sampai disitu. Pada November 2013, organisasi yang konsen terhadap masalah lingkungan hidup, seperti Walhi Aceh melayangkan petisi online kepada Gubernur untuk melindungi Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dari kerusakan. Petisi ini didukung sebanyak 14.835 orang. Mereka mendesak agar Gubernur tidak meloloskan regulasi yang akan memberikan izin pengembangan budidaya di KEL.
Puncaknya pada 30 Desember 2013, aliansi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Aceh. Ratusan massa protes dan menolak Qanun RTRWA 2013-2033 yang sebelumnya telah disahkan oleh DPR. Alasannya adalah karena RTRW tersebut akan mengurangi luas hutan Aceh, penyebutan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dihilangkan dan tidak memasukkan hak kelola mukim sebagai masyarakat adat di sana.
Menjadi menarik mencermati polemik tersebut, karena ada dua motif berbeda dibalik persoalan RTRW. Pertama, menjadi hal yang lucu ketika ada kebijakan pemerintah yang mencanangkan penambahan luas hutan di wilayah Aceh, tetapi justru oleh masyarakat Aceh sendiri ditiap kabupaten/kota menolak kebijakan tersebut. Disisi lain, saat ada pemerintah yang mencanangkan kebijakan sebaliknya, ada pula mayarakat yang tergabung dalam KPHA menolak kebijakan tersebut.
Jika memang kekhawatirannya adalah soal kelestarian lingkungan, maka kebijakan pemerintah Aceh periode sebelumnya ketika ingin menambah luas hutan, harusnya mendapat apresiasi baik dari segenap elemen masyarakat. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Rasanya ada konflik kepentingan di balik polemik RTRW Aceh ini.
Kata ‘demi masyarakat’ memang seringkali dijadikan komoditas untuk diperdagangkan. Adakalanya kata ini ampuh, namun adakalanya kata ini akan dilindas zaman pula nantinya. Rasanya kita harus benar-benar bertanya pada masyarakat Aceh yang ‘sesungguhnya.’
Kedua, dibalik itu semua, ada hal lain yang patut dicermati lebih mendalam. Adanya dua motif berbeda dibalik polemik RTRW Aceh ini menunjukkan bahwa pemerintah Aceh menjalankan manajemen coba-coba ketimbang manajemen adaptif dalam menyelesaikan RTRW-nya. Ketika satu kebijakan dicanangkan dan kebijakan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka pemerintah mencoba dengan kebijakan yang lain. Inilah potret manajemen pemerintah Aceh, khususnya dalam RTRW yang sedang berlangsung hingga saat ini.
Tentang tata ruang
Tata Ruang diatur melalui UU No. 26/2007. Salah satu isu utama yang sering disoroti dan kerap menjadi ketakutan banyak pihak adalah soal pertambangan. Soedomo (2012) mengungkap bahwa dalam isu tersebut perlu terjadi perombakan besar, terutama dalam pemikiran. Sebab banyak pihak yang menafsirkan pasal 5 ayat (2) UU No. 26 tahun 2007 sebagai “kegiatan pertambangan diperbolehkan hanya di dalam kawasan budidaya.” Tafsiran ini muncul karena bunyi pasal 5 ayat (2) UU No. 26 tahun 2007 yang menyatakan “Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya”.
Pertanyaan yang terlebih dulu harus dijawab ialah, 'peruntukan menentukan fungsi kawasan' atau 'fungsi kawasan menentukan peruntukan?'
Kita menyadari bahwa sumber daya tambang adalah sumberdaya yang hanya dapat dihasilkan melalui proses alami oleh alam dan tidak mungkin dapat diadakan secara buatan oleh manusia ataupun teknologi. Karena karakteristiknya yang alami ini (tidak dapat diadakan oleh manusia atau teknologi), maka konsekuensi logisnya adalah, peruntukan pertambangan hanya diperuntukkan bagi kawasan yang mengandung bahan tambang.
Dengan kata lain, peruntukan kawasan menentukan fungsinya, bukan sebaliknya. Adalah hal yang sangat tidak logis bila suatu kawasan diperuntukkan bagi pertambangan ketika tidak ada informasi tentang adanya sumberdaya tambang yang secara ekonomis layak untuk dimanfaatkan.
Jadi, interpretasi terhadap pasal 5 ayat (2) UU No. 26/2007 yang lebih logis adalah “bahwa kawasan dengan peruntukan pertambangan digolongkan sebagai kawasan yang berfungsi budidaya (Soedomo, 2012).” Lebih tegasnya, jika ada kawasan lindung yang dikemudian hari diketemui dan diketahui mengandung sumberdaya tambang yang layak dimanfaatkan maka fungsinya harus diubah menjadi kawasan budidaya, bukan melarang pertambangan di dalam kawasan lindung tersebut.
Kini yang perlu dilakukan masyarakat Aceh adalah bagaimana mengawal sumberdaya alam Aceh agar dapat terdistribusi secara merata dan tidak dikuasai oleh satu pihak. Satu hal yang patut diingat adalah tujuan kita untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat, bukan menjauhkan sebesar-besar kemakmuran dari rakyat.
*Penulis adalah peneliti di FORCI Development (Centre for Forestry Organization Capacity and Institution Development), Fakultas Kehutanan IPB