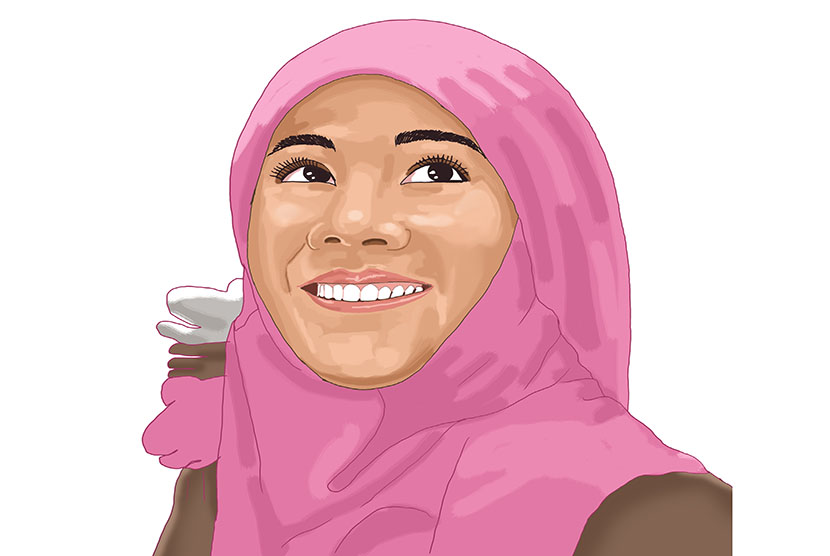REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Asma Nadia
Di sebuah stasiun, seorang gadis dengan wajah gusar mendatangi saya yang sedang menunggu kereta keberangkatan. Sosoknya terlihat letih. Butiran keringat terlihat seperti manik-manik di pelipis. Setelah memperkenalkan diri, tanpa banyak basa- basi ia melontarkan satu pertanyaan.
“Mbak, saya bingung! Apa saya salah?”
Saya masih belum mengerti ke mana arah pembicaraan.
“Bingung?”
Masih dengan napas tersengal ia meneruskan.
“Begini Mbak, ada kasus perempuan terlibat prostitusi. Dibayar puluhan juta untuk berhubungan dengan pengusaha. Lalu, tertangkap oleh aparat yang sejak awal memang mengejarnya. Menurut berita, bahkan aparat menangkap basah keduanya saat sedang berzina.”
Gadis itu mencoba menghela napas panjang, sebelum melanjutkan.
“Tapi yang saya tidak mengerti mengapa mereka justru bebas. Dan yang diperkarakan adalah makelarnya. Ini kan aneh. Orang menjual diri bukan tersangka, yang membayar bukan tersangka, tapi yang menjadi mediator malah ditangkap. Menurut Mbak?”
Ah, tentang itu rupanya.
Terus terang saya bukan pakar akademisi di bidang hukum, akan tetapi kebingungan gadis itu mewakili rasa keadilan masyarakat saat ini.
Belum sempat saya menjawab, sang gadis, yang di sela-sela perkenalan sempat bercerita dirinya sedang belajar keras untuk masuk ke fakultas hukum universitas favorit, sudah melemparkan pertanyaan kedua.
“Ada lagi Mbak, kasus dua lelaki kepergok di mobil sedang melakukan aktivitas seksual sesama jenis lalu tertangkap basah masyarakat. Kemudian setelah diproses ke kantor aparat penegak hukum. Sekalipun dengan bukti dan saksi yang cukup kuat, keduanya dilepaskan alasannya tidak ada pasal yang bisa menjerat hubungan antara sesama jenis.”
Saya menghela napas, belum sempat menjeda gadis itu kembali berujar.
“Padahal di tempat lain, banyak pesta gay yang digerebek dan dibawa ke kantor penegak hukum. Jujur saya bingung kenapa di satu tempat hal ini diperkarakan di tempat lain justru dibebaskan?”
Oh. Mulut saya membulat. Tapi, lagi-lagi tanpa memberi kesempatan merespons, si gadis untuk kesekian kali meneruskan percakapan sepihak ini.
“Ada lagi Mbak, kasus kepala daerah yang diproses hukum karena dianggap jarinya memberi kode simbol kampanye satu kandidat pilpres. Padahal itu dilakukan saat cuti. Lebih aneh lagi, sebelumnya ada menteri, juga banyak kepala daerah lain yang secara terang menderang menyatakan dukungan ke kandidat tertentu, tapi mereka tidak dipermasalahkan. Kasus sama, keadilan yang diberlakukan kok berbeda-beda? “
Sekali ini saya sengaja tidak merespons. Menunggu saja dia memuntahkan semua unek-unek. Dan benar, si gadis tak tampak menantikan jawaban, justru sebaliknya.
“Padahal Mbak, aku mau jadi sarjana hukum karena hukum adalah panglima, kita ini negara hukum. Nah, kalau penerapan hukum seperti ini, rasanya malu.”
Wajahnya pias. Air mata mulai mengendap-endap di bola matanya. Saya raih tangannya, saya usap pelan. Berusaha mengalirkan semangat saat harapan seolah menguap entah ke mana.
“Kamu sebaiknya tetap mengejar impian menjadi sarjana hukum. Kalaupun hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya justru keberadaanmu yang kelak akan meluruskan, atau setidaknya menjadi bukti hidup. Contoh nyata pihak yang tidak mewakili ketimpangan tadi.’
Dia terdiam. Sepasang mata dengan bulatan hitam besar, tertuju lurus ke arah saya. Berangsur senyumnya mengembang.
Bagus, dia sudah lebih tenang. Sepertinya ini saat yang tepat bagi saya mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan sang gadis.
Kami bertatapan. Saya menarik napas, sementara benak mengatur kata-kata yang siap meluncur. Tapi sebelum sepatah pun lahir dari lisan, mendadak terdengar pengumuman kereta yang akan segera meninggalkan stasiun. Si gadis terkesiap, menyimak dengan saksama.
Lalu, seperti kehadirannya yang tiba-tiba, si gadis dengan mudah beranjak. Kali ini dengan senyum samar terselip di bibir, dan sepotong ucapan terima kasih.
Saya tercengang. Dilanda keheranan. Tidak satu pun pertanyaannya sempat saya jawab. Tapi, dia memang seakan tidak membutuhkan jawaban. Mungkin semua lontaran tadi, murni bersifat retoris.
Ia, seperti juga sebagian kita, mungkin hanya butuh melepaskan beban yang selama ini menyumbat pikiran. Malangnya beban itu kini justru tertinggal di kepala saya, dan kian memberati.