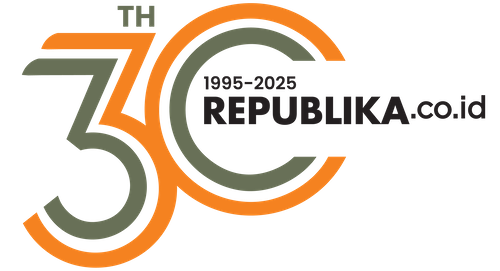REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Sunarsip
“Kekeliruan” terbesar dari BJ Habibie adalah sejarah. Yaitu, sejarah yang telah menempatkan dirinya menjadi presiden menggantikan Soeharto sehingga apa pun kebijakan yang diambil Habibie ketika itu selalu dianggap sebagai kebijakan untuk melanggengkan kekuasaan rezim Soeharto atau Orde Baru.
Terlebih, sebelum menjadi presiden dan wakil presiden, BJ Habibie adalah seorang menteri yang saat itu sedang “naik daun” dengan berbagai prestasinya di bidang teknologi dan menjadi kesayangan Soeharto.
BJ Habibie mulai membantu Soeharto sebagai menteri adalah sejak 1978, yaitu ketika menggantikan Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai menteri negara riset dan reknologi (Menristek). BJ Habibie menjabat menristek selama 20 tahun, sebelum ditunjuk sebagai wakil presiden pada 11 Maret 1998.
BJ Habibie sebagai wakil presiden hanya selama dua bulan karena pada 21 Mei 1998 dilantik menjadi presiden ke-3 RI menggantikan Soeharto yang menyatakan berhenti akibat unjuk rasa dan krisis multidimensi yang menuntut dirinya mundur. Nah, sejak menjadi presiden inilah drama perseteruan Habibienomics dengan para penentangnya terjadi dengan sangat kuat.
Istilah Habibienomics pertama kali dimunculkan oleh Kwik Kian Gie (KKG) pada 4 Maret 1993 melalui tulisannya di sebuah media massa nasional. Pemikiran utama yang melandasi lahirnya Habibienomics sebenarnya sederhana.
Menurut BJ Habibie, perekonomian Indonesia harus dibangun melalui pengembangan teknologi untuk menciptakan keunggulan kompetitif (competitive advantage) dalam rangka mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Kunci utama untuk mewujudkan keunggulan kompetitif adalah investasi di bidang sumber daya manusia (SDM).
BJ Habibie bukanlah seorang ekonom, dirinya adalah insinyur. Karena itu, tidak mengherankan bila pemikirannya lebih mengarusutamakan teknologi.
Sesungguhnya, pemikiran BJ Habibie merupakan pemikiran yang rasional. Dalam ilmu ekonomi modern, berbagai model ekonomi juga telah memasukan unsur teknologi sebagai faktor yang turut menentukan kenaikan output melalui kenaikan nilai tambah (value added).
Dengan kata lain, selain faktor produksi berupa sumber daya alam (tanah), manusia (tenaga kerja), dan modal (investasi) yang telah dikenal sejak Adam Smith (1776), teknologi juga berperan dalam menentukan pertambahan output nasional. Bahkan, variabel teknologi sebagai faktor produksi telah diperkenalkan oleh pemikir ekonomi David Ricardo pada 1917.
Pemikiran ekonomi BJ Habibie menimbulkan polemik, terutama sejak KKG melabelinya dengan istilah Habibienomics. Salah satu poin krusial dari pemikiran ekonomi BJ Habibie yang akhirnya menimbulkan polemik adalah konsep mengenai competitive advantage.
Konsep competitive advantage ala BJ Habibie ini dianggap berlawanan dengan arus utama (antimainstream) yang saat itu mendominasi kebijakan ekonomi Indonesia. Arus utama pemikiran ekonomi yang saat itu mendominasi kebijakan ekonomi Soeharto atau Orde Baru adalah konsep tentang keunggulan komparatif (comparative advantage), buah pemikiran ahli ekonomi Widjojo Nitisastro atau yang dikenal dengan istilah Widjojonomics.
Perbedaan utama antara konsep “comparative advantage” ala Widjono Nitisastro dan competitive advantage ala BJ Habibie terletak pada aspek yang ditekankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada konsep comparative advantage, penekanan utama adalah kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia untuk mengejar ketertinggalan ekonominya.
Keunggulan komparatif kita saat itu antara lain sumber daya alam yang melimpah dan upah tenaga kerja yang relatif murah. Berbagai keunggulan komparatif ini bila pemanfaatannya dimaksimalkan dapat mendorong kenaikan output dan menciptakan lapangan kerja yang luas, yang sangat dibutuhkan, karena saat itu kita sedang berupaya baru keluar dari krisis multidimensi yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelum Orde Baru.
Sementara itu, pada konsep competitive advantage, penekanannya adalah nilai tambah melalui pemanfaatan teknologi. Melalui konsep ini diharapkan Indonesia tidak lagi mengandalkan sumber daya alam yang melimpah serta upah buruh yang murah, melainkan dengan memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan output yang lebih besar. Sekaligus, melalui pemanfaatan teknologi, Indonesia dapat menyetarakan diri dengan negara-negara maju di bidang teknologi.
Kedua pemikiran ini sebenarnya memiliki landasan yang rasional. Kedua pemikiran ini keluar pada era yang berbeda dan tentunya kebutuhan bangsa yang berbeda pula. Saya berpendapat, kedua pemikiran ini hanya masalah tahapan saja.
Setelah pemerintah berhasil membangun ekonomi melalui pemanfaatan keunggulan komparatifnya, memang sudah saatnya beralih mengembangkan keunggulan kompetitifnya melalui teknologi, sebagaimana tahapan yang dilakukan oleh negara yang telah berkembang menjadi negara maju seperti Korea Selatan. Presiden Soeharto pun sebenarnya mengelola kedua pemikiran ini dengan cukup bijak, yaitu dengan memberikan ruang bagi keduanya berkembang dan tidak menjadikan keduanya sebagai dogma.
Sayangnya, sejarah tidak berpihak pada Habibienomics. Habibienomics dianggap menyimpang oleh para pengikut fanatik Widjonomics. Habibienomics dianggap terlalu mahal dan hanya mengejar gengsi sebagai negara.
Para penentang Habibienomics menganggap Indonesia belum membutuhkan teknologi canggih yang dikembangkan BJ Habibie. Di saat yang sama, Indonesia memang sedang menderita krisis ekonomi akibat krisis moneter 1997/98, sehingga terdapat alasan untuk “membunuh” Habibienomics.
Kekhawatiran para penentang Habibienomics semakin meningkat ketika BJ Habibie secara otomatis menjadi presiden ke-3 RI. Khawatir Habibienomics akan berlanjut, diciptakanlah stigma bahwa BJ Habibie dan Habibienomics adalah part of problem, part of Soeharto.
Bahkan, sebuah media nasional yang sejak awal menentang kepemimpinan BJ Habibie, setiap harinya memberitakan berita negatif tentang BJ Habibie dan sekaligus menampung opini dari pihak-pihak yang berseberangan dengan BJ Habibie.
Dan upaya mereka akhirnya memang berhasil! Selama kepemimpinannya, BJ Habibie bahkan terpaksa mengikuti rekomendasi dari lembaga moneter internasional (IMF) untuk menghentikan sejumlah industri strategis yang dirintisnya. Perlu diketahui, rekomendasi IMF tersebut juga hasil masukan dari para penentang Habibienomics. Secara perlahan, satu per satu industri strategis rintisan BJ Habibie dimatikan (shut down).
Pada 20 Oktober 1999, BJ Habibie pun berhenti sebagai presiden RI karena laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR dan Habibienomics pun ikut “mati”. BJ Habibie akhirnya hanya menjabat selama 17 bulan dengan torehan catatan prestasi ekonomi meski tidak fantastis, tetapi relatif baik, mengingat krisis ekonomi yang dahsyat.
Minggu lalu, 11 September 2019, Indonesia tidak hanya kehilangan Habibienomics, tetapi sekaligus kehilangan jasad BJ Habibie karena dipanggil sang Khaliq. Sayangnya, hingga BJ Habibie pergi, tahapan ekonomi Indonesia belum bergerak dari comparative advantage, dan itu pun manfaatnya semakin berkurang.
Buktinya, kinerja ekonomi kita masih dengan mudah terombang-ambingkan oleh pergerakan harga komoditas sumber daya alam. Kini, beberapa dari penentang Habibienomics berada dalam pemerintahan.
Semoga mereka menyadari kekeliruannya dulu tentang Habibienomics dan menebusnya melalui pengembangan teknologi dan industri strategis bagi peningkatan nilai tambah.