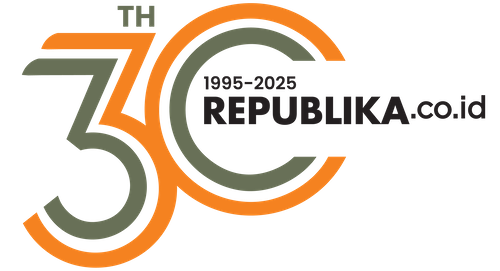Sengitnya persaingan politik, yang menjurus ke arah keretakan sosial, di seputar pemilihan presiden kali ini tidak bisa dibaca sekadar bentrokan ambisi kuasa. Gejala ini menyembunyikan persolan yang lebih besar, berkaitan dengan ekspresi kebebasan di ruang publik dalam konteks demokrasi padat modal dengan ketimpangan sosial yang lebar.
Ruang publik ideal, dalam pandangan Habermas, adalah domain tempat opini publik terbentuk yang menjamin berlangsungnya komunikasi bebas penguasaan serta argumen yang kritis dan rasional. Para partisipan dalam wacana publik tidak terhambat oleh ketidaksetaraan dan pemaksaan sehingga terjadi proses belajar secara kolektif.
Seiring dengan perkembangan suatu masyarakat dari kehidupan tradisional menuju modern, arena untuk proses belajar kolektif (collective social learning) ini beralih dari ikatan-ikatan komunal-tertutup menuju asosiasi-terbuka, dari ikatan-ikatan keturunan dan kasta menuju masyarakat kelas. Bentuk komunikasi dan belajar sosial (social learning) yang diciptakan dan dipraktikkan oleh asosiasi-asosiasi terbuka yang bersifat sukarela dan egaliter ini melahirkan apa yang disebut sebagai "civil society".
Dalam konteks Indonesia, Orde Reformasi menjadi momentum bagi keterbukaan ruang publik dan pemberdayaan civil society. Hal ini ditandai oleh penguatan kembali hak-hak sipil, kebebasan berpendapat, berkumpul dan berorganisasi, yang selama Orde Lama dan Orde Baru dikekang oleh negara.
Walaupun demikian, nilai-nilai demokrasi tidak bisa ditegakkan dengan mudah di tengah tingkat pendidikan rendah, buruknya situasi ekonomi, dan lemahnya supremasi hukum. Bahkan, transisi demokrasi dan reformasi politik tanpa dukungan tertib hukum dan keadilan sosial-ekonomi sering kali dibarengi tindakan-tindakan anarkis, konflik sosial, dan kekerasan etno-religius.
Di masa transisi demokrasi, kekuatan civil society sangat penting dalam mendukung demokrasi. Namun, kekuatan civil society bergantung pada persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk perdebatan publik.
Dalam ruang publik yang bebas, setiap individu mempunyai posisi yang sama satu sama lain dalam melakukan transaksi-transaksi wacana dan praktik politik tanpa mengalami tekanan dan distorsi. Kedua, keadaan yang demokratis yang memungkinkan adanya kebebasan bagi warga negara, terpeliharanya hak-hak asasi manusia dan ketertiban umum.
Ketiga, kuatnya sikap toleran yang memungkinkan adanya saling menghargai setiap perbedaan dan menghormati aktivitas yang dimiliki orang lain. Keempat, keadilan sosial-ekonomi yang menjadi basis kesetaraan dalam partisipasi politik.
Dengan kata lain, penguatan demokrasi dan civil society mengandaikan adanya kebebasan yang bersejalan dengan keadilan. Dalam hal kebebasan, jika pada sistem politik otoritarian, ancaman utama dari civil society muncul dari negara, dalam sistem demokratis, ancaman itu justru muncul dari kekuatan-kekuatan civil society, yakni berupa kemunculan fanatisisme komunalistik. Fanatisisme merupakan antipoda atas civil society karena menolak rasionalitas, prinsip representasi dalam politik, serta pemerintahan hukum (konstitusional) sebagai bantalan vital demokrasi.
Menurut Huntington, kelompok-kelompok marginal yang terlempar dari gelanggang politik formal akan mengembangkan fanatisisme dan cenderung bersikap "iri" (resentment) terhadap kebebasan, partisipasi, dan modernisasi.
Tetapi, fanatisisme tidaklah muncul tanpa akar. Ia muncul akibat terganggunya basis-basis keadilan dan distorsi komunikasi dalam ruang publik. Berdasarkan pengalaman, banyak kekerasan dan konflik sosial terjadi akibat ketidakadilan (nyata maupun perseptual) serta deprivasi sosial. Kedua hal ini diakibatkan terutama oleh kesenjangan dalam alokasi sumber daya, baik pada tingkat domestik maupun internasional serta lumpuhnya daya-daya komunikatif karena subordinasi dunia kehidupan (lifeworld) oleh dunia sistem.
Keadilan hukum terganggu ketika warga negara diberi perlakuan yang berbeda atau tak diberi perlindungan atas hak-hak sipil dan politiknya. Jika warga negara gagal memperoleh perlindungan dari negara, secara alamiah mereka akan mencari perlindungan dari sumber-sumber yang lain. Sumber-sumber alternatif ini bisa dalam bentuk premanisme, koncoisme, etnosentrisme, kelompok-kelompok kegamaan eksklusif, dan seterusnya.
Ketidakadilan ekonomi berperan besar dalam menyulut fanatisisme. Demokrasi tidak melulu berhubungan dengan politik. Bagi Alexis de Toxqueville, demokrasi memiliki makna di luar politik, yaitu kesederajatan kondisi sosial dan ekonomi ditambah dengan semangat egalitarianisme dan keinginan merdeka. Fanatisme berkembang subur saat berhadapan dengan ketimpangan ekonomi-politik.
Ketimpangan ini terjadi, baik karena warisan aneka diskriminasi kolonial maupun rezim-rezim otoriter pascakolonial. Tetapi, sumber ketimpangan sosial-ekonomi baru yang tak kalah pentingnya adalah konsekuensi dari globalisasi dan penetrasi kapitalisme.
Di Indonesia, pergeseran ke arah sistem politik demokratis yang membawa serta gelombang aspirasi neoliberal dalam perekonomian terjadi ketika tradisi negara kesejahteraan belum berjejak. Penetrasi kapital dan kebijakan propasar di tengah-tengah perluasan korupsi serta lemahnya regulasi negara dan pelaku ekonomi "kebanyakan", memberi peluang bagi bersimaharajalelanya "predator-predator" raksasa, yang secara cepat memangsa pelaku-pelaku ekonomi menengah dan kecil.
Ekspansi kepentingan predator besar ini tak berhenti pada dunia usaha, melainkan juga menyusup ke soal perumusan perundang-undangan, bahkan sampai pada pemilihan pejabat pemerintah di daerah.
Alhasil, untuk mencapai demokrasi substantif, kebebasan di ruang publik harus dikelola secara dewasa. Ketidakmampuan masyarakat dalam mengorganisasi kebebasan memunculkan kekhawatiran terjadinya "kebebasan yang kebablasan", yang mengandung ancaman terjadinya anarki. Inilah yang dicemaskan banyak pihak bahwa kebebasan tidak dibarengi dengan prinsip tanggung jawab.
Konsolidasi demokrasi di Indonesia akan berhasil jika kita berhasil mengelola tuntutan kebebasan yang bersejalan dengan keadilan. Jika keduanya tak berjalan berkelindan, ancaman yang akan kita hadapi tidak saja soal disintegrasi sosial, tapi juga akan hancurnya kerekatan sosial (social bond) dalam masyarakat.
Bila kerekatan sosial hancur, akan tumbuh social distrust (iklim tidak saling memercayai) di antara kelompok-kelompok sosial, sehingga kelompok yang satu dengan yang lainnya dalam masyarakat akan saling curiga, saling bermusuhan atau bahkan yang paling mengerikan, adanya upaya untuk saling meniadakan.
Dalam situasi ini, tawuran massal gaya Thomas Hobbes, perang semua lawan semua (war of all againts all), bukan lagi mitos. Dengan ini, kita sadar, betapa pentingnya membuka diri penuh cinta untuk yang lain. n oleh yudi latif