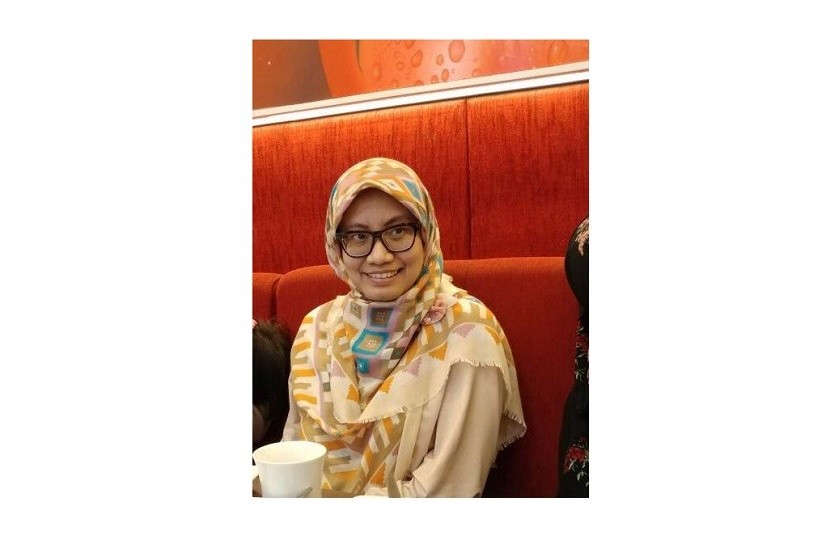REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Reiny Dwinanda*)
Enam bulan sejak kasus pertama Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia, penahaman masyarakat tentang penyakit infeksi virus SARS-CoV-2 ini memang masih sangat beragam. Coba saja lihat kolom komentar di media sosial yang membahas berita-berita tentang pandemi.
Banyak sekali yang menganggap Covid-19 ini tidak semengerikan yang dikabarkan. Mereka juga bilang, virus corona akan lenyap kalau media berhenti memberitakannya.
Soal ini, segenap elemen masyarakat harus introspeksi. Kesalahan apa yang telah diperbuat hingga memburamkan pandangan masyarakat tentang pandemi.
Saya jadi teringat pidato PM Singapura Lee Hsien Loong soal respons pemerintahnya mengenai Covid-19 di depan Parlemen pada pekan ini. Ia berterima kasih atas upaya abdi negara, pemimpin politik, pelaku bisnis, dan publik untuk keterlibatannya dalam menjalankan dan mematuhi aturan pegendalian dan pencegahan Covid-19 yang "tough and painful".
Ya, berat dan menyakitkan, tetapi itu penting untuk saat ini. Di Indonesia, kita sepertinya masih tergagap untuk memberikan keteladanan dalam penerapan protokol kesehatan.
Di lain sisi, ada pula sebagian kecil orang yang mengambil tindakan ekstrem untuk melindungi diri dan keluarga dari risiko terinfeksi virus corona. Mereka melakukan disinfeksi rumah secara ekstensif, sehari-hari memakai masker bedah, dan selalu mengikuti perkembangan informasi soal Covid-19.
Keluarga saya sepertinya termasuk yang standar saja dalam merespons pandemi. Kami baru sekali menerima kunjungan dari famili. Itu pun tetap dengan protokol kesehatan. Semua duduk berjarak, memakai masker, dan tak bersalaman meski tangan sudah dicuci bersih.
Sehari-hari, kami beraktivitas di rumah. Suami hanya tiga hari di kantor. Ia resik sekali. Berbaju lengan panjang, pakai masker, face shield, dan bawa sajadah ke kantor. Pulang kantor langsung mandi dan membersihkan barang bawaan.
Kami harus berhati-hati, terlebih ibu punya komorbid. Meskipun sudah melakukan upaya pencegahan, kami ternyata tak sepenuhnya bebas dari ketakutan terkena Covid-19.
Hari-hari paling mencemaskan tiba mulai Selasa, 1 September 2020. Sore itu, suami mengabari hasil tes cepat (rapid test) di kantornya memperlihatkan hasil reaktif. IgG-nya positif sehingga perlu dikonfirmasi melalui uji usap cairan hidung dan tenggorokan dengan tes PCR.
Semula, saya masih bisa tenang. Toh ini rapid test, bisa jadi false positive atau ada reaksi antibodi terhadap virus lain yang terdeteksi.
Apalagi, suami sedang sumeng dan nyeri tenggorokan.
Begitu tiba di rumah, suami langsung membicarakan rencana isolasi mandiri. Saat itulah saya mulai goyah. Tak ingin rasanya berpisah. Saya takut kondisi suami tiba-tiba memburuk tanpa ada orang di dekatnya yang bisa membawanya ke rumah sakit. Terbayang happy hypoxia yang siang itu beritanya saya edit.
Di lain sisi, kondisi saya pun sedang tidak fit. Bersin berseri, hidung meler, batuk sesekali, napas pendek, dan diare sedang melanda.
Saya yakin itu cuma rhinitis alergi yang sedang kumat dan perut berontak akibat salah makan. Tetapi, suami dan ibu tak mau ambil risiko. Sahabat yang juga seorang dokter menguatkan agar saya tak ikut mengungsi ke apartemen bersama suami untuk isolasi mandiri. Saya harus di kamar sendiri dan pakai masker, sementara suami mengungsi.
Arahan berikutnya datang dari dokter senior. Beliau merekomendasikan agar kami sekeluarga swab test, bukan rapid test. Soalnya, Jakarta zona merah dan profil kesehatan anggota keluarga kami juga jadi pertimbangan.
Bukankah sekarang penularan terbanyak terjadi di rumah? Bisa saja bukan suami yang menjadi pembawa virus.
Mungkin saya atau anggota keluarga lainnya yang lebih dulu terinfeksi setelah berinteraksi dengan kurir belanja online, abang ojek daring yang membawakan makanan pesan-antar, atau dari sopir taksi yang membawa kami ke supermarket? Entahlah, padahal kami sudah pakai masker dan jaga kebersihan tangan. Tapi terkadang memang sulit membuat orang lain mau jaga jarak saat di antrean apapun.
Saya tak bisa tidur semalaman. Kembali terpikir sumber penularan, cara memberi tahu lingkungan tentang hasil tes kami nanti andaikan tak sesuai dengan harapan, hingga risiko terburuk yang mungkin terjadi. Over thinking sepertinya.
Saya lalu mencoba menyusun langkah dengan mengingat-ingat lagi pesan sang dokter. Beliau bilang, jangan ambil risiko untuk menunda swab test atau menggantinya dengan rapid test saja yang biayanya jauh lebih terjangkau.
Sebagai informasi, rapid test di rumah sakit terdekat sekitar Rp 100 ribu. Hasilnya keluar dalam dua jam. Sementara itu, swab test Rp 1,5 juta dengan hasil bisa diketahui dalam dua hari.
Rabu, 2 September, jadilah kami berempat menjalani swab test. Suami uji usapnya di rumah sakit rujukan kantornya, sementara saya, ibu, dan anak semata wayang di rumah sakit terdekat.
Masa menunggu hasil itu benar-benar membuat mental saya naik-turun, seperti naik roller coaster. Bersyukur sekali rasanya sanak famili dan sahabat terus mendampingi dari jauh. Mereka tak henti mendoakan, menanyakan kabar, menghibur, mengingatkan untuk mendongkrak imunitas, dan menawarkan vitamin serta aneka makanan yang enak-enak.
Bertemankan mereka, hati saya jadi tenang. Tak ada stigma yang saya rasakan terkait kemungkinan kami kena Covid-19.
Stigma, menurut saya, akan membuat orang yang tengah mendapatkan musibah terkait diagnosis Covid-19 ibarat jatuh lalu tertimpa tangga dan tak ada yang menolong. Sedih banget rasanya.
Ketidakpahaman masyarakat terhadap Covid-19 menjadi bibit stigma. Warga bisa memblokir jalan depan rumah orang yang keluarganya dirawat karena terinfeksi virus corona, tak mengizinkan siapapun melintas, dan takut tertular meski cuma untuk menggantungkan di pagar kantung berisi bantuan pasokan makanan untuk keluarga yang tengah isolasi mandiri.
Hari berjalan begitu lambat dalam penantian menuju terungkapnya hasil swab test. Kamis, 3 September, saya mengambil waktu untuk beristirahat total.
Setelah cukup tidur, saya mulai lebih bisa mengendalikan emosi. Rasa takut, cemas, dan tak berdaya sudah saya adukan ke Yang Maha Penyayang. Saya mencoba banyak bersyukur, apalagi tes ini untuk kebaikan semua. Lebih baik tahu dan mencari pertolongan kan daripada tidak tahu lalu ternyata positif Covid-19 dan berisiko jatuh sakit parah atau menularkannya pada orang lain.
Jumat, 4 September. Robert Pattinson, aktor pemeran utama The Batman dikabarkan positif Covid-19 di London, Inggris. Di hari yang sama, kasusnya di Indonesia bertambah 3.269. Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 pun menjadi 187.537.
Dari angka itu, 895 kasus disumbang DKI Jakarta. Mungkinkah salah satu dari kami sekeluarga termasuk di antaranya?
Suami rupanya lebih dulu mendapat hasilnya. Sebelum Zuhur, ia sudah dikabari bahwa hasil PCR-nya negatif.
Alhamdulillah wa syukurillah... Lega sekali rasanya. Tetapi, kami belum bisa kembali berkumpul. Hasil tes saya, ibu, dan anak bujang belum juga keluar.
Saya bolak-balik menelepon rumah sakit untuk menanyakan hasilnya ke bagian laboratorium. Persoalannya, nadanya sibuk melulu.
Saya masih mencoba bersabar hingga menjelang Isya. Lalu kemudian saya coba telepon lagi. Kali ini upaya saya berhasil. Bagian laboratorium berjanji akan mencarikan hasilnya dan mengirimkannya via surel.
Beberapa menit menuju pukul 20.00 WIB, satu per satu hasilnya masuk ke kotak surat elektronik.
Ibu dan anakku keduanya negatif. Bagaimana dengan saya? Alhamdulillah, sujud syukur, hasilnya juga negatif. Leganya paripurna rasanya. Suami pun bisa berkumpul kembali di rumah.
Hanya saja, hasil tes itu menunjukkan kondisi kami di tanggal 3 September. Kini, besok, atau lusa bisa saja kami tertular jika tak berhati-hati.
Sehat itu nikmat yang sangat berharga, namun terkadang tak dijaga karena terlalu yakin bahwa kita akan baik-baik saja. Saya pun terbayang horor tiga hari itu terulang lagi. Naudzubillahi min dzalik.
*) penulis adalah wartawan republika.co.id