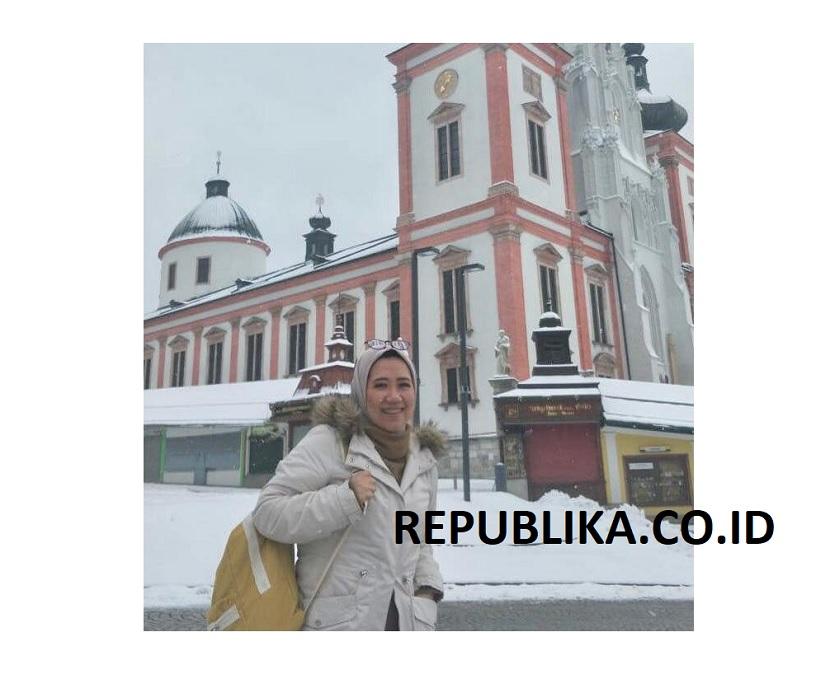REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dian Andriasari, Dosen FH Universitas Islam Bandung, PBHI Yogyakarta
“Demokrasi mestinya menjadi medium untuk mengubah nasib negara-bangsa menjadi lebih baik, dijamin segala hak sebesar-besarnya, dibuka akses seluas-luasnya menuju demokrasi subtansial, sayangnya demokrasi yang saat ini bergulir terjebak dalam riuh pesta yang dibangun di atas remang-remang antara imajinasi dan realitas”
Bermula dari Solon, seorang bangsawan dan penyair Yunani. Kisahnya kemudian ditulis setelah kematiannya, orang beramai-ramai membincangkan warisan gagasan dan pikiran-pikirannya tentang demokrasi. Sebut saja Herodotus dan Plutharkhos yang pertama-tama menuliskan tentang Solon. Meski tak banyak sumber informasi tentangnya, pelan-pelan sejarah menuliskan nama Solon dalam perbincangan ihwal demokrasi bermula.
Ia menyukai seni, menggunakannya sebagai alat propaganda, mungkin ia juga menggunakan seni sebagai medium pelariannya ketika frustasi dengan politik. Pada abad ke-6 SM ia membuat kebijakan yang menggemparkan, kebijakan yang menerabas pakem-pakem pemerintahan polis.
Kebijakan itu bermula dari krisis sosial yang bergejolak di Athena. “Wong cilik” pada masa itu terlilit utang, tak sedikit di antara mereka rela menjadi budak untuk melunasi utang-utangnya. Upah buruh seringkali dipotong, petani terperangkap dalam jerat kemiskinan hingga akhirnya mereka menjual dirinya untuk menjadi budak karena kehilangan hak atas tanahnya. Ironi, situasi kontras dipertunjukkan oleh kekuasaan, bangsawan dan ningrat menguasai perekonomian, menguasai tanah dan berkuasa di pemerintahan. (Britannica, 2021)
Perjalanan demokrasi pada masa itu meninggalkan jejak pemikiran bahwa demokrasi adalah jalan keselamatan, keberpihakan penguasa dalam membela rakyat yang tertindas. Demokrasi juga adalah alat kekuasaan dan penguasan yang dikontrol oleh rakyat, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.
Ironi Demokrasi Indonesia Hari Ini
Pemilu yang di sebut sebagai pesta demokrasi dijelang beberapa bulan lagi. Gelaran pesta demokrasi hanya mengkampanyekan ilusi-ilusi belaka, menjauhkan masyarakat dari esensi demokrasi yang sesungguhnya. Mesin politik elite menabuh gaduh.
Suara gaduh itu bermula dari ketuk palu hakim Mahkamah Konstitusi; menuai kontroversi. Arus bawah gencar melakukan penolakan dan kritik kepada lembaga yang lahir sebagai anak kandung reformasi.
Eksaminasi publik terhadap putusan digelar oleh beberapa fakultas hukum, menghadirkan banyak pakar hukum tata negara yang kompeten dan berintegritas. Sayangnya, suara perlawanan arus bawah tak mampu melawan arus kehendak kekuasaan. Ia tetap berjalan-melenggang kehilangan marwah.
Demokrasi dan segala proses yang mengitarinya tak lebih hanya hanya pendangkalan. Demokrasi justru memunculkan simplifikasi yang mereduksi proses-proses sosial termasuk politik dan hukum didalamnya.
Realitas post truth di dalamnya menghadirkan beragam perdebatan yang disuguhkan melalui televisi, medsos bahkan maraknya hoax. Inilah yang dalam pandangan Jean Baudrillard merupakan medan yang mengkondisikan khalayak ramai untuk ditarik seluruh perhatian dan konsentrasinya ke dalam sebuah medan layaknya black hole.
Ia menyebutnya Simulacra, yaitu realitas yang ada adalah realitas maya, realitas semu, realitas buatan (hyper-reality). Pantulan realitas semu itu tergambar dalam kontra narasi yang bergulir, menyamarkan kecurangan —bersembunyi dalam titah atas nama hukum.
Konsekuensi dari sebuah proses demokrasi yang “sakit” di antaranya adalah maraknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa. Kita semua mafhum inti dari paham hak asasi manusia adalah pengertian bahwa segenap kekuasaan manusia adalah terbatas.
Terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan demi menjaga kemanusiaan martabat manusia. Paham hak asasi manusia dapat dikatakan merupakan ‘grendel’ terhadap kesewenang-wenangan penguasa dengan seluruh kewenangan yang dilekatkan terhadapnya. Paham hak asasi manusia menyatakan dengan gamblang kesamaan nilai semua orang sebagai manusia. (Franz Maginis Suseno, 2010)