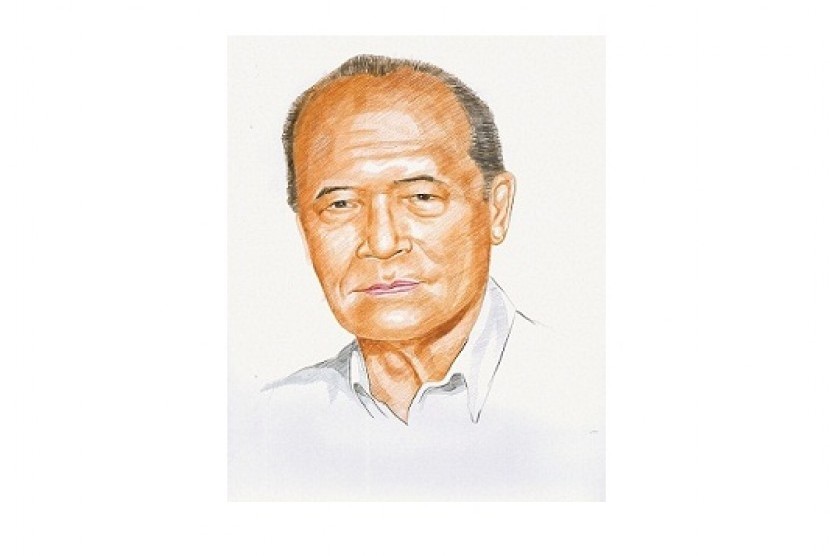REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafifi Maarif
Sebenarnya saya kurang berselera mengikuti kultur politik yang berkembang di DPR dan DPD RI, periode 2014-2019, dalam proses penentuan dan penetapan pimpinannya masing-masing. Biasanya saya memantaunya melalui siaran tv, sekalipun sepotong-sepotong, tidak utuh. Kali ini lebih banyak melalui RRI Pro 3 yang didengar sambil tiduran, tidak serius. Dalam sistem pemilihan pimpinan, kultur yang berkembang di DPD lebih beradab dibandingkan dengan apa terjadi di DPR yang brutal. Bahwa di lingkungan DPD juga berlaku persaingan ketat untuk berebut palu pimpinan, adalah lumrah belaka, tetapi di DPR yang dikuasai oleh partai-partai pendukung KMP (Koalisi Merah Putih), iklim balas dendam amat menonjol, sesuatu yang tidak terasa di lingkungan DPD, karena memang berasal dari unsur independen, sekalipun sebagian adalah mantan tokoh partai. Suasana di DPR menunjukkan bahwa slogan: siap kalah, siap menang, barulah sebatas slogan. Di DPD, suasananya memang lebih tenang, karena daya tarik dan kiprah para senatornya selama ini kurang mendapat perhatian publik.
Di antara partai yang bermain di DPR lama dan baru, PD (Partai Demokrat) adalah yang paling tidak jelas kelaminnya, tetapi berlindung di bawah slogan ‘penyeimbang.’ Kultur politik yang berlaku dalam partai ini sangat ditentukan oleh karakter pimpinan puncaknya yang selalu memantau ke mana arah angin bertiup. Ibarat seorang sutradara, tokoh puncak ini memang sangat piawai dalam memainkan kartu politiknya, tetapi pengamat yang jeli gampang saja membacanya. Tetapi PDI-P sebagai pemenang pilpres memang kurang lihai dalam menjalin komunikasi politik dengan parpol lain. Mungkin para politisinya terhalang oleh dinding sejarah masa lalu yang sulit ditembus.
Kembali ke PD. Sikap walk-out saat memperdebatkan RUUMD3 di DPR, periode 2009-2014, anak buahnya berkilah bahwa semuanya itu adalah inisiatifnya sendiri, bukan berasal dari sutradara. Tak ubahnya seperti burung onta yang menyembunyikan kepalanya dalam pasir, sementara tubuh dan ekornya dibiarkan nongkrong di luar. Tetapi inilah politik dalam iklim peradaban yang masih rendah yang dikemas dalam serba kesopanan dan dalam budaya saling menutup. Anas Urbaningrum, mantan ketua umum PD, banyak bercerita kepada saya tentang partai ini dan sang sutradara. Sayangnya, cerita itu disampaikan di saat posisinya sudah terancam. Sebelumnya Anas juga tidak kurang gigihnya dalam membela mentornya itu. Teman dalam politik kekuasaan jarang yang berumur panjang, kecuali jika diikat dan direkat oleh sebuah ideologi yang serius dan mantap. Di Indonesia sekarang ini, apa yang bernama ideologi itu sudah dijadikan barang mainan. Rapuh sekali. Orang berpindah partai sama saja seperti berganti pakaian.
Sebenarnya brutalitas di DPR belum tentu akan berlangsung sedemikian garang dan gaduh, sekiranya Jokowi sejak awal mau membuka pintu untuk melakukan politik transaksional, sesuatu yang memang harus dihindarinya, demi mengubah kultur politik Indonesia yang sarat dosa dan dusta selama ini. Bukankah DPR selama ini dikenal sebagai salah satu lembaga tinggi negara, tempat bersarangnya para koruptor, yang ketahuan atau yang belum ketahuan? Bagaimana perjalanan ke depan, tentu sulit kita katakan sekarang. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu pemihakan total kepada kepentingan rakyat banyak yang jarang terwakili di Senayan dan memang telah terabaikan selama puluhan tahun. Jokowi-JK tidak perlu cemas benar menghadapi kepungan dari kiri-kanan, dari berbagai jurusan, selama pemerintahannya benar-benar berjalan di atas rel konstitusi, demi mewujudkan janji-janji kemerdekaan yang terbengkalai lantaran cekcok politik berkepanjangan yang sering benar mendera dan mencederai republik ini.