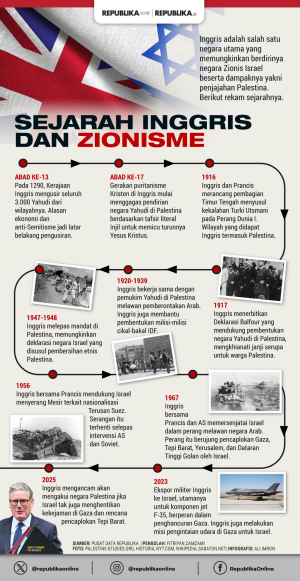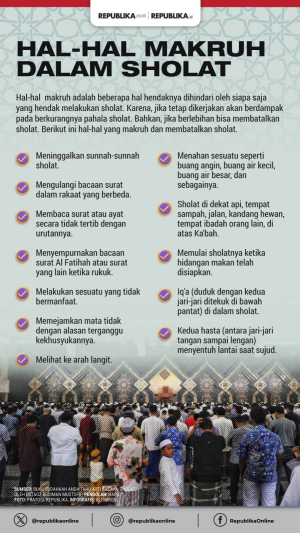REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mengatakan, ada beberapa kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah berkaitan dengan kepentingan pemilihan kepala daerah (pilkada). Mulai dari kebutuhan yang legal seperti modal kampanye maupun tindakan melanggar hukum misalnya jual beli suara dan mahar politik dari kepala daerah kepada partai politik.
"Memang ada beberapa kasus yang menunjukkan adanya irisan antara korupsi kepala daerah dan kebutuhan atau kepentingan pemenangan pilkada," ujar Almas dalam konferensi nasional daring, Kamis (15/10).
Ia menyebutkan, setidaknya ada 11 kasus korupsi yang berhubungan dengan kontestasi pilkada per 2018. Misalnya kasus korupsi yang dilakukan mantan wali kota Cimahi, Atty Suharti dan suaminya yang juga wali kota Cimahi Itoc Tohija.
Bahkan, dalam putusan atau dakwaan jaksa disebutkan tertulis, tindakan korupsi yang dilakukan keduanya untuk kepentingan persiapan modal pilkada. Atty mengumpulkan uang untuk modal pilkada dari korupsi proyek infrastruktur yang dikerjakan di daerahnya.
Almas mengatakan, ongkos politik yang sangat tinggi untuk mengikuti pilkada memang sering disebut sebagai faktor utama kepala daerah melakukan korupsi. Menurutnya, untuk biaya legal seperti dana kampanye, biaya saksi, dan lainnya masih bisa dibenahi dengan pembentukan regulasi yang tepat.
Sementara, untuk biaya ilegal seperti mahar politik maupun jual beli suara atau politik uang menjadi persoalan yang tidak mudah diatasi. Mahar politik ini dimainkan oleh partai politik yang meminta dana kepada calon yang ingin maju dalam pilkada melalui partainya.
"Bahkan banyak juga bakal calon kepala daerah yang terpaksa tidak dicalonkan karena tidak sanggup memberikan mahar politik," kata Almas.
Dengan demikian, biaya politik tidak menjadi satu-satunya faktor yang mendorong kepala daerah korupsi. Ada masalah yang beririsan dengan partai politik, mulai dari tuntutan pendanaan partai sehingga marak terjadi mahar politik dan kandidasi yang buruk.
Selain itu, hukuman kepala daerah yang tidak berdaya cegah dan minim efek jera. Kajian ICW pada 2019 terhadap 104 kasus korupsi oleh kepala daerah yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), rata-rata vonis hukuman hanya enam tahun empat bulan.
"Ini masih jauh dari vonis yang tinggi, yang maksimal, padahal masih bisa divonis lebih tinggi," tutur Almas.
Padahal, lanjut dia, ada kasus dengan kerugian negara yang sangat tinggi, tetapi hukuman yang diberikan kepada kepala daerah rendah. Contohnya, kasus korupsi oleh Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna Abdul F yang merugikan negara Rp 346 miliar dan kasus korupsi Bupati Siak, Arwin AS yang merugikan negara Rp 301 miliar, tetapi keduanya hanya mendapatkan vonis empat tahun penjara.
Kemudian dilihat dari nilai suap yang tinggi seperti dilakukan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho sebesar Rp 61 miliar mendapatkan vonis hanya tiga tahun. Bupati Empat Lawang Budi Antoni yang melakukan suap senilai Rp 15 miliar, tetapi vonisnya hanya empat tahun.
Di samping itu, minimnya pengawasan internal pemerintah daerah yang semestinya dilakukan DPRD dan publik. Akan tetapi, akses informasi pemerintah daerah kepada publik sebagai upaya transparansi sering menjadi perdebatan.
"Publik hanya bisa efektif mengawasi kalau publik bisa mengakses informasi yang cukup, yang lengkap dari pemerintah daerah," tutur Almas.

![Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mengatakan, ada beberapa kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah berkaitan dengan kepentingan pemilihan kepala daerah (pilkada).[Ilustrasi kepala daerah korupsi]](https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/kepala-daerah-korupsi-ilustrasi-_181218221031-305.png)