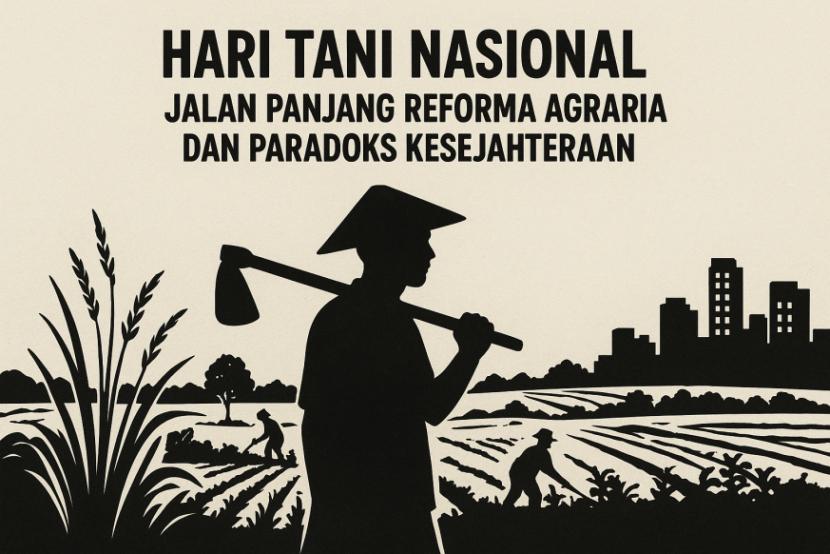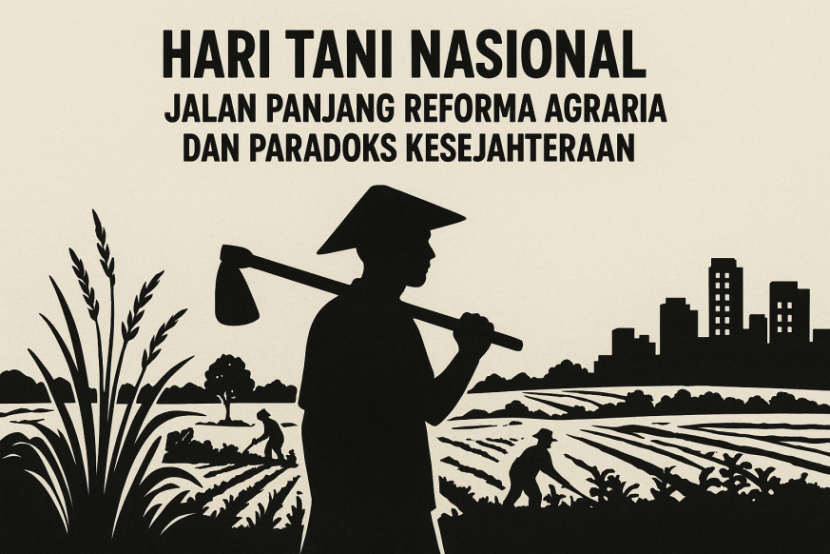
Oleh: Ricco Andreas (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Penggiat Pusat Kajian Hukum Sriwijaya)
Setiap tanggal 24 September, bangsa Indonesia memperingati “Hari Tani Nasional”. Tepat 65 tahun bukan angka yang muda lagi, peringatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk menengok kembali sejarah panjang perjuangan petani dalam memperjuangkan hak atas tanah. Sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, cita-cita besar reforma agraria adalah mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan penguasaan tanah. Namun, setelah lebih dari enam dekade, cita-cita tersebut masih jauh dari harapan. Yang muncul justru paradoks: negara agraris dengan tanah subur, namun petani masih hidup dalam bayang-bayang kemiskinan dan konflik agraria yang tak kunjung reda.
Makna Reforma Agraria
UUPA 1960 lahir dalam semangat anti-feodalisme dan anti-kolonialisme. Hukum agraria kolonial warisan Belanda dianggap menindas rakyat kecil karena lebih berpihak pada kepentingan perusahaan perkebunan besar dan modal asing. Reforma agraria dimaknai sebagai penataan ulang struktur kepemilikan tanah, agar setiap warga negara, khususnya petani, memperoleh akses yang adil. Dengan begitu, petani dapat menggarap lahan, meningkatkan produksi pangan, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan.
Namun, perjalanan panjang itu penuh lika-liku. Program redistribusi tanah berjalan lambat, bahkan terhenti pada masa Orde Baru. Alih-alih menyejahterakan petani, kebijakan agraria lebih berpihak pada kepentingan investasi dan pembangunan skala besar. Akibatnya, kesenjangan penguasaan tanah semakin melebar hingga hari ini.
Negara Agraris dan Paradoks Kesejahteraan
Indonesia sering disebut negara agraris. Hasil Sensus Pertanian 2023 mencatat jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 25.122.642 rumah tangga, sementara jumlah rumah tangga petani tercatat 27.368.114 rumah tangga dan bagian besar di antaranya adalah petani gurem (pemilik lahan sempit).
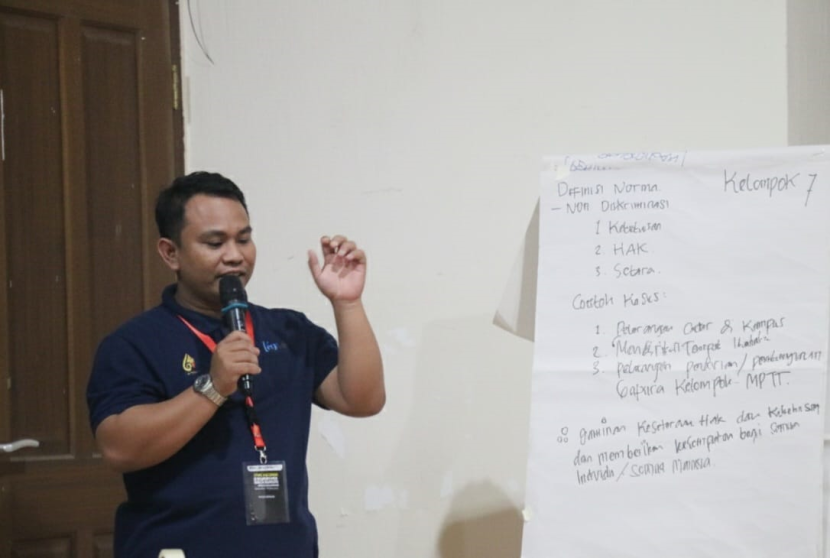
Secara teori, keberadaan jutaan rumah tangga petani ini semestinya menjadi kekuatan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Namun kenyataannya banyak petani tetap hidup rentan; paradoks itu semakin jelas melihat praktik di lapangan: meski tanah luas dan subur, impor sejumlah komoditas pangan masih terjadi dan alih fungsi lahan pertanian terus berlangsung. Misalnya, pada awal 2025 Indonesia masih mencatat impor beras (volume menurun dibanding tahun sebelumnya tetapi masih terjadi di awal tahun).
Di Sumatera Selatan, alih fungsi lahan pertanian menjadi isu serius yang mencerminkan paradoks pembangunan. Data terbaru menunjukkan penyusutan lahan baku sawah dari sekitar 621 ribu hektar menjadi hanya 470 ribu hektar. Angka ini menandakan ribuan hektar sawah produktif telah berubah fungsi, baik menjadi kawasan permukiman, proyek infrastruktur, maupun aktivitas industri. Tekanan urbanisasi dan ekspansi pembangunan kota membuat lahan pertanian kian terdesak, padahal sawah adalah penopang utama ketahanan pangan daerah.
Ironisnya, Sumatera Selatan justru memiliki potensi lahan baru yang sangat besar. Wilayah rawa pasang surut dan rawa lebak diperkirakan mampu mendukung pencetakan sawah baru hingga 1,3 juta hektar. Pemerintah daerah bahkan menargetkan pencetakan sawah puluhan ribu hektar sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan nasional. Upaya ini diharapkan bisa menutup celah dari berkurangnya sawah eksisting akibat konversi lahan.
Kondisi ini memperlihatkan dua wajah Sumatera Selatan: di satu sisi memiliki peluang besar untuk menjadi lumbung pangan melalui pemanfaatan lahan rawa; di sisi lain harus menghadapi ancaman berkurangnya sawah produktif akibat alih fungsi. Paradoks ini menuntut kebijakan agraria yang konsisten agar pembangunan tidak mengorbankan ketahanan pangan jangka panjang.
Fenomena-fenomena lain, yaitu tingginya proporsi petani gurem, alih fungsi lahan yang menggerus areal produktif, dan ketergantungan pada impor beberapa komoditas menjelaskan mengapa negara yang disebut agraris masih menghadapi paradoks kesejahteraan: potensi produksi besar tidak otomatis diterjemahkan ke dalam kesejahteraan petani dan kemandirian pangan tanpa kebijakan penataan ruang, perlindungan sawah, dan dukungan kepada petani skala kecil. Upaya pemerintah untuk memperkuat stok dan kedaulatan peningkatan cadangan beras BULOG yang dilaporkan mencapai jutaan ton pada 2025 adalah langkah mitigasi, tetapi tantangan struktural bagi petani gurem tetap nyata.

Konflik Agraria: Luka yang Terus Menganga
Salah satu ironi terbesar dalam perjalanan reforma agraria adalah konflik agraria yang terus meningkat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sepanjang tahun 2024 terjadi 295 letusan konflik agraria, naik 21% dibandingkan tahun sebelumnya. Luas lahan yang terdampak mencapai 1,1 juta hektare dengan korban sekitar 67 ribu keluarga. Sektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar konflik, khususnya perkebunan sawit. Infrastruktur juga menjadi penyebab utama, termasuk pembangunan jalan tol, bendungan, dan kawasan industri.
Jika ditarik lebih panjang, sejak 2015 hingga 2023 terdapat 2.939 konflik agraria dengan total lahan sekitar 6,3 juta hektare, melibatkan lebih dari 1,7 juta rumah tangga. Angka ini menunjukkan bahwa setiap tahun ribuan keluarga petani terjebak dalam ketidakpastian, kehilangan tanah garapan, bahkan menjadi korban kriminalisasi.
Data KPA 2024 juga mencatat sekitar 93 ribu petani menjadi korban langsung konflik, baik melalui penggusuran, penganiayaan, maupun kriminalisasi. Tragisnya, ada kasus di mana konflik berujung pada kematian.
Reforma Agraria: Janji Manis Sang Penguasa
Pemerintah sebenarnya memiliki program besar melalui reforma agraria 9 juta hektare. Rinciannya: 4,5 juta hektare untuk legalisasi aset, dan 4,5 juta hektare untuk redistribusi tanah. Namun, hingga akhir 2023, capaian redistribusi baru sekitar 379 ribu hektare, atau hanya 9% dari target. Sementara itu, legalisasi aset berjalan lebih cepat, padahal redistribusi tanah adalah inti reforma agraria yang sejati.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: apakah reforma agraria benar-benar dijalankan untuk petani kecil, atau justru sekadar formalitas administrasi? Alih-alih memperkuat posisi petani, kebijakan sering kali justru memperkuat legalitas perusahaan besar melalui skema sertifikasi tanah.
Dalam konteks pembangunan, isu swasembada pangan kembali mencuat. Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada 1984, sebuah capaian monumental yang diakui dunia. Namun, ketergantungan pada impor kembali meningkat sejak 1990-an hingga kini.

Hari Tani Nasional seharusnya menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa kedaulatan pangan tidak bisa dilepaskan dari kedaulatan agraria. Jika sawah terus digusur untuk proyek infrastruktur dan industri, maka swasembada hanya menjadi slogan kosong. Reforma agraria sejati harus menempatkan petani sebagai aktor utama pembangunan, bukan korban pembangunan.
Alih fungsi sawah menjadi salah satu isu paling serius. Proyek strategis nasional sering kali menempatkan petani pada posisi yang lemah. Sawah-sawah produktif digusur demi kawasan industri, jalan tol, atau perkebunan skala besar. Petani yang tergusur jarang mendapat kompensasi layak, bahkan sebagian besar terjebak dalam kemiskinan baru karena kehilangan mata pencaharian.
Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks kesejahteraan agraria. Pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan justru memiskinkan sebagian petani. Negara menghadapi dilema antara mendorong investasi dan menjaga keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan petani.
Refleksi Hari Tani Nasional
Peringatan Hari Tani Nasional bukan sekadar mengenang sejarah lahirnya UUPA 1960. Lebih dari itu, ini adalah ajakan untuk refleksi kolektif. Pertama, bahwa reforma agraria masih menjadi agenda penting yang belum tuntas. Kedua, kesejahteraan petani tidak bisa dilepaskan dari akses yang adil terhadap tanah. Ketiga, pembangunan harus diletakkan dalam kerangka keadilan ekologis dan keberlanjutan.
Indonesia memang sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada dorongan kuat untuk menarik investasi besar-besaran. Di sisi lain, ada mandat konstitusi untuk menyejahterakan rakyat, termasuk petani. Jalan panjang reforma agraria tidak boleh berhenti pada retorika atau sertifikasi belaka. Ia harus diwujudkan melalui distribusi tanah yang adil, perlindungan lahan pertanian, dan keberpihakan pada petani sebagai tulang punggung bangsa.
Hari Tani Nasional adalah cermin perjalanan panjang bangsa ini dalam menata tanah dan kehidupan petani. Sejarah, konflik, dan paradoks yang menyertainya memberi pelajaran penting: tanpa reforma agraria sejati, kesejahteraan petani hanya akan menjadi janji yang tak pernah ditepati. Saatnya negara menempatkan petani bukan sekadar sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang berdaulat. Karena pada akhirnya, “kedaulatan pangan hanya bisa lahir dari kedaulatan agraria”. ●