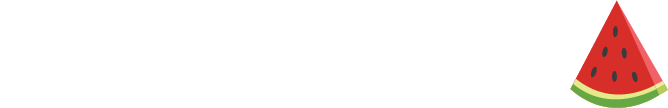REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kirgistan adalah negara kecil berbentuk republik di kawasan Asia Tengah, yang pernah berada di bawah kekuasaan Uni Soviet. Negara ini berbatasan langsung dengan Cina, Tajikistan, Uzbekistan, dan Kazakhstan. Mayoritas penduduk Kirgistan adalah pemeluk Islam.
Berdasarkan sensus terakhir pada tahun 2007, jumlah penduduk Kirgistan mencapai 5,5 juta orang. Dan sekitar 80 persen penduduknya beragama Islam, 18 persen berafiliasi dengan Gereja Ortodoks Rusia, dan dua persen sisanya penganut Yahudi dan keyakinan lainnya.
Meski pemeluk Islam mendominasi, namun Pemerintah Kirgistan termasuk keras dan tegas terhadap warga Muslim. Seperti kebijakan yang diambil Pemerintah Kirgistan awal 2010 lalu; Pemerintah Kirgistan mengeluarkan undang-undang baru yang membatasi kegiatan kehidupan beragama di sana.
Banyak pihak yang meyakini undang-undang tersebut sengaja diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk memaksakan pandangan tentang agama tertentu pada masyarakat dan targetnya adalah komunitas Muslim.
Undang-undang yang baru dikeluarkan ini mewajibkan kelompok-kelompok keagamaan, baik yang sudah resmi (legal) maupun belum, untuk mendaftarkan organisasinya. Berdasarkan peraturan tersebut, sebuah organisasi keagamaan harus memiliki anggota sedikitnya 200 orang sebelum dinyatakan boleh beroperasi oleh pemerintah.
Undang-undang itu juga melarang distribusi literatur, baik dalam bentuk cetak, audio, atau rekaman video keagamaan di tempat-tempat umum, sekolah-sekolah, dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi.
Para pemuka agama di Kirgistan mengungkapkan keberatannya atas pemberlakuan undang-undang ini. Mereka menilai keberadaan undang-undang tersebut menindas kehidupan beragama di sana.
Seorang pemuka Islam di Kirgistan, Kadyr Malikov, menyatakan undang-undang ini menyulitkan gerakan-gerakan Islam dan komunitas Muslim di Kirgistan. Di samping itu, ia juga menilai isi undang-undang itu terlalu berlebihan dan menimbulkan kesan bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan seakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi Kirgistan.
“Orang-orang di pemerintahan tidak bisa membedakan antara ajaran dan tradisi Islam yang damai dengan ekstremis. Tentunya ini akan mempersulit kami jika ingin membangun madrasah atau masjid baru dan (juga) mempersulit hubungan antara pemerintah yang sekuler dengan komunitas Muslim,” papar Malikov seperti dikutip laman Islamonline.